Oleh: Jean Loustar Jewadut
Mahasiswa STFK Ledalero, Anggota Kelompok Diskusi Centro John Paul II, Tinggal di Ritapiret
Pada tahun politik ini, atensi banyak pihak terarah pada diskursus seputar peran cendekiawan di ruang publik. Namun, jauh sebelumnya, para filsuf Yunani kuno telah berbicara banyak tentang peran cendekiawan dalam sebuah bangunan negara.
Sejumlah filsuf Yunani kuno memiliki perspektif yang positif tentang cendekiawan. Plato dan Aristoteles pernah mengemukakan fungsi edukatif negara yang berkuasa sebagai penegak moral individu-individu.
Dalam rangka menjamin moral individu, maka negara harus dipimpin oleh seorang cendekiawan, dalam hal ini adalah filsuf. Bagi Plato, hanya filsuf yang dapat melihat persoalan kehidupan sebenarnya.
Metode berpikir abstrak, holistik, universal, dan radikal merupakan sebuah conditio sine qua non dalam memimpin negara menuju ke arah yang lebih baik.
Filsuf dapat membuat distingsi antara kebaikan dan keburukan. Dia mampu meyakinkan massa untuk lebih berpihak pada kebenaran dan kebaikan.
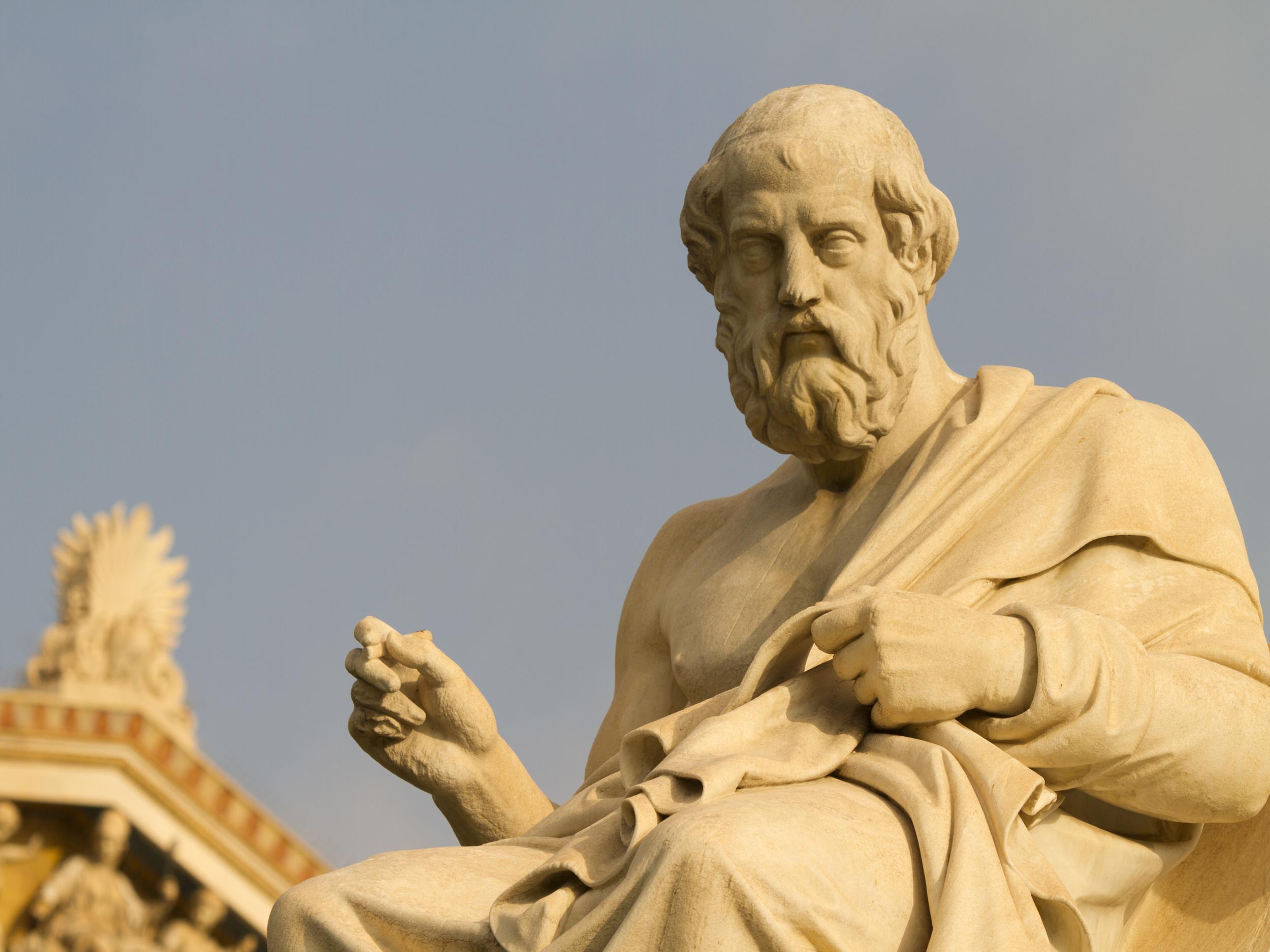
Filsuf juga dapat melihat nilai-nilai yang abadi (Ilahi) karena filsuf adalah seorang yang mampu ber-theoria. Bagi Aristoteles, seperti juga Plato, kata theoria tidak dipahami sebagai teori dalam pengertian modern.
Orang Yunani memahami theoria sebagai upaya untuk memandang dan merenungkan realitas yang abadi yaitu realitas Ilahi. Dengan ber-theoria, seorang filsuf bisa mengakrabkan diri dengan kebijaksanaan.
Dalam konteks dunia modern, pertimbangan apakah seorang cendekiawan harus memimpin sebuah negara juga menuai pro dan kontra.
Dalam diskursus seputar filsafat politik, dikenal adanya legitimasi eliter selain legitimasi religius dan legitimasi demokratis. Legitimasi eliter memberikan kekuasaan hanya kepada kelompok elit (entah karena turunan, kasta, kepandaian, maupun ideologi).
Bentuk tradisional kekuasaan menurut legitimasi eliter disebut sebagai aristokrasi (seperti yang disinggung Plato dan Aristoteles pada zaman Yunani kuno) dan bentuk modern kekuasaan menurut legitimasi eliter disebut sebagai teknokrasi yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh para ahli.
Legitimasi teknokratis optimis bahwa keahlian-keahlian yang dimiliki oleh seseorang menjadi modal berharga yang membuatnya bisa menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam sebuah negara.
Keahlian-keahlian, menurut perspektif teknokrasi, dipandang sebagai syarat utama bagi terwujudnya negara yang sejahtera. Namun, reaksi kontra terhadap teknokrasi pun bermunculan.
Basis argumentasi pihak kontra adalah sifat keahlian terbatas, dan karena aspek keterbatasan tersebut, sebuah keahlian tertentu tidak dapat menyelesaikan secara tuntas kompleksitas masalah dalam sebuah negara.
Para ahli dibutuhkan hanya untuk memberikan sumbangan pikiran tentang bagaimana cara-cara yang harus ditempuh untuk memimpin sebuah negara demi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Harapan
Dalam masyarakat, cendekiawan adalah kelompok masyarakat yang memiliki identitas khusus yang membedakannya dari kalangan masyarakat yang lain.
Menurut Jean-Francois Lyotard, seorang filsuf Prancis kontemporer, cendekiawan memiliki kekuatan intelektual yang memampukannya untuk membedakan benar-salah, baik-buruk, dan bernilai-tidak bernilai. Kalangan masyarakat yang lain menaruh harapan penuh kepada para cendekiawan agar kehadiran dan peran mereka di tengah masyarakat sungguh-sungguh menghadirkan pencerahan konsepsional, pencerahan persepsi, dan pencerahan argumentasi.
Kalangan masyarakat lain menilai para cendekiawan memiliki suara kenabian untuk menyuarakan kebenaran di tengah gempuran hoaks yang datang silih berganti.
Penilaian semacam ini sesungguhnya menjadikan kaum cendekiawan sebagai agen pembentuk opini publik. Sebagai agen pembentuk opini publik, cendekiawan harus selalu menyuarakan kebenaran dan berbuat kebaikan.
Kebenaran dan kebaikan harus menjadi pilihan utama para cendekiawan. Kebenaran berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat dimengerti (intelligibiltas), sedangkan kebaikan berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat dikehendaki (apetibilitas).
Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan diharapkan para cendekiawan memiliki komitmen untuk memasyarakatkan hubungan tersebut.
Para cendekiawan diharapkan mampu mengerti secara baik realitas hidup masyarakat sehingga mampu menyuarakan kebenaran dan selanjutnya merancang perbuatan-perbuatan manusiawi sebagai respon konstruktif untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang dialami oleh masyarakat.
Cendekiawan sejati tidak pernah berbangga karena memiliki sejumlah informasi dan pengetahuan yang luas tentang topik-topik tertentu. Cendekiawan perlu menjaga keseimbangan antara intelektualisme dan rasionalitas.
Rasionalitas berkaitan dengan kemampuan setiap orang untuk bertanya dan mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi. Hal ini berbeda dengan intelektualisme yaitu keadaan di mana seseorang mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik-topik tertentu.
Ignas Kleden membuat sebuah contoh yang menarik tentang intelektualisme dan rasionalitas. Seorang petani yang mempunyai informasi yang terbatas tentang ilmu pertanian tetapi mampu bernalar untuk memperganda hasil pertaniannya, tentunya jauh lebih rasional ketimbang seorang mahasiswa atau cendekiawan yang mempunyai banyak informasi ilmiah, tetapi tidak mampu memanfaatkan atau menggunakan informasinya tersebut demi pelayanan publik.
Tidak dapat disangkal bahwa cendekiawan tentu saja memiliki banyak perbendaharaan infomasi dan pengetahuan di otak, namun rasionalitas perlu terus-menerus dikembangkan, dengan mengolah secara kritis segenap kenyataan dan informasi yang berhubungan dengan nasib rakyat.
Rasionalitas berhubungan dengan pengolahan lebih lanjut yang diperoleh secara efektif dan efisien di kampus maupun dari hasil belajar pribadi demi kepentingan transformasi sosial politik.
Pendekatan privatisme Epikurus yang dibangun atas basis argumentasi bahwa orang, untuk bisa bahagia, harus menarik diri dari urusan publik dan mengembangkan diri dalam lingkungan akrab teman sealiran mesti dijauhi oleh para cendekiawan.
Pendekatan yang mesti menjadi pijakan filosofis untuk diinternalisasi oleh para cendekiawan adalah pendekatan sosialitas Aristoteles yang menegaskan bahwa kebahagiaan manusia sebagai makhluk sosial terletak pada keterlibatan dan tanggung jawab sosialnya untuk menciptakan progresivitas masyarakat.
Dalam bahasa yang lebih lumrah didengar yaitu para cendekiawan tidak boleh mengurung diri dalam menara kampus karena merasa puas dengan perolehan IPK dan gelar-gelar atau pangkat-pangkat akademik.
Kiprah cendekiawan di tengah masyarakat mesti dilandasi oleh kebijaksanaan, kebenaran, keadilan, dan keberpihakan pada martabat luhur manusia.
Peran etis dan sosial-politis cendekiawan adalah salah satu jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan yang dulu pernah dilontarkan oleh Imanuel Kant: Apa yang harus saya lakukan? sebagai reaksi terhadap realitas destruktif yang menyengsarakan masyarakat.
Cendekiawan selalu dipanggil dan diharapkan keterlibatannya di dalam berbagai persoalan kehidupan politik karena kehidupan politik inilah yang menentukan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pribadi keluarga umat manusia.
Hal yang mesti dilakukan oleh cendekiawan adalah menyerukan berbagai praktik ketidakadilan yang menodahi keluhuran martabat manusia, memposisikan mereka yang dipinggirkan ke pusat perhatian publik, memberikan konsientisasi (penyadaran) bagi masyarakat yang kurang sadar bahwa mereka sedang dijajah oleh pemimpin dan regulasi yang tidak pro rakyat, mengikuti dan mengevaluasi kinerja pemimpin yang berkuasa, mengkritisi berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin, dan mengontrol jalannya sebuah pemerintahan.
Hal ini penting karena dalam konteks negara demokrasi, selalu ada kontrol terhadap pemimpin.
Segala kebijakan yang diambil dan program yang dilakukan oleh pemimpin dapat langsung diamati oleh masyarakat secara langsung atau melalui media massa.
Cendekiawan Boneka
Beberapa waktu lalu, dikeluarkan pernyataan dan seruan yang ditanda tangani oleh 106 cendekiawan Indonesia di Jakarta tentang “Menolak Pemiskinan dan Pembusukan Filsafat di Ruang Publik”.
Pernyataan dan seruan ini tentu lahir dari kegelisahan melihat ulah sejumlah cendekiawan yang menjadikan filsafat sekadar sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan pragmatis.
Filsafat yang mengajarkan orang untuk mencintai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksaan kehilangan jati dirinya sebagai akibat dari kiprah salah kaprah sejumlah cendekiawan.
Filsafat yang mengutamakan rasionalitas kritis dalam membaca realitas masyarakat menjelma menjadi rasionalisasi sehingga kebohongan yang disampaikan berulang kali di tempat yang berbeda-beda seolah-olah menjadi kebenaran yang mendapat legitimasi publik.
Kenyataan miris seperti ini menimbulkan kegalauan akademis di kalangan masyarakat lain yang menaruh kepercayaan kepada para cendekiawan sebagai agen yang memberikan pencerahan publik.
Keterlibatan politis sejumlah cendekiawan menjelang pesta demokrasi tahun ini menjadi sorotan utama publik. Betapa tidak, sejumlah acara di layar kaca menampilkan diskusi dan debat para cendekiawan baik yang mempunyai jabatan politik maupun yang berada di luar lingkaran kekuasaan.
Tentang keberhadapan para cendekiawan dengan kekuasaan, ada dua pandangan yang berbeda. Pertama, pandangan yang dipelopori oleh Julien Benda, filsuf Prancis. Menurut Benda, para cendekiawan tidak boleh melibatkan diri dalam kekuasaan. Posisi utama para cendekiawan adalah di luar kekuasaan. Dengan berada di luar kekuasaan, menurut Benda, para cendekiawan dengan bebas mengontrol dan mengkritik kekuasaan.

Kedua, pandangan yang dipelopori oleh Antonio Gramsci, filsuf Italia. Berbeda dengan Benda, Gramsci berpendapat bahwa para cendekiawan diharapkan keterlibatannya dalam kekuasaan.
Keterlibatan secara langsung dalam kekuasaan harus selalu disertai oleh komitmen untuk bersahabat dengan kebenaran dan mengusahkan kebaikan.
Menurut saya, entah terlibat langsung dalam kekuasaan ataupun berada di luar sistem kekuasaan, para cendekiawan tetap memiliki potensi untuk mengkhianati identitas keintelektualannya dengan memilih menjadi cendekiawan boneka.
Dalam konteks dunia Yunani Kuno, pada abad 5 SM, identitas cendekiawan boneka hadir secara nyata dalam diri para sofis yang terampil beretorika untuk memberikan pengajaran pada masyarakat zaman itu. Sialnya, argumentasi yang diutarakan oleh para sofis adalah argumentasi manipulatif dan diungkapkan dalam rangka memperoleh bayaran dari pihak yang menggunakannya.
Hampir semua orang tentu pernah membaca, mendengar, dan menonton film tentang pinochio. Kisah tentang pinochio adalah sebuah kisah inspiratif dan sarat makna.
Pinochio (sebuah patung kayu yang menjadi manusia) adalah dongeng anak-anak yang secara implisit mengisahkan tema tentang kejujuran dan kesetiakawanan. Pinochio adalah sebuah patung hasil karya seorang pemahat hebat.
Patung itu sangat mirip dengan manusia, sehingga pemahatnya menginginkan agar pinochio menjadi seorang manusia. Singkat cerita, seorang peri menghembuskan nafas ke patung itu dan jadilah pinochio. Tetapi, hidup pinochio berada di bawah perintah si peri. Pinochio harus setia mematuhi perintah si peri agar tidak dikembalikan menjadi patung kayu. Lalu, apa hubungan antara kisah pinochio dengan cendekiawan boneka?
Eksistensi seorang cendekiawan boneka mirip dengan kisah pinochio. Seorang cendekiawan boneka selalu berada di bawah perintah sekelompok orang yang lebih berpengaruh.
Sekelompok orang tersebut mengharuskan cendekiawan tertentu untuk membangun argumentasi yang rasional dan sistematis seturut kemauan mereka yang tentunya akan mendatangkan keuntungan tertentu bagi mereka.
Jika demikian adanya, maka sebuah konklusi sederhana yaitu terjadinya pengkhiantan intelektual dan perendahan akal sehat di mana akal sehat diinstrumentalisasi sedemikian rupa oleh cendekiawan hanya untuk pemenuhan kepentingan pihak yang membayarnya entah dalam bentuk apa saja.
Cendekiawan boneka ada di sekitar kita. Senjata untuk melawan mereka adalah berpikir kritis terhadap argumentasi-argumentasi yang diutarakan dan menguji kebenaran arguementasi-argumentasi tersebut dengan argumentasi-argumentasi dari buku maupun dari cendekiawan-cendekiawan lain yang masih bersedia mengabdi bukan pada kekuasaan, melainkan pada kebenaran, kebaikan, dan kebijaksaan.


