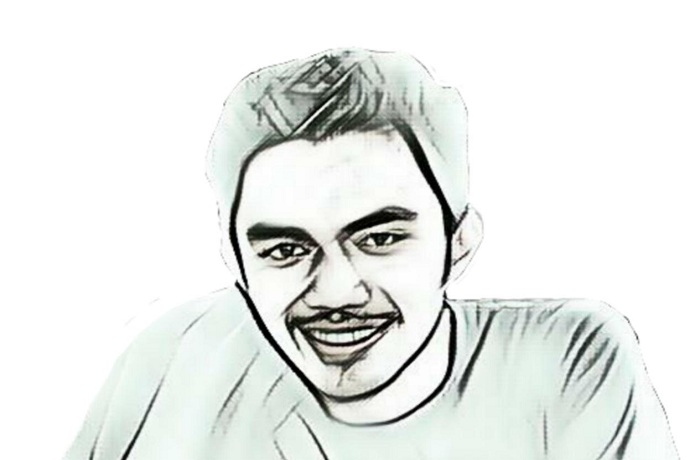Oleh: Dedi Harsali*
Artikel singkat ini merupakan tanggapan atas tulisan dari saudara Donatus Vedin yang dimuat di VoxNtt.com (05/04/2019).
http://fuq.zqc.mybluehost.me/2019/04/05/cek-baik-baik-belis-mahal-justru-menegaskan-budaya-konsumtif-kita/43823/
Tanggapan ini didasari oleh tinjauan saya dalam kebudayaan Manggarai yang berkaitan dengan belis (paca).
Saudara Donatus Vedin mengatakan bahwa “belis mahal” justru menegaskan budaya konsumtif kita. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan dari saya, “adakah orang yang kaya karena belis”?
Menurut saya, belum ada fakta yang menunjukkan bahwa seseorang bisa kaya karena belis.
Penulis mencoba menuangkan tulisan tanggapan ini berlandaskan pengalaman (empiris) penulis yang pernah ikut dan berpartisipasi dalam acara bertemunya kedua keluarga besar ( cumang cama tu’a) sebelum melangsungkan pernikahan.
Tulisan ini juga didukung dengan materi kuliah “Budaya Daerah” yang pernah diikuti penulis sewaktu menempuh pendidikan strata satu di STKIP St. Paulus Ruteng satu tahun silam.
Dalam artikel saudara Donatus, belis berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan seperti apa yang saudara maksud? Pernikahan sesungguhnya ada 2 (dua) bentuk, ada pernikahan adat (némpung atau wagal) ada pula pernikahan menurut gereja katolik.
Sejauh yang saya tahu dalam kebudayaan Manggarai, belis selalu dikaitkan dengan pernikahan adat. Tetapi, dalam tulisan saudara Donatus, tidak dijelaskan secara spesifik berkaitan dengan hal ini.
Pernikahan adat adalah pernikahan tahap pertama dalam masyarakat adat Manggarai. Pernikahan adat ini sudah ada sebelum agama Katolik masuk ke tanah Manggarai.
Dalam tradisi masyarakat Manggarai, untuk membentuk atau membangun suatu keluarga baru perlu melewati proses yang panjang. Yang menjadi ciri khas dari proses ini adalah dengan adanya mas kawin (paca). Mas kawin itulah yang menjadi dasar untuk mengukuhkan kehidupan sumai-istri (Janggur, 2010: 67-69).
Sedangkan, menurut ajaran gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah perjanjian. Istilah perjanjian atau kesepakatan mau membaharui istilah hukum. Kata perjanjian dipilih untuk mengingatkan kita akan perjanjian antara Allah dan manusia yang berlandaskan pada cinta kasih.
Dasar dari sebuah perkawinan adalah cinta kasih yang tampak dalam persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Dalam gereja Katolik, hakikat perkawinan dipahami secara lebih mendalam sebagai sakramen yaitu ikatan cinta mesra dan hidup bersama antara suami-istri yang diadakan oleh sang pencipta dan dilindungi dengan hukum-hukum-Nya yang menampakan cinta kasih Allah kepada umat-Nya (Hardana, 2010: 10-11).
Sepintas, pernikahan menurut gereja Katolik tidak membicarakan tentang belis. Lantas, masihkah kita bergeming, dan takut untuk menikah hanya karena “belis mahal” yang dibuat oleh adat?
Tentang “belis mahal” (Paca mésé)
Berbicara tentang belis merupakan tema yang aktual akhir-akhir ini, seperti yang saudara Donatus paparkan. Ruang linimasa media sosial kian dibanjiri dengan opini yang sebetulnya bukan menjadi hal baru bagi kita, terutama orang Manggarai.
Media sosial kian menjamur dengan munculnya beragam pendapat yang diutarakan dalam kolom komentar. Keberatan terhadap “belis mahal” dijunjung tinggi.
Dalam kebudayaan Manggarai, “belis mahal” adalah hal yang lumrah dan bukan menjadi ironi bagi masyarakat. Menurut saya,“Belis mahal” dikatakan ironi karena sebuah alasan yang fundamental.
Alasan yang cukup fundamental yang dimaksud yaitu juru bicara (tongka) tidak piawai dalam mengolah kata-kata dan menghasilkan go’ét (perumpamaan-perumpamaan), serta tidak lihai dalam menarik simpati tongka dari pihak anak rona (pemberi istri).
Dari alasan di atas, dapat disimpilkan bahwa sejatinya “Belis” merupakan urusan dari tongka. Kedua keluarga hanya menyiapkan uang (anak wina) dan menentukan jumlah uang (anak rona).
Ketika tongka dari pihak anak rona meminta jumlah uang yang cukup besar melampaui yang disiapkan oleh anak wina, tongka dari pihak anak wina harus megadakan tawar-menawar. Misalnya, tongka menggunakan go’ét yang berbunyi ”mangkéng caké, salang wa’é, wa’é téku tédéng. Toé salang tuak, salang wa’é”.
Go’ét “mangkéng caké salang wa’é, wa’é téku tédéng. Mangkéng caké” diartikan dengan “menggalih tanah”.
Salang wa’é berarti jalannya air. Sedangkan wa’é téku tédéng berarti air yang ditimbah. Jika diterjemakan maka go’ét ini diartikan “menggalih tanah untuk jalannya air yang kita timbah setiap kali dibutuhkan”.
Go’ét ini dipakai dalam upacara cumang cama tu’a pada saat ditentukan “Belis”. Tujuannya agar hubungan yang baru terjalin antara kedua keluarga besar (anak rona dan anak wina) tetap harmonis seperti air yang mengalir dan tidak kenal musim.
Dalam hal ini, tidak dituntut berapa jumlah uang yang dibawa dan disiapkan oleh anak wina.
Toé salang tuak artinya; “tidak melalui jalan aren”. Pohon aren merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh di daerah Manggarai.
Pohon ini menghasilkan minuman yang kemudian dijadikan sebagai minuman tradisional (tuak) oleh masyarakat Manggarai. Tetapi, tidak semua pohon aren menghasilkan tuak. Aliran tuak dari pohon ini tidak seperti aliran air (yang selalu mengalir).
Dampak negatif dari tuak yang dihasilkan pohon aren adalah orang selalu agresif. Go’ét ini hanya sebagai simbol agar pihak anak rona tidak menuntut banyak.
Selain itu, ketika pihak anak rona masih menuntut “belis mahal”, maka langkah yang harus diambil oleh tongka dari anak wina adalah menyanyikan lagu “wa, wa, koé njieng, wa, wa koé”.
Lagu ini memiliki pesan yang mendalam agar nilai belis diturunkan dan tidak terlampau tinggi (baca: mahal). Dengan demikian, kedua calon mempelai dapat menemukan titik terang.
Di balik itu semua, kita bisa menilai bahwa belis dalam kebudayaan Manggarai tidak menuntut untuk dibayar lunas.
Karena yang paling diutamakan adalah kesinambungn hubungan antara kedua keluarga besar anak rona maupun anak wina. Lebih dari itu, kebahagiaan kedua pengantinlah yang paling utama.
* Penulis adalah Guru PAK SMP St. Maria Maumere, Alumnus STKIP St. Paulus Ruteng