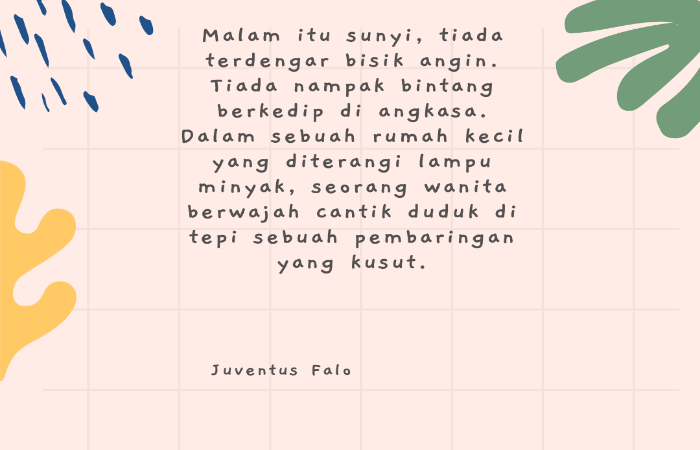Oleh: Yuventus Falo
Malam itu sunyi, tiada terdengar bisik angin. Tiada nampak bintang berkedip di angkasa. Dalam sebuah rumah kecil yang diterangi lampu minyak, seorang wanita berwajah cantik duduk di tepi sebuah pembaringan yang kusut.
Pandangannya sayu, sedih, terarah pada sosok anak kecil yang terkulai di pangkuannya. Bibirnya terkatup rapat, melukiskan kegetiran hatinya yang dirundung duka dan merintih:
“Aduhai anakku, bunga hatiku, betulkah engkau, yang terkulai di pangkuanku, lemas tak bernyawa lagi ini? Kemarin, masih kupeluk tubuhmu yang mungil, yang dingin karena demam, aku cemas, namun penuh harap…… mungkin lekas sembuh. Tetapi kini kenyataan pahit harus kualami sekarang kau sudah tiada lagi. Aku hanya menatap harap yang kosong. Oh, kemiskinan! Itukah penyebab kematianmu? Ibarat sebuah pohon bunga, kau telah tumbuh di tanah yang gersang, yang adalah lembah kemiskinan ini. Dengan penuh kasih sayang aku telah berusaha memperoleh air, guna melawan keringnya tanah di mana kau tumbuh. Ya, tanah gersang di atas mana tanganku sendiri telah menumbuhkan engkau, karena tiada lain yang kami miliki selain sebidang tanah gersang kemiskinan ini. Tetapi betapa bahagia hatiku, ketika kuncup kecil telah nampak pada pohonmu yang ramping itu. Engkau mencapai usia dua tahun, manis dan sehat. Betapa hatiku mendambakan, menatap harap masa depan yang cerah untuk bunga hatiku yang mungil. Tetapi ternyata panasnya api yang membara di tanah kemiskinan kami, telah membuat kuncup itu layu, terkulai. Jatuh di atas tanah yang gersang itu. ….. Wulan …Wulan anakku, bunga hatiku, engkau telah layu dan gugur sebelum sempat merekah dan menampilkan pesonamu!”
Wanita itu tetap termenung terseret arus kegetiran hatinya sambil menatap wajah mungil yang tak bernyawa itu.
Ya, mereka memang orang miskin, orang kecil saja. Suaminya, seorang pegawi rendahan gaji Rp 150.000,- setiap bulannya.
Tetapi apakah arti gaji sekian itu berhadapan dengan taraf kehidupan yang kian hari kian meningkat tanpa terhentikan ini?
Untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari tak cukup, apalagi hudup di kota.
Setelah kelahiran puteri yang pertama, ia telah berusaha matian-matian untuk meningkatkan kariernya untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.
Dengan ijazah SMA suamiku juga bukan orang yang terlalu bodoh. Ia cukup berkemauan baik serta rajin menjalankan tugasnya sebagai pegawi adminstrasi.
Tetapi cukupkah kemauan yang baik itu meningkatkan kariernya dan memperoleh kenaiakan gaji, tanpa uang pelicin?
Teringat pula oleh wanita muda itu, beberapa bulan, ketika puterinya mulai menjadi lemah dan sakit- sakitan …… kemudian jatuh sakit yang cukup parah.
Suaminya menghadap atasan untuk meminjam uang! Apa jawavan yang diterimanya? “Pinjaman dari bulan yang lalu belum lunas. Sekarang kamu mau pinjam lagi? Sebaiknya engkau berusaha saja.”
Ah, betapa kejamnya! Siapa yang mau mengerti derita si miskin? Si pegawai kecil dan rendahan? Para atasan yang kaya tidak menghirauakannya. Yang mereka pikirkan hanya supaya tumpukkan uang bagi dirinya sendiri itu, kian hari kian meninggi.
Itukah orang-orang kaya? Yang miskin pengertian dan berbelas kasih akan sesamanya/ mereka itu telah terkena wabah egoisme!
Kaya, ya yang kaya selalu menjadi lebih kaya, sedangkan yang miskin biarlah ia berenang melawan gelombang kemiskinan tanpa memperoleh uluran tangan. Wanita itu merintih pelan menghapus air matanya.
Seorang laki- laki berwajah cekung yang sejak tadi duduk termenung di depan kamar sambil bertopang dagu merenungkan musibah yang sedang melanda keluarganya.
Mulai sadar akan keadaan di sekitarnya. Ia bangkit dan mendekati istrinya. Sikapnya tenang. Seulas senyum getir terlukis di bibirnya.
Pandangan matanya mengungkapkan derita hidupnya. Dengan halus tangannya diletakkan di bahu wanita muda itu, si istri menoleh. Mereka beradu pandang tanpa mengucapkan kata-kata.
Sunyi, sepi, malam di malam yang gelap itu. Gemerisiknya desir angin pun tiada mampu menganggu kesunyian yang sedang mencekam kedua hati manusia yang dilanda duka itu.
Lelaki itu ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur istrinya, namun ia tidak mampu. Hatinya bagaikan tersayat, merasa diri bersalah karena tidak mencukupi kehidupan keluarga.
Mereka hanya saling memandang, keduanya saling mengerti. Tidak sesal, tiada saling menyalahkan di hati mereka.
Mereka menyadari keadaannya yang memang serba kurang, dan mereka memangtak berdaya.
Si suamu berwajah cekung itu membelai rambut istrinya, kepalanya membungkuk memandang Wulan yang tak bernyawa.
Butir- butir air mata perlahan berjatuahan di atas kepala mungil yang terbujur kaku. Yang terdengar hanya desah lemah, bisik hatinya meratap seolah-olah rintihan itu terbawa hembusan angin yang halus ke telinga Wulan yang tak bernyawa itu.
“Ah, seandainya aku ini kaya, tentu Wulan tidak akan meninggal. Seandainya aku membawanya ke rumah sakit yang mahal dan baik. Seandainya aku sanggup membiayai segala sesuatunya dan dapat membelikan obat-obat yang ia perlukan tentu Wulan akan sembuh. Ah. Wulan penyakit memang berat dan gawat, dan aku sebagai ayahmu telah gagal menolong nyawamu karena ganasnaya kemiskinan yang tak teratasi ini. Ah, Wulan putriku sayang, maafkanlah papamu ini.”
Di sebuah makam yang sunyi, di depan gundukan tanah yang hanya ditandai sebuah kayu salib bertuliskan RIP yang sederhana tertuliskan juga : DI SINI BERISTIRAHTLAH DENGAN TENANG “WULANDARI” PUTRI KAMI YANG TERCINTA.
Setiap sore, dua sosok tubuh nampak berlutut di depannya. Keduanya membisu, yang terdengar hanya gemerisiknya dedaunan yang tertiup angin lenbut si ayah berdoa:
“Ya Tuhan ampunilah aku, karena sebagai seorang ayah aku telah gagal dalam perjuangan untuk dapat mencukupi keluargku. Ah, terangilah jalanku untuk dapat menyambut dengan tabah, hari depan yang masih asing, apa pun yang akan diberikan kepada kami, kuatkanlah iman kami. Aku akan tetap berjuang.”
Wanita muda itu berdoa: “Wulan, ampunilah ayahmu ia telah berusaha dengan halalkan segala cara untuk mempertahankan hidupmu tetapi ternyata ……. ia gagal, karena kami memang miskin. Ya kemiskinan yang bagaikasn tanah gersang itu, telan menelan banyak korban yang tak berdaya. Ah, anakku engkau benar-benar seperti sebuah kuncup bunga yang mungil tetapi engkau telah layu sebelum sempat merekah. Namun, sekarang engkau kutanam di taman hatiku, kuncup itu akan tetap segar tersiram oleh air cintaku, dan kelak, pda saatnya engkau akan merekah indah di taman hatiku.”
Ketika kedua insan itu meninggalkan makam hari sudah mulai gelap. Mereka berjalan tanpa banyak bicara.
Hati dirasakan sepi, se-sepi makam yang mereka tinggalkan. Hujan gerimis membasahi sepanjang jalan yang mereka lalui.
Mereka berjalan tanpa mengirauakan aiar hujan yang mulai membasahi tubuh mereka. Ketika sampai di rumah, ya rumah sempit dengan perabotannya jauh daripada lengkap itu, mereka saling berpandangan.
Wanita itu menjatuhkan diri dalam pelukan suaminya, aiar matanya membasahi wajahnya yang pucat. Dengan lembut sang suami berbisik:
“Ah, betapa aku ingin membawamu melalui jalan kehidupan yang bertaburkan bunga melati, tetapi kini, hanya duri-duri yang engkau dapatkan. Bertabahlah istriku yang baik, kita akan berjuang menentang kemiskian ini, saatnya akan tiba …… kita pasti menang ….” ssng istri mengangguk perlahan, seraya mengusap air mata di pelupuk matanya.
Elar- Manggarai Timur (berdasarkan pengalaman sebuah keluarga)
Jumat, 08 januari 2022