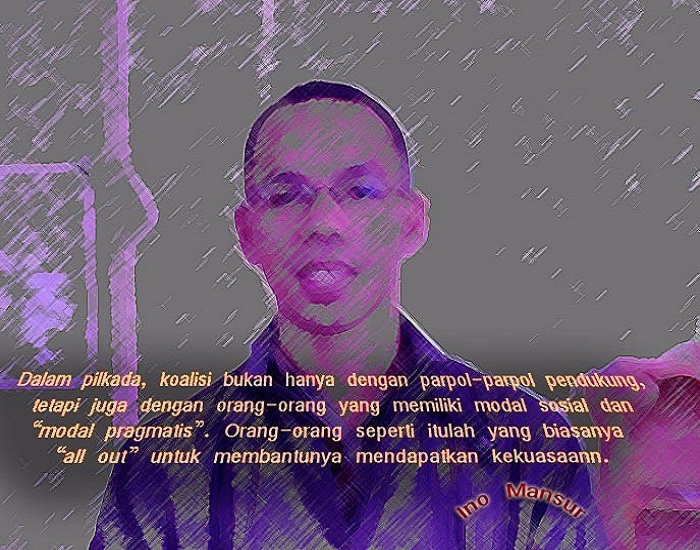Oleh Inosentius Mansur *
Apakah Pilkada bisa melahirkan pemimpin “bernyali”? Inilah pertanyaan yang boleh jadi ganjil, tetapi hemat saya penting. Saya memang percaya bahwa semua calon yang dinyatakan layak untuk mengikuti perlombaan demokrasi lokal merupakan “orang-orang khusus” yang memiliki kemampuan khusus pula.
Mereka layak untuk berkompetisi dalam pesta demokrasi elektoral lokal lima tahunan. Sampai di sini, setiap calon pemimpin boleh berbangga diri, sebab “lolos” dan “lulus” sensor.
Setidaknya, partai memiliki pertimbangan khusus untuk memberikan rekomendasi politik kepada calon tertentu. Tidak mungkin parpol merekomendasikan figur yang tidak memiliki keunggulan ataupun “nilai jual” tertentu.
Tersandera
Persoalannya adalah banyak pemimpin daerah yang selama ini merupakan produk Pilkada belum menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki nyali. Mereka tidak suka “ribut”, melainkan “datar-datar” saja.
Takut mengambil langkah “provokatif” dan barangkali juga takut ditekan oleh orang-orang yang berada disekelilingnya. Walaupun awalnya ingin “tampil beda”, ingin melakukan gebrakan-gebrakan liberatif, tetapi ketika mendapatkan kedudukan (pemimpin), sang pemimpin kembali normatif dan “menormalisasi” relasinya dengan elite-elite politik dan para penjasa sehingga eksistensinya aman.
Sepintas, hal seperti ini agaknya baik. Mengapa? Karena seorang pemimpin mesti bisa mengakomodir segala potensi yang mengelilinginya secara baik sehingga berdampak konstruktif bagi pembangunan daerah. Dia tidak boleh gegabah apalagi serampangan.
Tetapi pertanyaannya: bagaimana kalau orang-orang yang dipercayakan untuk membantunya itu tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya secara benar? Langkah seperti apakah yang diambilnya agar hal seperti itu tidak mengorbankan rakyat?
Selama ini, ada beberapa “pejabat” teras di daerah-daerah yang tidak bisa menjalankan perannya secara reproduktif, tetapi tetap saja dipertahankan.
Kinerjanya tidak terlalu signifikan, atau bahkan menurun, tetapi ironisnya masih saja diberi kepercayaan untuk menduduki suatu instansi. Lembaga yang dipimpinnya seringkali menjadi sumber distorsi, tetapi hal itu tidak menjadi rujukan bagi pemimpin untuk “mencopotnya”.
Hal seperti ini terjadi (bisa saja) karena semenjak seseorang menjadi (bakal) calon kepala daerah, telah didukung oleh orang-orang yang rela memberikan apa saja kepadanya agar bisa menjadi pemimpin.
Koalisi yang dibangun, bukan hanya dengan parpol-parpol pendukung, tetapi juga dengan orang-orang yang memiliki modal sosial dan “modal pragmatis”. Orang-orang seperti itulah yang biasanya “all out” untuk membantunya mendapatkan kekuasaan.
Lalu, apakah sebatas itu saja? Tentu saja tidak! Dukungan mereka pasti penuh kalkulasi. Mereka membutuhkan “imbalan”. Imbalannya kemudahan dalam segala hal ataupun posisi strategis tertentu.
Prinsip: the right man on the right place diabaikan, karena jabatan diberikan berdasakan perhitungan balas jasa. Hal seperti inilah yang menyebabkan sang pemimpin tersandera dan tidak bisa mengambil langkah rasional yang berorientasi common good.
Keterikatannya dengan “para penjasa” membuat dia tersandera. Dia tidak akan berani melakukan evaulasi terhadap kinerja para pembantunya untuk selanjutnya mengambil sikap pasti demi kemajuan daerah yang dipimpinya.
Maka jangan heran jika pembangunan daerah tidak berjalan sesuai ekspektasi publik. Pejabat yang dipercayakan untuk menduduki jabatan tertentu tidak memiliki kesanggupan untuk menterjemahkan konsep pembangunan daerah secara baik.
Dia tidak tahu dan tidak mampu melakukan inventarisasi atas berbagai persoalan sosial untuk diartikulasikan lewat program liberatif. Efeknya adalah rakyat tetap menderita. Kebaikan bersama yang diharapkan hanya tinggal mimpi, sulit sekali menjadi kenyataan.
Bernyali
Karena itulah, menurut saya, Pilkada bukan sekadar mencari dan memilih pemimpin yang dianggap layak oleh parpol. Lebih dari itu, Pilkada mesti menjadi momentum untuk memilih pemimpin “bernyali”.
Pemimpin “bernyali” adalah pemimpin yang tidak takut tekanan. Dia memakai perspektif kerakyatan dan merujuk pada “intuisi” kerakyatan dalam mengeluarkan kebijakan sosial. Dia melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
Dia adalah pemberani dan bukan pengecut. Dia berani untuk mengambil langkah-langkah pasti serta terobosan-terobosan alternatif meskipun “ditolak” segelintir kelompok hegemonik.
Dia memiliki pertimbangan matang serta tidak tersandera oleh deal-deal politik tertentu. Keputusan politiknya jauh dari kontaminasi kepentingan pragmatis.
Saat dia mengambil keputusan, dia benar-benar yakin bahwa keputusannya itu hanya untuk rakyat. Disamping itu, dia juga memiliki kalkulasi dan prediksi jitu bahwa apa yang diputuskannya mampu mendongkrak nasib rakyat ke arah yang lebih baik.
Sudah saatnya apa yang dilakukan Ahok di Jakarta ditiru oleh para pemimpin daerah kita di NTT. Alangkah bagusnya jika pejabat yang tidak memiliki kesanggupan “dieliminasi” atau tidak diberikan jabatan daripada menjadi penghambat pembangunan. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mengorbankan rakyat banyak.
Selain itu, pemimpin juga mesti memiliki “cetak biru” untuk menilai kinerja para pembantunya. Dari situ, dia bisa mengevaluasi sejauhmana kesanggupan mereka dan apa dampaknya bagi kemajuan daerah.
Indikator-indikator pencapaian mesti diukur dan diverifikasi dengan data lapangan dan bukannya “hanya” berdasarkan laporan dari para pembantunya. Lalu, bagaimana dengan anda, para calon pemimpin? Apakah anda memiliki nyali?
*Pemerhati sosial-politik dari Seminari Ritapiret-Maumere