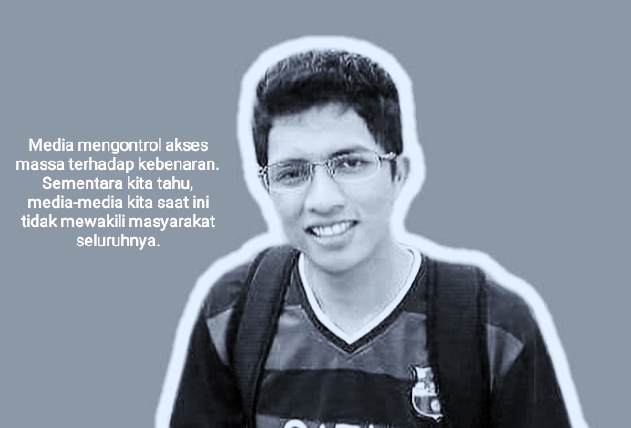Oleh: Ferdi Jehalut
Mahasiswa STFK Ledalero
Hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet yang sempat menggegerkan publik beberapa waktu lalu sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa kebudayaan massa sedang mengontrol kebudayaan modern.
Kebudayaan massa merupakan suatu istilah untuk menunjukkan kebudayaan-kebudayaan yang disebarluaskan oleh industri media, baik media mainstream maupun media online.
Di sini, pembentukan opini dan penilaian publik tentang suatu hal diambilalih oleh industri media yang setiap hari menghadirkan ke hadapan publik aneka berita yang sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan media bersangkutan.
Istilah “kebudayaan massa” dipopulerkan oleh para pemikir dari Mazhab Frankfurt di Jerman (Adorno, Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas).
Dalam diskusi tentang kebudayaan, para ilmuwan sosial ini sangat pesimis dengan kebudayaan kontemporer yang mereka sebut sebagai kebudayaan massa. Menurut mereka, industri budaya telah menghasilkan produk kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan massa. Kebudayaan ini telah mengontrol kebudayaan modern (Bernard Raho, 2007:89).
Ada tiga hal yang menjadi keprihatinan para pemikir Mazhab Frankfurt terkait kebudayaan massa ini.
Pertama, mereka prihatin karena para produser budaya massa menghasilkan sejumlah kepalsuan yang disebarluaskan secara massal melalui media massa dan media elektronik.
Kedua, mereka merasa terganggu dengan akibat-akibat dari budaya ini yang menentramkan, membius, tapi menekan orang.
Ketiga, kebudayaan massa adalah alat yang dimanfaatkan untuk memanipulasi individu-individu untuk mengikuti apa saja yang ada di dalam masyarakat yang sudah “diatur” itu. (ibid.)
Kembali kepada persoalan Ratna Sarumpaet. Persoalan ini sebenarnya tidak menjadi rumit seandainya Prabowo, Fadli Son, dan Amien Rais tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan konferensi pers.
Akan tetapi, karena mereka sendiri tahu dahsyatnya pengaruh media dalam pembentukan opini dan penilaian publik, maka tanpa melalui proses verifikasi yang cermat mereka melakukan konferensi pers. Dan memang terbukti bahwa tidak lama setelah konferensi pers dilakukan, berita penganiayaan Ratna Sarumpaet menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.
Selanjutnya, setelah berita penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet diketahui sebagai hoaks, spontan kecaman terhadap Ratna Sarumpaet membanjiri media sosial dan media mainstream.
Pertanyaannya, dalam kasus ini, apakah hanya Ratna Sarumpaet, Prabowo, Fadli Zon, dan Amien Rais yang mesti dinilai sebagai penyebar hoaks? Menurut hemat saya, media-media yang telah memberitakan kasus itu juga dapat disebut sebagai penyebar hoaks. Bahkan, media-media inilah yang justru mempunyai andil besar dalam penyebaran hoaks Ratna.
Kita coba sedikit berimaginasi. Seandainya media-media yang turut memberitakan kasus itu sebelum diketahui sebagai hoaks mengedepankan prinsip verifikasi, pastilah mereka tidak terjebak dalam lingkaran yang sama. Dengan itu, publik juga tidak dibodohi oleh berita bohong itu.
Akan tetapi, kita tahu bahwa media-media kita juga sering kali terjebak dalam persoalan yang sama, yakni memburu rating minus verifikasi.
Bagi mereka, hal itu mungkin beralasan, karena tuntutan aktualitas berita mengharuskan mereka untuk segera memberitakan peristiwa yang sedang terjadi. Namun, dengan itu, media-media akhirnya terjebak dalam penyebarluasan kepalsuan dan kebohongan secara massal.
Reaksi atas Kebohongan
Kebohongan selalu menyembunyikan sesuatu. Ia menyembunyikan ketakutan, niat, nafsu, kerakusan, dan kekejian. Selain menyembunyikan sesuatu, kebohongan juga membahasakan irasionalitas. Ia membahasakan raibnya nurani untuk terlibat dalam persaingan yang sehat.
Salah satu bahaya dari kebudayaan massa adalah orang bisa bereaksi atas sebuah kebohongan. Dalam masyarakat yang didominasi oleh kebudayaan massa, akses terhadap kebenaran pada batas tertentu dibatasi oleh media.
Media mengontrol akses massa terhadap kebenaran. Sementara kita tahu, media-media kita saat ini tidak mewakili masyarakat seluruhnya.
Mereka pasti mewakili kepentingan pemilik media dan pemodal yang menyokongnya atau bisa juga preferensi politik pemiliknya. Oleh karena itu, konten-konten yang disajikan kepada publik pun sudah hampir pasti membahasakan kepentingan itu. Kebenaran dengan demikian mudah diuapkan.
Proses pembohongan massal sangat mungkin terjadi. Itu artinya, ketika media memberitakan sebuah kebohongan, massa juga dengan sendirinya akan berekasi terhadap kebohongan itu.
Dalam kasus Ratna Sarumpaet, hal di atas menjadi sangat nyata dan terang-benderang. Ratna Sarumpaet menciptakan hoaks. Prabowo, Fadli Son, dan Amien Rais bereaksi terhadap hoaks itu.
Kemudian massa juga bereaksi atas hoaks yang sama setelah Prabowo dan kawan-kawannya melakukan konferensi pers. Di sini, peran media sebagai sarana pembentukan opini publik sangat besar. Melalui media-media, dalam waktu sekejap kebohongan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia.
Massa akhirnya ramai-ramai bereaksi terhadap kebohongan. Dan reaksi terhadap kebohongan tentu sebuah kebohongan juga.
Pertanyaan yang paling mungkin muncul dari kasus di atas adalah mungkinkah Ratna Sarumpaet adalah pelaku tunggal dalam merancang pembohongan massal itu? Apakah reaksi Prabowo, Fadli Son, dan Amien Rais yang melakukan konferensi pers murni karena mereka peduli terhadap hak asasi manusia Ratna Sarumpaet yang dikabarkan dianiaya? Apakah media-media yang memberitakan kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet yang kemudian diketahui hoaks itu benar-benar bebas dari kepentingan politis dan bisnis?
Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul dari sikap skeptis dan curiga dalam merespons suatu peristiwa atau pemberitaan media. Jadi, landasannya adalah hermeneutika kecurigaan dan skeptisisme.
Maka, ketika saya membaca berita tentang kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh orang yang tak dikenal yang kemudian diketahui sebagai hoaks itu, saya tidak gegabah memberikan komentar.
Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, sebagiannya semoga akan disingkapkan setelah proses peradilan dan dalam diskursus publik pada hari-hari yang akan datang.
Namun, terhadap reaksi Prabowo dan kawan-kawan yang dengan cepat melakukan konferensi pers, saya kurang terlalu yakin bahwa itu bentuk kepekaan terhadap penganiayaan atau singkatnya pelanggaran HAM.
Alasannya sederhana. Kalau seandainya Prabowo benar-benar mempunyai kepekaan terhadap soal-soal semacam itu, mengapa dari dulu Prabowo tidak pernah mendesak negara (baca: pemerintah) untuk membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu?
Padahal, sebagai oposisi pemerintah seharusnya ia menjual isu itu sebab komitmen awal pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggran HAM berat masa lalu sampai saat ini belum terealisasi.***