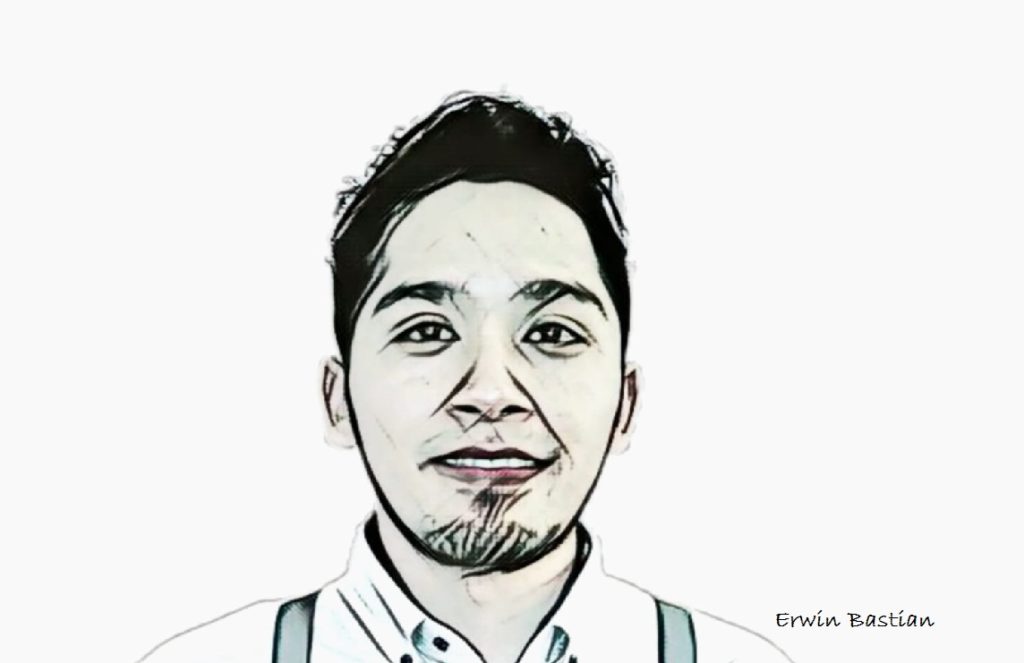Oleh: Erwin Bastian*
Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM dalam bukunya “Berfilsafat Politik” (Riyanto, 2014:59) mengungkapkan bahwa politik adalah diskursus.
Karena itu, ia menekankan peranan komunikasi berupa bahasa, menjadi unsur penting dalam politik. Profesor Filsafat di STFT Widya Susana-Malang ini yakin bahwa jika bahasa penuh dengan cemoohan (bisa juga hoaks), politik menjadi ajang kegilaan.
Politik berada dalam ruang gelap apabila, bahasa politik penuh dengan kekerasan, diskriminasi rasial, dan instrumentalisasi agama .
Mengutip seorang filsuf Pierre Bourdieu, Prof Riyanto (2014:64) mengatakan bahwa bahasa itu propaganda yang memiliki kekuatan menghancurkan.
Ketika sebuah bahasa seperti “kelompok ini atau itu kafir” yang terjadi adalah pengondisian secara jitu rasionalitas masyarakat untuk memandang bahwa kelompok lain layak untuk dibenci dan dilenyapkan.
Realitas ini sangat tampak dalam persaingan meraih elektabilitas di bumi politik Indonesia saat ini. Hawa politik terasa semakin “panas”.
Setiap hari, media masa dipenuhi oleh berita-berita seputar persaingan politik atau bahkan berita-berita yang sengaja dikaitkan dengan politik. Para petarung politik bersaing merebut suara rakyat sebanyak banyaknya dengan taktik dan teknik masing-masing tim.
Satu tujuan persaingan ini adalah untuk meraih kekuasaan politik. Namun, “Apakah rakyat memilih pemimpin karena pemimpin itu berkualitas atau apakah pemimpin itu baik/berkualitas karena rakyat memilihnya?”, politik mempunyai jawaban lain.
Worldlessness
Worldlessness adalah suatu istilah yang biasa digunakan oleh seorang filsuf bernama Hanna Arendt untuk menggambarkan dunia bersama yang sudah tidak sesuai dengan yang semestinya (yang diidealkan).
Dunia bersama yang ia maksudkan adalah dunia yang diciptakan oleh manusia dalam dialog, komunikasi, dan berbagai tindakan bersama setiap hari. Ketika membangun komunikasi dan dialog, manusia menciptakan dunia bagi diri dan bagi sesamanya.
Bagi Arendt, dunia itu dibentuk oleh kebersamaan dan komunikasi di mana semua orang berpendapat dan mengalami kebebasan. Ketiadaan situasi seperti inilah yang disebut Arendt sebagai worldlessness.
Sedikit berbeda dengan Arendt, penulis melihat fenomena worldlessness secara lebih mendalam dari sekedar kebersamaan, komunikasi, atau kenyataan bahwa semua orang berpendapat dan bertindak. Pertanyaan yang paling fundamen adalah komunikasi/dialog macam apa?
Hemat saya, dunia bersama yang diidealkan itu mesti mengandung kebebasan, komunikasi/dialog yang positif, terbebas dari hoaks, terbebas dari upaya untuk saling menyerang atau saling membenci (verbal maupun fisik) dan berlandaskan prinsip etis.
Kegagalan dalam politik terjadi ketika, masyarakat pemilih justu memilih pemimpin yang merupakan hasil dari kebohongan/manipulasi atau hoaks dan hasil dari isu-isu irasional.
Secara singkat penulis menyebutkan beberapa ciri worldlessness yang tampak dalam perpolitikan Indonesia.
Pertama pembodohan terhadap masyarakat. Kedua, rusaknya kehidupan bersama akibat konflik-konflik sosial tanpa adanya kesadara rekonsiliatif. Ketiga, rusaknya komunikasi dan dialog yang menjadi sarana terbentuknya dunia bersama. Keempat, hilangnya kebebasan masyarakat sebagai subyek penting dalam demokrasi.
Worldlessnes dalam Perpolitikan Indonesia
Worldessnes sebenarnya bukanlah ungkapan yang menyiratkan rasa pesimis penulis dengan tendensi politik yang sedang bergulir di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Worldlessness merupakan sebuah bentuk evaluasi kritis atas berbagai fenomena perpecahan, konflik, politisasi agama, politisasi budaya, dan manipulasi yang disebabkan oleh persaingan politik yang tidak sehat.
Dalam hal ini, komunikasih dan dialog itu bersifat sementara dan sangat bergantung dari elemen-elemen pembentuk dialog itu. Kalau dialog dan komunikasi dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab maka, dunia bersama sulit tercapai.
Untuk mengatasi situasi ini ada dua arah solusi yang dianjurkan. Pertama, mengembalikan moralitas ke dalam politik. Persaingan politik tidak sehat yang terungkap dalam prinsip “tujuan menghalalkan segala cara” adalah kematian politik itu sendiri.
Kebaikan bersama yang dicita-citakan dalam politik tidak dapat diperoleh dengan cara yang tidak baik. Hal ini berarti politik sebenarnya harus berlandaskan pada tatanan moral/prinsip etis.
Politik tidak identik dengan kebusukan dan kebohongan karena patokan politik ada pada nilai etis yang ia pegang. Politik tidak sekedar persaingan untuk merebut kekuasaan tetapi juga merupakan perjuangan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, lebih beradab, dan lebih bermoral.
Kedua, menciptakan politik yang ramah kemanusiaan. Hal yang paling penting dalam politik ramah kemanusiaan adalah kecerdasan masyarakat untuk memahami dan bertindak dalam politik.
Pemahaman seperti ini, selain menjadi tameng untuk membatasi berbagai absurditas ke dalam politik, juga menyadarkan masyarakat bahwa konflik harus berakhir pada kultur rekonsiliatif.
Untuk itu, selain pendasaran moral, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat, dalam melawan berbagai upaya penghancuran dunia bersama manusia.
Pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis dalam hal ini bukanlah berpikir lebih keras melainkan berpikir lebih baik. Segala isu yang diterima hendaknya tidak dipercayai begitu saja tanpa pertimbangan yang baik. Kita mengkritisi sesuatu dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentangnya.
Kedua, mengutamakan kemanusiaan. Unsur paling fundamental dalam politik adalah manusia atau kemanusiaan. Tanpa manusia tidak mungkin ada politik. Karena itu, politik sebenarnya hadir untuk melayani kepentingan manusia atau masyarakat dalam suatu negara tertentu.
Politik tanpa pertimbangan kemanusiaan adalah politik yang lupa diri. Dia tidak sadar dasar terdalam dari dirinya sendiri.
Ketiga, penerapan nilai-nilai budaya dan agama dalam politik. Kultur politik Indonesia memang tidak dapat dipahami sebagai politik yang murni sekuler karena, peran kebudayaan dan agama sangat dominan dalamnya.
Setiap kebudayaan dan juga agama selalu memiliki segudang nilai luhur yang berguna bagi setiap orang. Politik sebenarnya tidak terlepas juga dari nilai-nilai yang ada dalam budaya dan agama-agama ini.
Karena itu, nilai-nilai dalam budaya dan agama-agama mesti dapat diterapkan dalam politik.Bukan pencitraan yang seharusnya ditonjolkan melainkan nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya dan agama-agama.
Politik sebagai diskursus dengan media komunikasi mengandaikan ketentuan rasional dan hati nurani. Rasionalitas membantu manusia untuk menentukan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta.
Hati nurani berfungsi sebagai patokan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan apakah tindakan itu baik atau buruk. Karena itu kematian rasio sebenarnya bukan terjadi hanya karena kematian manusia (totalitas), melainkan karena rasio tidak menjalankan fungsinya untuk berpikir, berpikir tentang dunia bersama manusia.
Sedangkan kematian hati nurani terjadi bukan saja karena kematian manusia secara fisik melainkan juga karena kematian daya spiritual rohaniah. Sehingga ketiadaan pertimbangan hati nurani dan rasio dalam politik adalah worldlessness sama seperti orang yang sudah “mati sebelum meninggal”.
*Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero