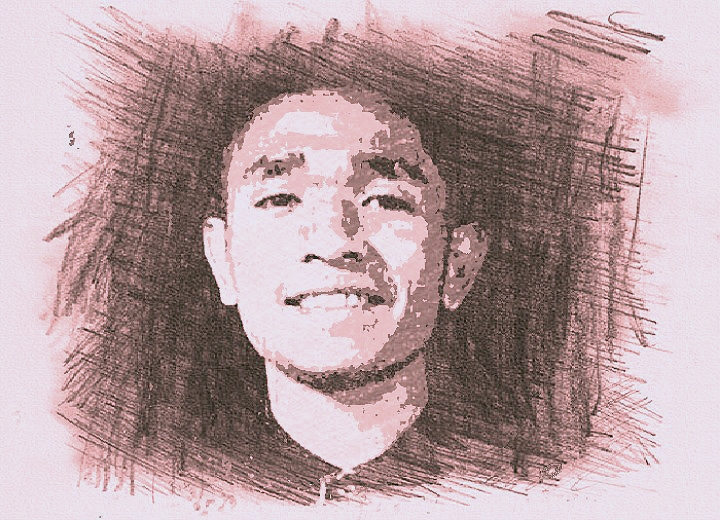Oleh: Rian Odel
Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere
Sejarah mencatat Pancasila lahir setelah Ir. Soekarno melewati proses refleksi yang matang tatkala berada di Ende, Nusa Tenggara Timur.
Dengan demikian, tidak bisa dibantah bahwa Nusa Tenggara Timurlah yang menjadi rahim bagi dasar negara Republik Indonesia.
Dalam Proses refleksi itu, Soekarno kembali menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam budaya lokal masing-masing suku bangsa di Indonesia. Hal yang sangat dibanggakan ialah bahwa refleksi itu pada akhirnya menemukan puncaknya di NTT.

Walaupun demikian, perjalanan Pancasila selalu problematis sebab ada kerusakan dalam diri sebagian penganutnya yang gagal memaknai Pancasila.
Buktinya, masih ada aspirasi protes untuk menggantikan Pancasila. Selain itu banyak orang yang mengaku Pancasilais tetapi tutur kata dan tingkah lakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pada titik ini, generasi milenial NTT mesti menyadari tanggung jawabnya untuk menangkal pemahaman kotor yang berusaha mengkudeta Pancasila di Ibu Pertiwi. Salah satu jalan yang mesti ditempuh yaitu merawat budaya lokal NTT sebagai dasar berpancasila.
Generasi Milenial NTT
Para ahli memprediksi awal tahun 1980-an sebagai awal kelahiran generasi milenial dan berakhir pada sekitar tahun 2000-an. Generasi milenial NTT adalah aset unggul peradaban dan kebudayaan bangsa.
Mereka mempunyai tanggung jawab demi menjaga warisan luhur bangsa yang sudah berakar pada momen sumpah pemuda 1928 silam. Potensi yang terkandung dalam jiwa-raga mereka menjadi kekuatan untuk proses terealisasinya nilai-nilai Pancasila. Sebut saja Dicky Senda – selain sebagai penggagas Komunitas Lakoat Kujawas, ia juga seorang penulis muda NTT yang berpartisipasi dalam memajukan potensi anak-anak NTT khususnya dalam bidang literasi, budaya lokal dan kewirausahaan sosial.
Keterlibatannya menjadi contoh bagi generasi milenial dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila seperti bidang sosial dan kecerdasan anak bangsa.

Bukan hanya Dicky Senda, melainkan juga ada banyak generasi milenial NTT lainnya yang telah menyumbang potensi kreatifnya secara total demi suburnya Pancasila.
Budaya Lokal dan Pendidikan Pancasila
Budaya lokal (local culture) merupakan akar dari identitas sebuah bangsa. Bangsa yang besar mesti mengenal budayanya sendiri (Soekarno). Hal ini ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant bahwa ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri (lihat Van Peursen, 1976), sebab budaya merupakan hasil karya manusia.
Melalui hasil karya tersebut, terpancar karakteristik manusia bersangkutan misalnya aktivitas sosial dan falsafah hidup. Dalam tubuh kebudayaan terjalin banyak aspek, misalnya, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat-istiadat dan lainnya. Demikian E. B. Tylor dalam Primitive Culture (1973). Artinya, kebudayaan menjadi pedoman tingkah laku manusia menuju harmonisasi dengan sesamanya dan lingkungan alam (Gregor Neonbasu, Manuskrip, 2008).
Pancasila adalah dasar negara yang lahir dari kebudayaan Indonesia, maka generasi milenial NTT merupakan penjaga sekaligus pewaris nilai-nilai Pancasila sesuai dengan idealisme para Bapa Bangsa.

Salah satu dasar kekuatan bagi generasi milenial untuk mencapai nilai-nilai Pancasila yaitu merawat budaya lokal NTT. Patut dibanggakan bahwa provinsi NTT kerap kali dijuluki sebagai Nusa Tertinggi Toleransi. Hal ini tentu bukan sekadar label semata tetapi berlandaskan pada falsafah hidup dan aktivitas riil orang NTT dalam membangun bangsa Indonesia.
Julukan luar biasa tersebut merupakan buah dari nilai-nilai budaya lokal NTT yang sarat dengan aspek humanisme sebagaimana tercantum dalam butir-butir Pancasila. Pada tahap ini, kesadaran generasi milenial tentang pentingnya budaya lokal mesti ditingkatkan.
Melalui budaya lokal, identitas partikular dalam diri generasi milenial NTT bisa disatukan, misalnya keanekaragaman dalam bidang agama yang seringkali menimbulkan huru-hara di bangsa ini.
Pemahaman tentang persatuan dalam segala segi perbedaan mesti diproduksi dalam diri generasi milenial NTT. Huru-hara yang dimaksud barangkali disebabkan oleh hilangnya identitas budaya lokal dalam diri anak-anak bangsa, padahal budaya lokal adalah sumber sekaligus inspirasi lahirnya Pancasila.
Lantas, bagaimana generasi milenial merawat budaya lokal NTT sebagai referensi pendidikan pancasila?

Pertama, kembali ke kampung. Artinya, generasi milenial NTT mesti menggali kebiasaan luhur yang telah lama mengakar di tengah masyarakat alamiah di kampungnya sendiri.
Peradaban luhur yang diwariskan oleh leluhur menyimpan banyak aspek bernilai bagi wawasan generasi milenial NTT. Sebut saja, aspek kekeluargaan, toleransi religius, gotong-royong dan sebagainya mesti menjadi referensi bagi generasi milenial NTT.
Kebiasaan-kebiasaan luhur tersebut masih dipraktekkan secara alamiah oleh masyarakat lokal di kampung tanpa intervensi lembaga pendidikan.
Mungkin berlebihan kalau saya mengadopsi pemikiran J.J. Rousseau (1712-1778) untuk kembali ke alam. Manusia mesti kembali ke dalam kehidupan alamiahnya sebagai ada yang baik. Dia bahkan memberi sinisme terhadap perkembangan pendidikan yang kaku bisa membuat manusia (anak-anak) menjadi “rusak” oleh sistim pendidikan formal.
Refleksi filsuf Pendidikan ini bisa dibaca secara lebih luas dan kiranya merangsang generasi milenial NTT khususnya yang berpendidikan untuk rendah hati kembali belajar di kampung halamannya yang masih alamiah tingkah laku berpancasila.
Inti pendapat Rousseau ialah tentang perkembangan diri yang bebas tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini mendukung perkembangan alamiah seorang anak tanpa intervensi pendidikan sebab menurutnya pendidikan bisa membawa anak pada kekacauan berpikir dan bertingkah laku. Radikalisme agama, ujaran kebencian yang gemar dilakukan oleh generasi milenial berpendidikan atau para pemuka agama bisa menjadi contoh yang tepat.
Kedua, lembaga-lembaga pendidikan mesti meningkatkan wawasan berbudaya lokal, misalnya, optimalisasi mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok). Melaluinya, wawasan generasi milenial semakin bersih dari stimulus eksternal seperti radikalisme agama, primordialisme sempit dan konsep dekstruktif lainnya yang berusaha melumpuhkan nalar kritis generasi milenial NTT.

Budaya lokal adalah identitas dasar yang mengikat semua orang NTT. Dari segi perbedaan agama misalnya, saya menganjurkan lembaga-lembaga pendidikan khususnya yang berbasis agama untuk menyediakan waktu yang cukup bagi generasi milenial untuk menggeluti teologi agama tradisional suku-suku yang ada di NTT – selain menggeluti teologi agama samawi yang tentunya memiliki perbedaan mendasar walaupun mempunyai muara yang barangkali sama.
Maksudnya, generasi milenial NTT yang lahir dari budaya lokal khas daerahnya masing-masing mampu memahami lebih mendalam konsep agama tradisional yang ada dalam budayanya sehingga ada keseimbangan dalam memahami konsep religiusitas lain yang berbeda. Saya mengangkat ini sebab perbedaan teologi agama samawi seringkali menjadi nomor satu patologi sosial.

Ketiga, Generasi milenial mesti merasa bangga sebagai orang NTT yang kurang-lebih sudah mampu memproduksi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup.
Kebanggaan ini mesti diwujudkan secara riil dalam berbagai bidang, misalnya kecerdasan melalui literasi, organisasi lintas perbedaan, melahirkan ide konstruktif demi terwujudnya NTT yang sejahtera, partisipasi sosial-politik, perjuangan emansipasi, bertingkah laku baik, memelihara alam, produktivitas dan aktivitas positif lainnya yang menjadi fondasi baginya untuk membangun hidup berpancasila di NTT tercinta demi Indonesia maju.
Bukan hanya itu, hal yang terpenting ialah generasi milenial juga mesti mewartakan ide nasionalisme melalui infrastruktur kebudayaan lokal khas NTT.