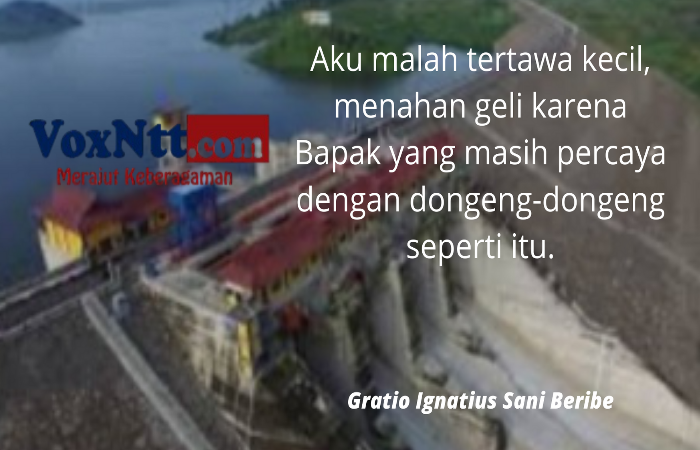*Cerpen
*Oleh: Gratio Ignatius Sani Beribe
“Tidak bisa nak, tidak bisa!”
Kata-kata itulah yang selalu diucapakan Bapak ketika aku mendorongnya mengizinkan proses pembangunan bendungan di wilayah desa kami.
Bapak sebagai kepala desa berungkali menolak memberi izin kepada pemerintah.
Biarpun harga ganti rugi lahannya telah ditawarkan setinggi-tinggi mungkin, tetapi Bapak tetap kukuh menolak.
“Ayolah Pak, kapan lagi kita bisa mendapatkan uang ratusan juta tanpa harus bekerja keras.
Hasil panen Bapak kalau dikali sepuluh pun, tak bisa mendapatkan uang sebesar itu. Lihat juga dengan warga desa yang lain Pak, hidupnya masih miskin, anak-anaknya banyak yang masih sekolah.
Jika Bapak memberikan izin pembangunan, dijamin anak-anak tersebut bisa sekolah sampai sarjana.
”Bapak tetap bisu dan bergeming. Matanya jauh menatap ke arah langit pagi di depan teras rumah.
“Tetap saja nak, Bapak belum bisa memberikan izin.”
“Kenapa Pak? Kenapa Bapak terus-terusan menolak? Apa alasannya?” Tanyaku dengan sedikit kesal, karena Bapak terus menolak tanpa memberikan alasannya.
“Alasannya, karena tanah tempat pembangunan bendungan tersebut adalah tanah panas.”
“Kenapa sampai disebut tanah panas?”
Bapak kemudian menghisap rokok dengan tarikan yang cukup dalam, sampai asap yang dikeluarkannya menyembul memenuhi pandangan kami.
“Menurut cerita nenek moyang dahulu, tempat pembangunan bendungan tersebut merupakan tempat perjanjian antara seorang Pangeran dari sebuah kerajaan di selatan yang ingin meminang Putri Raja di daerah ini.
Raja tersebut bersedia melepas Puteri satu-satunya jika Sang Pangeran dari selatan mampu membayar dua ratus batang emas dan dua puluh ekor sapi dengan batas waktu sampai esok malam.
Sang Pangeran bersedia memenuhi permintaan Raja tersebut, sehingga keesokan harinya ia membawa dua ratus batang emas dan dua puluh ekor sapi.
Ditaruhnya emas-emas tersebut dalam sebuah peti besar dan sapi-sapinya diikat pada pohon-pohon di tempat perjanjian mereka. Namun malang yang dialami Sang Pangeran.
Ketika hari sudah mau gelap dan Rombongan Raja bersama Putrinya hampir tiba, lima ekor sapinya ternyata dicuri oleh warga sekitar.
Sang Pangeran pun marah dan menyumpah-nyumpah tempat tersebut karena telah membawa kesialan bagi dirinya, namun yang tak ia ketahui bahwa rombongan Raja telah tiba disana dan merasa sumpah-serapah yang dilontarkannya merupakan penghinaan terhadap Raja.
Oleh karena itu, Pengeran tersebut langsung dibunuh di tempat dan pernikahan tak jadi dilaksanakan.
Mulai saat itulah, nenek moyang kita menyebut tempat tersebut sebagai tanah panas karena dipercaya Sang Pangeran masih mencari korban lima orang manusia sebagai ganti atas sapi-sapinya yang hilang.”
Bapak yang sedari tadi bercerta sembari menatap langit, kemudian menoleh kepadaku dengan tatapan yang serius.
“Harus lima korban nak, harus lima.”
Aku malah tertawa kecil, menahan geli karena Bapak yang masih percaya dengan dongeng-dongeng seperti itu.
“Pak, hari gini kok masih percaya sama cerita-cerita seperti itu? Aku jadi heran, selama ini Bapak menahan izin pembangunan bendungan hanya karena cerita fiktif yang tak masuk akal.”
“Tapi nak, menghormati nasihat leluhur itu perlu, karena dari pengetahuan dan tradisi merekalah kampung kita ini masih tetap bertahan sampai sekarang.”
“Iya Pak, saya paham. Tetapi coba Bapak lihat kondisi keluarga kita, Putri sebentar lagi lulus SMA dan harus kuliah. Aku sudah pacaran lama dan akan segera menikah.
Dan yang terakhir tentang Ibu Pak, Ibu sedang sakit berat dan dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya pengobatan serta perawatannya. Coba Bapak pikir baik-baik.
”Setelah aku berkata seperti itu, Bapak diam sejenak dan langsung masuk kedalam rumah tanpa ada sepatah kata pun.
Keesokan harinya, tak sengaja aku mendengar percakapan Bapak dengan pegawai pemerintah lewat hp.
Bapak akhirnya memberikan izin pembangunan bendungan. Aku pun sangat senang.
Mungkin Bapak luluh dengan segala pertimbangan yang kuberikan kemarin.
Ya mau bagaimana lagi? Memang keluarga kami dan warga desa lainnya juga sangat membutuhkan uang ganti rugi lahan tersebut.
Satu minggu kemudian dilaksanakan acara peletakan batu pertama sebagai simbolisasi dimulainya pembangunan bendungan.
Pejabat-pejabat Negara banyak yang hadir pada saat itu, disambut dengan riuh tari dan nyanyian dari warga desa.
Ritual adat pun menjadi hal yang penting sebagai bentuk penghormatan dan izin kepada arwah-arwah leluhur agar diberikan kemudahan dalam proses pembangan.
Untuk ritual adat ini, Bapak membeli lima ekor sapi yang dibunuh dan dibakar di tempat pembangunan.
Mungkin hal ini dilakukan selaras dengan cerita Bapak mengenai arwah Sang Pangeran yang masih mencari lima korban sebagai pengganti sapinya.
Selepas dari acara peletakan batu pertama, proses pembangunan bendungan langsung cepat dilaksanakan.
Kendaraan-kendaran besar dan alat-alat berat lalu-lalang masuk dan keluar desa.
Kamp-kamp untuk tempat tinggal para pekerja juga sudah dibangun. Uang ganti rugi lahan pun sudah mulai cair.
Setiap hari, selalu ada warga desa yang pergi ke kota untuk mengambil uang di bank.
Ada yang pulang dengan belanjaan-belanjaan kecil saja, dan sering juga yang pulang membawa kendaraan roda dua bahkan roda empat.
Bapak sendiri mendapatkan uang tambahan selain ganti rugi lahan karena statusnya sebagai kepala desa dan perannya dalam proses pembangunan bendungan.
Jumlah uang tersebut sudah bisa menjamin Putri, adikku yang akan melanjutkan kuliah, aku yang akan menikah beberapa bulan lagi, dan yang paling penting, Ibu bisa dirawat dengan baik di rumah sakit tanpa perlu khawatir tentang biaya.
Selama beberapa bulan, pembangunan bendungan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
Keadaan yang baik-baik saja ini tak bertahan lama sampai sebuah kejadian mengerikan terjadi.
Dua orang pekerja yang sedang berlindung di dalam mobil truck saat hujan turun, tersambar petir dan tak satu pun dari mereka yang terselamatkan.
Hanya berselang beberapa hari saja, kejadian yang tak kalah mengerikan terjadi lagi. Salah satu pekerja tertabrak mobil teman pekerjanya sendiri.
Menurut pengakuan dari pekerja yang mengendarai mobil, ia tak melihat siapa pun di depannya, dan ia tiba-tiba saja mobilnya menabrak seseorang.
Beberapa saksi juga menuturkan bahwa korban yang tertabrak seperti tidak sadar bahwa sedang ada mobil yang melintas dijalan.
Dari dua kejadian mengerikan tersebut, banyak pekerja yang mulai mengundurkan diri karena ketakutan.
Warga desa sendiri ramai dengan cerita bahwa tempat pembangunan bendungan tersebut merupakan tanah panas dan akan menelan banyak korban.
Akhirnya proses pembangunan bendungan ini benar-benar berhenti ketika salah satu pekerja kembali meninggal mendadak karena serangan jantung.
Tetapi anehnya menurut pihak keluarga, korban selama hidup tak pernah memiliki riwayat penyakit jantung.
Mulai saat itu, tak ada lagi yang ingin bekerja membangun bendungan.
Semua pekerjanya pulang dan menganggap bahwa tempat tersebut merupakan tempat terkutuk.
Ketika proses pembangunan bendungan mulai terbengkalai, para pejabat pemerintahan sering datang ke rumah untuk bertemu dengan Bapak.
Mereka meminta saran dan jalan keluar dari Bapak agar pembangunan bendungan dapat dilanjutkan.
Mereka pun sampai bersedia memberikan banyak uang jika Bapak dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan ini.
Namun Bapak sepertinya sudah ketakutan dengan korban-korban yang berjatuhan, sehingga Ia hanya bisa menolak permintaan dari para pejabat tersebut.
******
Lima tahun telah berlalu, dan bendungan tersebut telah berdiri kokoh menjadi kebangaan desa serta daerah. Aku sudah menikah dan keluarga kami pindah ke kota.
Bapak sudah berhenti menjadi kepala desa dan membuka sebuah toko bangunan yang cukup besar.
Tak hanya itu, Bapak juga mempunyai perusahaan jasa transportasi yang cukup terkenal di daerah kami.
Mungkin aneh tiba-tiba saja bendungan tersebut telah selesai dibangun jika sebelumnya proses pembangunanya pernah dihentikan. Memang semua kejadiannya serba tiba-tiba.
Jadi, sekitar empat tahun lalu, pembangunan bendungan ini tiba-tiba saja kembali dilanjutkan.
Pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat untuk kembali bekerja di tempat tersebut dan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang mengerikan.
Aku juga ingat, sehari sebelum pemerintah mengumumkan pelanjutan proses pembangunan, Bapak pulang ke rumah saat tengah malam dan sepertinya dari arah tempat pembangunan bendungan.
Pakaian bapak penuh dengan darah sehingga aku pun kebingungan dan diliputi banyak tanya.
“Pak, kenapa pakaiannya bersimbah darah seperti itu?”
Bapak tidak menjawab. Ia langsung ke kamar mandi dan mencuci pakaiannya. Raut wajah Bapak terlihat sangat kelelahan. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja terbesit dalam pikiranku tentang perkataan Bapak dahulu,
“Harus lima korban nak, harus lima.”
Penulis akrab disapa Gratio. Lahir di Kupang 19 Juni 2002. Kini sedang mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya Malang. Dapat ditemui di Ig: @sostroberibe