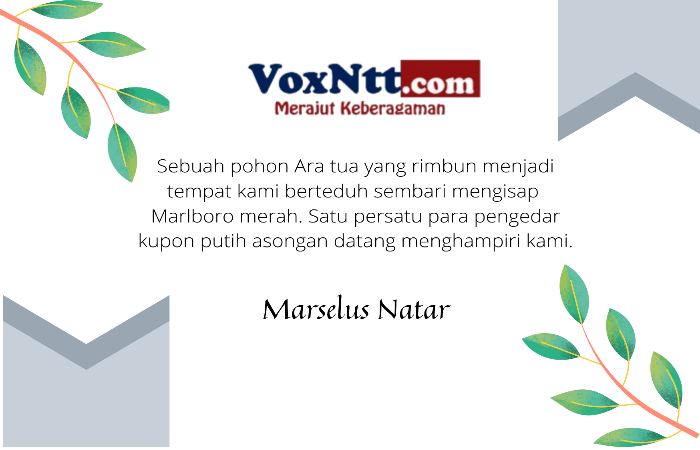Oleh: Marselus Natar
Matahari setinggi galah di atas puncak Ranaka. Sepasang gagak putih terbang merendah, berjibaku di antara kabut-kabut dan gerimis.
Gadis-gadis kecil dengan langkah pasti menyisir rimbun semak dan belukar sepanjang hutan lindung Rana Mese. Sesekali mereka melintasi
jalan raya Borong-Ruteng.
Kepala mereka menjunjung seikat kayu, sedang di punggung bakul-
bakul berisi sayuran bagai bersanding.
Gerimis tak kunjung usai, persis segumpal daging bayi rusa yang diawetkan dalam sebuah botol sopi bakar menyala. Awetnya tak lekang waktu.
Tidak ada yang dapat terjangkau mata, sejarak satu meter pun. Kabut-kabut menjalar di tanah. Rana Mese merupakan tempat paling misterius jika dilalui pada musim dureng seperti ini.
Sebuah pertarungan yang paling mengerikan adalah melawan kabut-kabut, melawan dersik angin yang mendesau dari balik hutan belantara, melawan derik jangkrik bak menjerit, atau suara monyet mengerih.
Aku dan Demus telah mengalami dan merasakan suatu kengerian dibalik
pertarungan itu. Nyali saja tidak cukup.
Sebagai bandar kupon putih, kami selalu menunggu para pengedar asongan yang datang dari berbagai kampung.
Setiap malam aku dan Demus,
menghabiskan waktu di sana. Sebuah pohon Ara tua yang rimbun menjadi tempat kami berteduh sembari mengisap Marlboro merah.
Satu persatu para pengedar kupon putih asongan datang menghampiri kami.
Tidak ada percakapan yang panjang selain menanyakan angka yang keluar pada hari yang bersangkutan, menyetorkan uang kepada pemenang, serta penyetoran angka dan uang pembelian angka pada hari yang bersangkutan.
Tidak lupa pula, kami berikan komisi kepada para pengedar kupon putih asongan tersebut. Setelah semuanya terpenuhi, satu persatu para pengedar kupon putih asongan pulang.
Sedang aku dan Demus tetap di sana, merekap kembali angka-angka yang telah disetorkan. Demikian hal tersebut kami lakukan setiap malam bahkan
hingga subuh.
Suatu pekan di bulan Desember, hujan deras disertai angin kencang melanda tempat kami.
Banjir dan longsor terjadi di mana-mana. Hampir semua warga persis hanya berada dalam rumah. Demikian pun aku dan Demus.
Para pengedar kupon putih asongan pun tak pernah menunjukkan batang hidung mereka kepada kami. Mayoritas pengisi angka kupon putih pun
turun drastis.
Kecuali orang-orang di sekitar tempat tinggal kami. Adalah Pius Sengsara,
seorang pria paruh baya yang baru saja membangun bahtera rumah tangga beberan bulan lalu, pagi-pagi benar mengunjungi rumahku. Piuk, demikian sapaan akrabnya, tampak tergesa-gesa.
Sedangkan kepalanya bagai menjunjung bintang gemintang, wajahnya berseri-beraura.
Setibanya di depan pintu rumah, ia lalu mengetuk pintu dengan keras. “Siapa?”, tanyaku pura-pura tidak kenal.
“Ole,.. Buka cepat dulu ta eh! Saya, Piuk, e”, sahutnya dalam rada mendesak. “Ole,.. Sabar ee.” Aku menjawabnya sembari melangkahkan kaki menuju pintu.
“Kau ada perlu apa pagi-pagi begini ta! Bikin ganggu orang tidur saja. Masuk sudah, kita dua duduk dan ngobrol di dapur saja e. Biar sambil seduh kopi.” Aku merayunya, sebab istri dan anak-anakku masih tidur.
“Begini ee, saya ini bertamu pagi-pagi buta karena semalam saya dapat mimpi baik. Saya bermimpi, Lopo Bebot meminta bantuan saya untuk memotong salah satu dari rumpunan bambu yang berada di Wae Mok. Saya pun memotong bambu yang dimaksud sesuai dengan permintaan Lopo Bebot. Nah, tadi pagi saat siuman, saya bingung bagaimana mencakar atau menafsirkan mimpi tersebut agar terejawantahkan ke dalam angka-angka. Kebingungan saya
terletak pada memilih dua kalimat berikut; Piuk Memotong Bambu Satu, P=16, M= 13, B=2 dan satu = 1. Saya sudah pikirkan untuk mengisi empat angka yakni, 6321. Rumusan kalimat
kedua yang muncul dalam pikiran saya adalah, Satu Bambu Dipotong Piuk, , Satu= 1, B= 2, D= 3, P=16, menjadi empat angka juga, yakni 1236. Apa pendapatmu terhadap dua opsi tadi?” ujar Puik serius.
Entah apa yang mengerayangi hati dan pikiranku, sehingga pagi itu aku seolah-olah hilang ingatan tentang kupon putih. Terhadap pendapat yang disodorkan oleh Piuk, terkait bagaimana mencakar atau menafsirkan mimpinya, sepertinya tidak terlintas dalam benakku. Aku bengong.
Sebatang pulpen dan secarik kertas kubiarkan berlabuh di tangan. Sedang Piuk sibuk melinting daun koli untuk dijadikan rokok.
Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba kakekku mendeham dari tempat tidurnya. “Tidak semua
mimpi ditafsirkan secara suka-suka. Mimpi bisa jadi petunjuk, entah sukacita atau petaka, di kemudian hari.” Ujarnya sembari melangkahkan kaki menuju tempat kami duduk.
Sontak, situasi dan keadaan semakin runyam. Semuanya sunyi. Mimpi itu melampaui kengerian di balik
hutan belantara Rana Mese.
“Konon, mimpi tidak pernah dikaitkan dengan angka. Betul, bahwa waktu itu belum ada judi kupon putih. Mimpi selalu dikaitkan dengan sesuatu yang
akan datang dan menimpa kehidupan dari sang empunya mimpi. Menurut saya, mimpi memotong bambu adalah celaka. Malapetaka akan menimpa kehidupan keluarga kalian. Saya tidak sedang mengutuk, mendoakan sesuatu yang tidak baik, atau menghalangi upaya kalian dalam menafsirkan mimpi tersebut. Saya hanya memberikan saran, selain kalian ejawantahkan mimpi itu ke dalam angka-angka, tolong ditafsirkan juga dari segi kebiasaan turun-temurun moyang kita, yakni mencari makna yang sesungguhnya dari mimpi tersebut kepada orang-orang tua di sini.”
Kata-kata yang disampaikan oleh kakek benar-benar membuat suasana semakin mencekam. Sebatang pulpen dan secarik kertas yang tadinya
berlabuh di tanganku, kini jatuh dan tergeletak di atas lantai.
Piuk termangu sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding. Aku melihat tubuhnya seperti orang kelelahan.
Pasrah bersandar di bahu dinding yang
kumuh. Pernyataan yang tersingkap dari bibir kakek menusuk sum-sum tulang punggungnya.
Piuk terlelap dalam mimpinya yang pelik dan penuh misterius untuk diuraikan.
“Bagaimana pun juga, mimpi itu tetaplah mimpi. Aku tetap mengartikannya dalam angka-angka. Menafsirkan mimpi dengan cara klasik sebagaimana dikatakan kakek adalah tradisi kuno yang telah sirna dalam arus zaman. Tuliskan untukku angkat 1236. Aku yakin besok angka itu akan keluar dari Hongkong.” Ujar Piuk rada kesal.
Aku lalu mengikuti permintaannya.
Hari pun berganti. Angka yang diisi Piuk melambung jauh. Angka yang keluar dari Hongkong jauh dari impian Piuk.
Atas peristiwa itu, hari-hari hidup Piuk bagai kehilangan roh kehidupan. Hati dan pikirannya selalu dihantui bayang-bayang mimpi yang tak lekas pergi.
Kehidupannya bagai orang-orang di panti rehabilitas. Bagai dedaunan di tubuh angin. Segalaimpian untuk mendapatkan uang tanpa keringat dan lelah bagai menjaring angin.
Segalanya menjadi sia-sia belaka. Siapa sanggup menahan amukan waktu? Lajunya bagai pelor sebuah revolver yang menembus ruang dan waktu. Yang menghadang pasti tercabik.
Melihat hari-hari hidup Piuk yang sia-sia belaka, istrinya pun depresi yang mengarah pada psikosomatik. Kian
hari tekanan psikosomatik itu kian berat. Langkah lakunya berubah total.
Sesekali ia menggoreng tinjanya sendiri untuk di makan. Puncak paling tragis dari apa yang dialaminya
adalah ketika ia menghabiskan nyawanya sendiri dengan cairan pestisida sejenis Roundup di
belakang rumah tempat mereka tinggal.
Peristiwa itu bagai penggenapan atas mimpi Piuk saban waktu. Suara ratap tangis mengalir deras dari berbagai mulut warga kampung. Mimpi itu mesti
menjelma histeris yang diwarnai ratap tangis tak terkatakan.