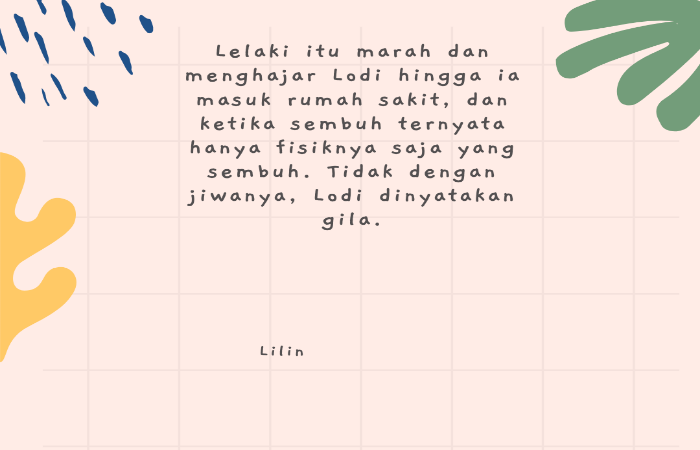Oleh: Lilin
Harusnya, saat ini usianya sudah 22 tahun. Ia pantas untuk menyandang gelar sarjana. Mamanya telah benar-benar merampas hak kebebasannya. Sebenarnya tidak saat ini saja, sejak tujuh tahun lalu tepatnya setelah kematian ayah kandungnya, kebebasan itu telah dihabisi dari kehidupan Lodi.
“Mama, akan menikah lagi.”
Ia mendengar pamit ibu kandungnya untuk menikah lagi dengan seorang lelaki tetangga kampung.
“Tapi, Ma. Apa tidak cukup kita hidup berdua saja?” Sore itu menjadi akhir kebebasan mengeluarkan pendapat baginya.
***
Perumahan ini hening. Mereka pindah siang itu ke kampung sebelah karena Mama Lodi memutuskan menikah dengan pemuda pilihan, setelah sepeninggalan ayahnya. Aku kesepian, tidak ada lagi teman menyenangkan sepertinya. Meskipun banyak teman-teman lain namun tidak ada yang mengalahkan kepandaian Lodi dalam mengerjakan soal-soal Matematika.
Meskipun hanya kampung sebelah, rumahnya cukup jauh dari rumahku. Dengan sepeda ontel sesekali aku mengunjunginya, meskipun tak jarang yang kujumpai hanya pagar hitam tinggi dengan halaman luas yang kosong.
Matahari mulai turun, dan langit-langit bersemu merah. Bulan sepertinya akan segera hadir, ketika kutinggalkan rumah Lodi minggu ini. Seperti biasanya setiap akhir pekan kita saling berkunjung, namun sudah beberapa pekan Lodi tidak pernah datang ke rumah, begitu juga sebaliknya tak pernah sekalipun ia menemuiku meskipun suara di kerongkonganku menjerit-jerit memanggilnya.
“Hai, siapa kamu?” Sebuah sapaan mengagetkanku.
Seorang perempuan seusiaku, dengan rambut sedikit kusut dan kotor mengembalikan ingatkanku dari kenangan 7 tahun. Ia mengenakan kaos biru muda dengan bawahan celana hitam. Wajahnya sedikit terlihat lebih tua dariku.
“Saya, Nisa,” jawabku.
“Sepertinya kamu bukan anak sini.” Lagi suara perempuan itu terdengar memperhatikanku. Bibirnya tersenyum.
“Iya, saya memang dari kampung sebelah, tapi sejak 7 tahun lalu bersama keluarga pindah ke kota. Kamu sendiri, siapa namamu?
Kali ini tidak hanya senyum yang diperlihatkannya kepadaku, ia tertawa lebar. Entah apa yang membuatnya tertawa.
“Aku? Siapa ya, Aku?” Ia kembali tertawa.
Aku ikut tertawa, sepertinya ia benar apalah artinya sebuah nama bagi kita. Yang terpenting adalah keakraban dalam perjumpaan ini. Kita saling ngobrol, mulai tentang musik kesenangan, film, dan pelajaran favorit kita di masa-masa sekolah dahulu, Matematika. Hal itu mengingatkanku dengan Lodi.
“Kamu kenal dengan seorang anak tidak, bernama Lodi. Ia juga jago Matematika?”
Ia menunduk di bangku taman.
“Aku tidak tahu, tapi mungkin ada yang pernah bernama Lodi di kampung ini.” Ia kembali terdiam, wajahnya muram.
“Aku harus pulang, besok kalau kamu mau datang saja ke sini lagi.”
Aku mengiyakan. Entah mengapa perasaan rindu kepada Lodi tergantikan sosoknya meskipun hanya dengan sekali bertemu. Ia berjalan menjauh ke arah barat.
“Hai, rumahmu nomor berapa?” Ia terus saja berjalan tanpa menoleh ke belakang, hanya lambaian tangannya ke langit-langit memberi isyarat angka 2.
***
Keesokan harinya aku membawa buku-buku Matematika tugas dari kampus yang mesti diselesaikan. Semestinya tahun ini ijazah kelulusan bisa kuperoleh. Namun masalah ekonomi yang mengharuskan keluarga kami pulang kembali ke kampung, membuatku mengambil cuti di tahun kemarin.
Tak lama kemudian ia datang, ia senang sekali ketika melihat apa yang kubawa.
“Hai, Nisa. Maaf ya terlambat. Wow Matematika?”
“Maaf ya, aku membawa tugas-tugas kuliahku. Banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi aku tak ingin kehilangan waktu bertemu denganmu.”
Matanya bersinar-sinar tatkala melihatku mulai mengutak-atik rumus kalkulus.
“Wow, ini salah satu favoritku.” Tangannya mulai bergerak mengambil pensil dari genggamanku. Menulis rumus, menghitung, dan menemukan hasil akhir jawabannya. Tak terasa dalam waktu lima belas menit ke sepuluh soal diselesaikannya tanpa kesulitan.
“Wow, luar biasa cepat sekali. Kamu hebat, aku saja tak mungkin bisa secepat ini.”
Ia tersenyum, matanya bersinar sendu.
“Kalau dari cara mengerjakan kurasa gelar sarjana Matematika layak untukmu.” Kami tertawa bersama-sama.
“Aku sudah menjadi sarjana semenjak lima tahun lalu,” gumam perempuan itu. Aku tak paham dengan maksudnya. Lima tahun lalu? Itu berarti semenjak ia berusia sekitar enam belasan tahunan.
Sore itu kita habiskan dengan berdiskusi tentang matematika dan cita-cita selanjutnya.
“Oia, apa pekerjaanmu saat ini?”
Ia kembali murung, dengan merapikan rambut keritingnya yang sedikit kusut dia bercerita.
“Saat ini, pekerjaanku hanya menghitung bintang, nyamuk, cicak, dan suara burung-burung malam.”
“Lho, kok?”
Aku tertawa mendengar lelucon yang baru saja keluar dari mulutnya.
“Iya, lucu ya? Aku selalu tertawa setiap selesai menghitung. Ibu selalu marah ketika aku berhenti menghitung. Salahku dimana coba?”
Aku menggeleng kepala, antara tidak tahu dimana kesalahan perempuan ini atau alasan ibunya memarahinya setiap ia selesai menghitung. Aneh ….
Seaneh diriku, bahkan setelah pertemuan kedua juga belum mengetahui siapa nama perempuan ini. Gadis berambut keriting kusut dengan wajah yang seringkali berubah-ubah, yang suka ngobrol dan berdiskusi soal-soal matematika di taman.
“Aku harus pulang.” Wajahnya berubah tegang.
“Kalau tidak ibu akan marah dan mencariku.”
***
Besoknya, aku kembali datang ke taman menjelang sore. Kali ini ia tak juga datang, beberapa waktu kutunggu tak juga tampak perempuan dengan rambut keriting kusut itu.
Ingatanku kembali kepada sosok Lodi teman masa kecil yang membuatku merasakan kehilangan.
Aku tak ingin kehilangan lagi, maka kuputuskan mengunjungi rumah gadis itu. Rumah nomor 2 seperti yang disyaratkan kepadaku di perjumpaan pertama lalu.
Aku tiba di sebuah rumah kayu kecil, lebih tepatnya sebuah gubuk nyaris roboh. Sunyi dan sepi, di samping rumah itu hanya ada semak belukar yang merimbun. Tidak ada siapapun, rumah ini tidak terawat, meskipun di sampingnya ada bangunan rumah besar dengan pagar hitam tinggi menjadi pembatas.
Untuk memanggil penghuni rumah kayu itu, aku tidak tahu siapa nama gadis itu. Ah bodohnya aku.
Cukup lama aku berdiam beberapa meter dari rumah itu. Sampai seorang perempuan tua dengan rambut yang sudah dipenuhi uban mengagetkanku.
“Maaf, Neng mencari siapa?”
“Ah, saya mencari gadis penghuni rumah ini.” Telunjuk kuarahkan tepat ke pintu rumah kayu itu.
“Ndak, salah neng?” Keterkejutan menyergapnya.
“Iya, Bu. Gadis yang berambut keriting dan pandai Matematika.”
“Oh, Lodi.”
Aku tak lagi mampu mendengar dengan jelas apa yang diceritakan perempuan itu. Semenjak ia menyebutkan nama Lodi.
Sampai siang ini, di hadapan nisan bertuliskan nama sahabat masa kecilku. Air mata tak lagi bisa kubendung. Lodi telah meninggal lima tahun lalu.
Setelah pernikahan ibunya dengan suami barunya, semua harta peninggalan Almarhum ayah Lodi dipindahkan menjadi milik mereka berdua. Hal itu membuat Lodi kesulitan membiayai sekolahnya. Sampai puncaknya ketika Lodi lulus SMU dan ingin meminta biaya guna melanjutkan kuliah seperti amanah Almarhum ayahnya.
Lelaki itu marah dan menghajar Lodi hingga ia masuk rumah sakit, dan ketika sembuh ternyata hanya fisiknya saja yang sembuh. Tidak dengan jiwanya, Lodi dinyatakan gila. Selama dua tahun ia dikurung di gubuk kayu sebelah rumah mewah mereka.
Sampai ia ditemukan meninggal dengan kepala berlumuran darah, Lodi bunuh diri dengan menghantamkan batu ke kepala sendiri.
Ayah tiri dan ibunya pergi ke kota karena malu dan tidak tahan dengan gunjingan orang.