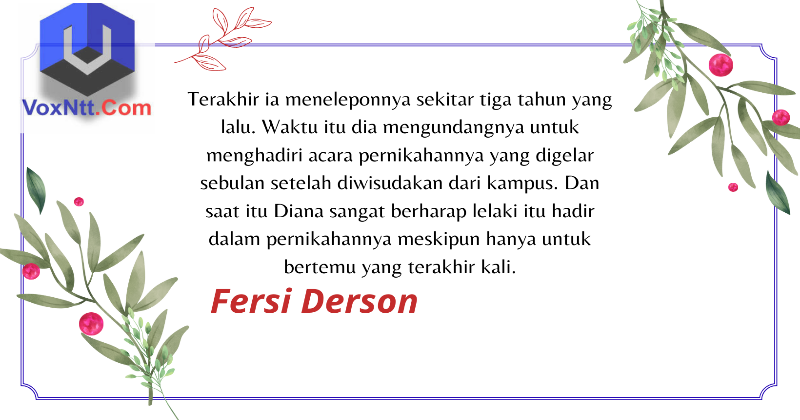Diana
Dalam kesepian seorang diri, Diana tiba-tiba menerawang kisah yang pernah terjadi. Bukan tentang hari-hari mereka bertengkar hebat dan membuatnya berpisah dengan sang suami.
Melainkan kisah yang berakhir lima tahun lalu, tepat saat ia memutuskan menikah dan meinggalkan lelaki itu. Kisah yang membuatnya jatuh cinta dan bahagia.
Ivan. Ya nama lelaki itu Ivan. Masih tergambar jelas dalam benaknya. Dengan sigap ia mengambil handephone yang terletak di atas meja. Ibu jarinya menari. Hatinya berharap panggilan yang ia lakukan tersambung dengan lelaki itu. Ini adalah panggilan pertama setelah menikah.
Namun, wajahnya berubah lesu ketika nomor telepon yang ia hubungi tidak aktif, dan mungkin lebih tepat nomornya sudah tidak dipakainya lagi.
Terakhir ia meneleponnya sekitar tiga tahun yang lalu. Waktu itu dia mengundangnya untuk menghadiri acara pernikahannya yang digelar sebulan setelah diwisudakan dari kampus.
Dan saat itu Diana sangat berharap lelaki itu hadir dalam pernikahannya meskipun hanya untuk bertemu yang terakhir kali.
“Van, aku harap, besok engkau hadir di pernikahanku. Engkau adalah tamu istimewaku.” Katanya dengan bulir-bulir bening di pelupuk matanya.
“Jika kuat aku akan datang.” Jawab lelaki itu ketus.
Siapa lelaki yang cukup berani datang ke pernikahan wanita ia cintai? Lalu menyiksa diri menyaksikannya bersanding dengan lelaki lain? Pikir lelaki itu. Ia urungkan niatnya untuk datang ke pernikahan itu.
Tentu saja demi menjaga perasaannya sendiri dan barangkali perasaan perempuan itu. Ia hanya menyampaikan sepenggal kalimat untuk mengucapkan selamat berbahagia melalui pesan WA yang hanya dibalas perempuan itu dengan gambar air mata.
Keesokan pagi setelah itu, Diana menerima pesan yang mengejutkan.
“Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Terima kasih engaku pernah menjadi seseorang yang istimewa bagiku. Terima kasih engkau memberiku banyak pelajaran. Kini aku pamit pulang ke kampungku. Selamat tinggal…”
Itu artinya Diana tidak bisa melihatnya lagi dan mungkin untuk selamanya, sebab mereka tinggal terpisah di dua kota kecil yang berbeda pulau.
Sejak itulah mereka tidak bertemu dan bertelepon. Namun, bayangan lelaki itu selalu hidup dalam ingatannya sampai setelah ia berpisah dari suaminya sekarang.
***
Sebenarnya bukan soal ekonomi yang membuat mereka berpisah. Barangkali karakter atau sifat dasar merekalah yang tidak cocok. Diana cepat tersinggung. Sementara lelaki itu suka emosi dan membesar-besarkan hal sepele. Memang sejak dahulu Diana merasa bahwa ditakdirkan bukan menjadi istrinya.
Dulu, ia mau menikah dengannya lelaki yang bernama Rian itu, karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Ia memang sudah mengenal. Usianya lebih tua lima tahun dari usianya. Mereka dijodohkan untuk mempererat hubungan persahabatan orangtua mereka.
“Ayah sudah bersepakat dengan Pak Niko, pernikahan kalian yang akan mempererat hubungan persahabatan antara keluarga kita dan keluarganya.” kata ayahnya.
“Tapi bukankah pernikahan yang membahagiakan itu jika dilakukan dua orang yang saling mencintai!” katanya.
“Yah, ayah yakin kamu akan mencintainya, Nak. Dia tak kurang apa. Cakep. Kaya raya. Punya pekerjaan bagus. Ayah yakin kamu akan hidup bahagia bersamanya.”
“Tapi ayah…”sebelum kalimatnya terucap tuntas, sang ayah lebih dahulu memotong.
“Cukup… tak ada alasan. Jangan bikin ayah malu!”
Ketika ayahnya berkata begitu, Diana sudah tak bisa berargumen lagi. Apa pun kata orangt uanya, ia menurut sekalipun hatinya menolak. Ia tidak kuasa membantah apalagi melawan, meski kenyataan terlampau jauh dari harapan.
Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamar, membayangkan cinta yang bertumbuh subur akan segera gugur. Ia akan merelakan separuh jiwanya yang tertanam pada lelaki bernama Ivan, lelaki yang hadir dalam setiap embusan napasnya.
Perpaduan dua keluarga kaya raya dan terkenal di kota kecil itu membuat pesta pernikahan mereka yang digelar sebulan kemudian sangat mewah. Sudah barang tentu menghadirkan pejabat-pejabat di bidang pemerintahan, tempat ayah mereka bekerja.
Namun, apa gerangan Diana tidak merasakan bahagia? Pikirannya melayang jauh tak terarah melampaui keberadaannya dalam tenda acara itu. Memang ia menikah tanpa rasa cinta sedikit pun Rian.
Namun, ia hanya berharap seiring berjalannya waktu, cinta akan bertumbuh untuk lelaki yang menjadi kenyataan hidupnya sekarang. Lelaki yang dipanggilnya suami tempat ia bermanja-manja. Ia berharap waktu hadir menumbuhkan cinta yang utuh. Karena itu, ia menjalani hari dengan sebaik mungkin dan berharap sesuai dengan keinginan dan hasrat suaminya.
Ia selalu menjaga sikap demi menyenangkan hati sang suami.
Namun, justru saat-saat begitulah ada celah-celah yang membuat sang suami mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Ada saja hal sepele yang membuat mereka berujung pada perbedaan pendapat.
Lalu mulai saling mempertahankan pendapat masing-masing. Tak ada yang mau mengalah. Sampai akhirnya berujung pada pertengkaran hebat sampai terdengar ke tetangga.
Suatu pagi yang yang cerah, tapi tak secerah itu susana batin mereka. Mereka adu mulut lagi dan membuat Rian tampak begitu emosi dan hendak melepaskan tali kontrolnya. Melihat itu Diana pergi dari rumah tak tahu ke mana.
Tak lama setelah itu, Rian pergi ke kantornya. Namun, susana dalam dadanya masih sesak dengan kemarahan dan emosi yang mendidih.
Karena tak kuasa memegang kendali, di kantor ia melempiaskan emosinya pada seorang bawahan yang datang terlambat. Ia memukulinya sampai babak belur hanya karena datang terlambat.
Sungguh merupakan kesalahan yang fatal dan membuatnya langsung dipecat dengan tidak hormat oleh atasannya. Sudah menjadi barang tentu Dianalah sasaran kemarahannya. Sampai di rumah, ia menghajar istrinya sampai babak belur dan mengusirnya dari rumah.
Sejak saat itu, Diana tinggal di rumah rumah orang tuanya dan memutuskan untuk berpisah. Pernikahan yang terhitung tiga tahun belum dikaruniai buah hati. Tuhan mungkin tidak menghendaki seorang anak lahir dalam keluarga yang diselimuti suasana panas dan tidak bertahan lama. Sebab, memiliki anak tidaklah gampang dan membutuhkan tanggung jawab besar.
***
Sauatu hari, Diana menikmati suasana pantai yang tak jauh di pinggir kota. Melihat pantai, itu, ingatan tentang Ivan hadir kembali dalam kepalanya. Membayangkan saat duduk berdua di bawah pohon.
Bermain kejar-kejaran sambil terpingkal-pingkal menertawakan tingkah mereka sendiri. Kadang lempar-lemparan dan siram-siraman air lalu menghabiskan minuman di bawah pohon.
“Jangan pernah tinggalkan aku.” suaranya tulus dan mendalam. Kepalanya tersandar di pundak kekasihnya.
“Seorang lelaki sejati tak berani meninggalkan perempuan yang mencintainya dengan tulus.” kata lelaki itu.
Cahaya senja kemerah-merahan. Di kejauhan sana ada pelaut melepas jala. Sambil menunjuk-nujuk ke sana dan entah apa yang mereka bicarakan. Air laut, pasir, pantai, dan mungkin penjual kelapa dan penjual bakso di pinggir pantai menjadi saksi kebahagiaan mereka.
Semua yang ada di bumi seolah tersenyum mendukung kebahagiaan mereka. Ivan miliknya dan dia milik Ivan. Sepasang mata seolah diciptakan hanya untuk menatapnya.
Pun sepasang tangan yang lengkap dengan sepuluh jari seolah hanya untuk bertautan dengan jari lelaki itu.
Di sebuah toko swalayan Diana terkejut saat matanya mendapati lelaki berbadan tegap.
Ia memakai kemeja biru muda, lengannya terguling sampai siku. Di tanggannya ada kantong plastik belanjaan. Di pundaknya sebuah ransel berukuran sedang. Ia hendak melangkah meninggalkan toko.
Dengan cepat Diana menaruh kembali sepatu yang dipegangnya lalu berjalan cepat mengejarnya.
“Ivan…” ia memanggil dengan suara agak keras.
Ivan! Ya benar dia. Ia sontak menoleh lalu terkejut saat tatapan mereka bertemu.
“Diana…” katanya.
Diana terus mendekatinya sambil menatap dalam-dalam. Mata bulat lelaki itu masih akrap di benak. Kulit kecolatan masih lekat dalam ingatan. Hidungnya, rambutnya, dan semua tetangnya masih utuh dalam ingatan Diana. Dia masih benar-benar lelaki yang membuatnya jatuh cinta. Tanpa pikir panjang ia memeluk tubuhnya erat.
“Apa kabar?” tanya Diana..
“Aku baik. Kamu bagaimana?” kata lelaki itu.
“Baik juga”
“Oya, kamu kenapa bisa di sini?”
“Aku ada tugas dari kantorku selama tiga hari di kota ini.” kata lelaki itu. “Lalu kamu sendiri dengan siapa?”
“Sendiri”
“Kok sendiri. Suamimu?”
“Kami tidak cocok dan sudah lama berpisah.” Jawabnya Diana, lesu.
Lelaki itu terkejut.
Ini perjumpaan pertama setelah enam tahun lalu. Sebuah perjumpaan yang tidak pernah dibayangkan.
Setelah menyelesaikan perbelanjaan, mereka menuju warung bakso, tidak jauh dari situ. Siang yang terik dan tapi tak terasa. Sambil menyantap bakso, mereka bercerita perihal kehidupan masing-masing.
Diana meceritakan kehidupan rumah tangganya dan pertengkaran mereka setiap hari. Dan sampai ia mengambil keputusan untuk bercerai dengna lelaki itu.
***
Ini malam terakhir Ivan berada di kota itu. Tugas selama tiga hari sudah selesai. Besok ia kembali ke kotanya. Tentu saja malam ini tidak dilalui begitu saja. Mereka habiskan malam di pantai yang sering mereka kunjungi dahulu. Mereka begitu mesrah laiknya dahulu saat berpacaran.
“Van…” katanya sambil menatap lelaki itu dalam-dalam.
“Iya, ada apa?”
“Apakah aku boleh meminta sesuau kepadamu?” suaranya begitu tulus.
“Ya, katakanlah.”
“Besok engkau akan pergi. Jika engkau tak akan ingin aku tersiksa di sini, bawalah aku pergi bersamamu.”
Kata-kata yang sulit diucapkan, tetapi lebih berat jika ia tidak katakan. Ivan menatapnya. Tatapannya dalam sekali. Di matanya ia menemukan ketulusan dan harapan.
“Ya, besok aku akan membawamu.” Lalu memeluknya erat.
Diana bahagia. Ia menemukan kembali cinta dan separuh jiwa yang hilang. Keesokan pagi mereka pergi. Diana meninggalkan kota itu. Meninggalkan orangtua dan pekerjaannya demi kebahagiaannya sendiri.
Penulis: Fersi Darson