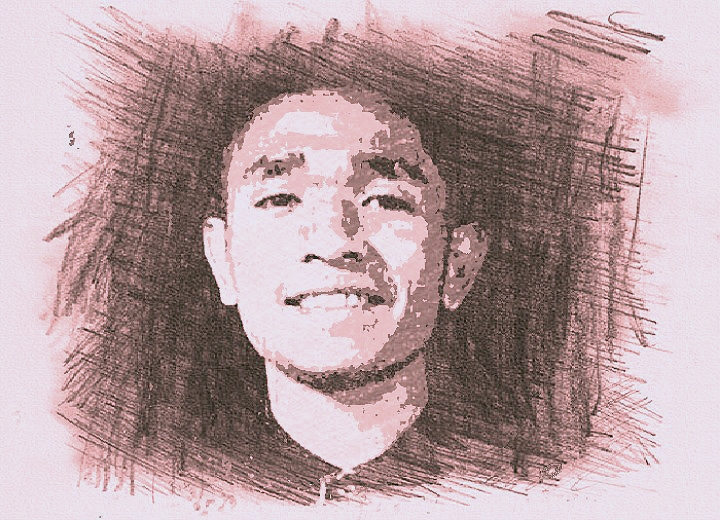Oleh: Rian Odel
Anggota KMK Ledalero
Ruang publik Indonesia sedang dihantui oleh konsep fundamentalisme berbasis agama. Ada oknum yang mengaku paling saleh menggunakan dalil-dalil agama untuk mengukur orang lain.
Jika ada pihak lain bertentangan dengan ajaran agamanya, akan dianggap kafir dan lansung diberi vonis negatif. Tanpa pengetahuan agama yang rasional, mereka telah membuat kekacauan pada ruang publik yang inklusif.
Praktik seperti ini tentu sangat jelas membuktikan bahwa sedang terjadi ketidakadilan dengan motivasi kedangkalan nalar beragama.
Agama tertentu dianggap sebagai dasar kehidupan bagi orang lain, padahal Indonesia merupakan negara plural. Menurut mereka, surga merupakan milik pribadi orang yang sepaham dengan mereka; di luar itu pasti menjadi penghuni neraka. Konsep ekstrim seperti ini pernah dihayati secara serius oleh Gereja dengan idiomnya yaitu, extra ecclesiam nulla salus.
Akibatnya, banyak orang merasa tidak bebas beragama. Etika keadilan yang ditawarkan oleh Emanuel Levinas menjadi jalan tengah yang paling pas untuk menyadarkan kembali kedangkalan kita dalam beragama di atas panggung publik Indonesia yang beranekaragam ini.
Kita didesak untuk keluar dari egoisme agama dan berbaur sekaligus mengakui agama lain dengan tidak memandang rendah mereka.
Etika Asimetris
Judul di atas memunculkan beberapa pertanyaan. Apakah mereka memahami ajaran agama dengan sangat mendalam? Mengapa mereka menjadi manusia ekstrim? Apakah mereka adalah korban yang mabuk dogma agama karena minim wawasan dan bagaimana solusinya?
Menurut saya, agama memiliki ajaran substansial yang selalu mengarahkan manusia untuk hidup baik. Tidak ada agama yang mengajarkan manusia untuk saling membunuh, menyegel rumah ibadah agama lain dan melegalisasi perang tanpa alasan yang akurat.
Ketidakadilan yang sering kita temukan bercokol di Indonesia merupakan akibat kedangkalan dalam memahami agama dan etika keadilan universal versi Emanuel Levinas. Dia selalu menekankan etika untuk menjadikan orang lain sebagai diri kita sendiri bahkan harus lebih dari itu. Exteriority And The Face merupakan judul umum yang membantu kita untuk keluar dari diri; dari dogma agama yang ketat ke dalam dogma kemanusiaan yang adil dan beradab.
Agama yang kita anut tidak boleh menjadi barometer untuk melihat kebenaran agama lain. Justru karena dalam agama kita, praktik ataupun pendidikan mungkin tidak menekankan kesamaan kemanusiaan, maka timbul huru-hara dalam merealisasikan ajaran agama tertentu ke dalam suatu ruang publik inklusif dan plural.
Indonesia adalah lahan subur terjadinya praktik agama yang salah, misalnya, penyegelan rumah ibadah dan perdebatan tentang dogma agama lain yang tidak memiliki relevansinya dengan agama kita. Pratik seperti ini menunjukkan bahwa kita masih terperangkap dalam keyakinan pribadi yang superior atau versi Levinas Totality. Dia mengatakan, “The other does not only appear in his face, as aphenomenon subject to the action and domination of a freedom ; infinitely distant from the very relation he enters, he presents himself there from the first as an absolute.”
Hal ini berarti bahwa kehadiran umat antaragama di Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak dan tanpa dominasi represif agama tertentu.
Praktik semacam ini masih subur kita temukan dalam realitas hidup beragama, padahal hak memilih agama tertentu adalah anugerah absolut yang tidak bisa digugat oleh pihak lain.
Kehadiran konsep fundamentalisme agama menjadi sebuah fenomana kontradiktif yang sekaligus mengajak kita untuk merefleksikan peran agama dalam kehidupan sosial sekaligus kita bercermin pada etika keadilan yang ditawarkan Levinas.
Ketika praktik fundamentalisme dan intoleransi merebak luas, dapat kita pastikan bahwa kemurnian sebuah agama menjadi sesuatu yang formalistis belaka. Kehadiran orang lain tidak lagi dilihat sebagai anugerah perbedaan yang indah tetapi sebaliknya dinilai sebagai musuh yang mengganggu. Lalu, apa itu agama? Apakah agama adalah sebuah sekolah untuk hidup yang baik atau institusi yang memproduksi fundamentalis?
Di sini, menurut saya, etika keadilan yang diajarkan Levinas menjadi ilmu pengetahuan yang mengalahkan atau menggugat eksistensi sebuah agama yang menyimpan atau memelihara fundamentalis.
Pantaskah kita menyebut agama sebagai institusi yang dianugerahkan Tuhan kalau umat-Nya menyegel tempat ibadah umat lain? Levinas mengatakan, “We Must explicate the power that beings placed in relation have of absolving themselves from the relation.”
Pendapat Levinas ini kalau dilihat dari perspektif agama sebenarnya sebuah ajaran mulia yang sangat membantu nalar umat antaragama untuk hidup berdampingan secara bebas.
Tempat ibadah harus membantu umat antaragama untuk secara bebas menjalankan ritual keagamaannya bukan malah disegel. Artinya, masih terjadi penjajahan berbasis agama. Tempat ibadah tidak boleh dilihat sebagai pagar pembatas agama satu dengan yang lain.
Menurut saya fenomena seperti ini bukan hanya masalah yang ada dalam tubuh para fundamentalis melainkan peran pemimpin agama gagal memberikan pendidikan agama. Maka argumentasi dari Levinas merupakan cahaya terang yang melampaui cahaya agama. Etika keadilan Levinas tidak terperangkap dalam ideologi agama tetapi merangkum kemanusiaan universal.
Hal seperti ini sulit kita temukan dalam realisasi hidup umat agama yang cacat akan kemanusiaan. Maka menurut saya, pendidikan dalam agama harus juga mengadopsi ajaran Levinas sebagai bagian dari pendidikan agama. Agama tidak boleh menolak ajaran keadilan kemanusiaan versi Levinas. Etika asimetris yang diciptakan Levinas harus dipandang sebagai tanggung jawab umat beragama untuk hidup saling mengakui dan menghormati bukan mengagungkan agama pribadi dan melecehkan agama lain.
Keadilan Dalam Etika
Keadilan selalu mengakui yang lain sebagai yang lain sesuai kondisinya; memberi ruang bagi yang lain sesuai kondisinya. Levinas menganjurkan agar keadilan yang harus dilakukan merupakan sebuah tanggung jawab subsitusi secara radikal; mungkin seperti Yesus.
“As nonviolence it nonetheles maintains the plurality of the same and the other. It is peace.” Demikian kata Levinas.
Keadilan seperti ini menuntut etika yang baik, bukan untuk mencari sensasi. Ketika masing-masing umat beragama membangun konsep seperti ini, maka tidak ada lagi kekerasan antaragama.
Hidup kita semakin kondusif karena saling menghormati esensi kemanusiaan yang lain. Dengan demikian maka konsep tentang ‘perdamaian’ tidak lagi sekadar teori yang ada dalam Kitab Suci tetapi muncul dalam relasi hidup bersama. Konsep yang dikonstruksi Levinas sangat bermanfaat dalam konteks pluralitas agama di Indonesia karena berisi kritikan terhadap cara membangun relasi yang tidak bermartabat.
Maka seharusnya paham kemanusiaan versi Levinas menjadi ilmu yang dipelajari dalam sekolah-sekolah yang berbasis agama sehingga kita tidak terpaku pada ajaran agama. Nalar manusia harus dipakai untuk menilai agamanya. Akal atau nalar merupakan hal substansial dari sebuah agama sehingga harus tetap dipakai secara waras (Peter Tan, 2018).
Kasus penistaan atau fanatisme mungkin menjadi akibat dari lemahnya nalar dalam beragama. Orang menaruh ketaatan mutlak pada ajaran kitab suci yang sebenarnya selalu bertumbuh dalam konteks tertentu dan dipakai untuk melecehkan pihak lain.
Di sini akal rasional menjadi irasional. Emanuel Levinas dalam etika wajah selalu menegur kita yang mengklaim diri sebagai orang saleh karena mempunyai agama tetapi mungkin tidak bertuhan.