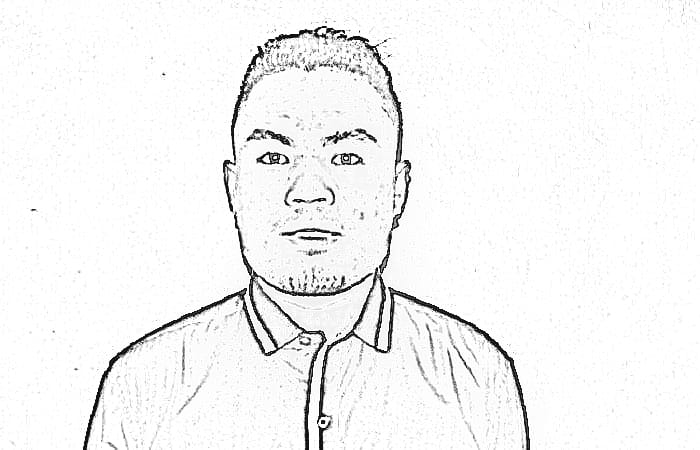Oleh: Florianus Jefrinus Dain
Ketua Centro John Paul II, tinggal di Ritapiret-Maumere
Salah satu pembacaan terhadap berbagai debat dan diskusi publik di media menjelang pilpres 2019 adalah berafiliasinya intelektual dengan para oligarki. Atau dengan kata lain perselingkuhan dan persilangan kepentingan antara para intelektual dengan oligarki melahirkan sebuah demokrasi yang compang-camping.
Alih-alih mengatakan intelektual berperan dalam sebuah demokrasi untuk membentuk sebuah tatanan kehidupan pemerintahan yang baik, justru terjebak dalam pengikisan demokrasi ke arah mempertahankan status quo dari oligark.
Gambaran demikian mengindikasikan bahwa dalam berbagai debat publik maupun diskusi, sebagian intelektual kita sedang terjerumus ke dalam suatu pola persinggungan kepentingan. Lihat dan saksikan posisi intelektual kita dalam setiap diskusi di media massa seperti televisi. Sebagian intelektual cenderung mengafirmasi dan merasionalisasi realitas sosial-politik untuk membela suatu posisi. Bahkan dalam keadaan salah pun mereka berusaha untuk membenarkannya. Tentu ini menjadi catatan serius bagi para intelektual yang tegerus dan tersedot ke dalam suatu rezim tertentu.
Hal ini mesti menjadi refleksi dan autokritik bagi para intelektual yang sedang bermain “api” di tingkat nasional. Atas nama mendukung calon tertentu, mereka merelakan pengetahuannya untuk membela walaupun ada nilai-nilai yang bertentangan dengan kenyataan moral.
Ada juga fenomena penggunaan data yang palsu demi suatu kesuksesan dalam sebuah pertahanan terhadapa rezim tertentu. Tentu ini fenomena ini menjadi salah satu parameter sekaligus indikator bahwa intelektual kita sedang narsis dalam keburukan.
Dalam setiap perdadaban dunia, peran intelektual sebenarnya ialah membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Menurut Seymour Martin Lipset sebagaimana dikutip Robert Brym, intelektual adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, terutama terlibat dalam produksi ide-ide ( Brym, 1993:2).
Ide-ide ini kemudian membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Atau Habermas menyebutnya sebagai model cendikiawan desisionistik. Mereka ini tidak terikat pada kepentingan tententu. Kehadiran mereka ialah membantu pemerintahan baik melalui kritik, maupun terlibat langsung dalam merancang arah bangsa yang baik. Maka tugasnya ialah membentuk good governance dengan kuasa pengetahuan yang dimiliki. Juga intelektual itu terlibat langsung dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Aliansi Oligarki
Namun kenyataannya, hari ini intelektual kita sedang bermain dengan para olgarki. Wacana yang mereka bangun sedang mempertontonkan persilangan itu. Contoh yang paling nyata misalnya bangunan wacana publik dari para pengamat politik yang terpolarisasi ke dalam fraksi politik tertentu.
Gejala ini sesungguhnya menunjukan intelektual kita sedang kehausan akan kekuasaan, kehormatan dan kekayaan. Bahwa persekongkolan dengan oligarki merupakan cara mereka untuk bersandar dan tetap eksis untuk memajukan nasib. Ada usaha untuk memindahkan stratifikasi sosial-ekonomi dengan membualkan pengetahuan yang dimiliki.
Mereka kemudian tersedot dalam suatu jaring kekuasaan dengan pretensi untuk mendapatkan kehormatan dan kekayaan. Akibatnya, kuasa pengetahuan yang dimiliki menjadi semacam senjata untuk mempengaruhi publik. Pengetahuan itu ditransfer dalam rangka membangun opini masyarakat terhadap elit politik tertentu.
Fenonema ini cukup berbahaya dalam sebuah proses demokratisasi. Sebab, kaum intelektual yang berafilasi dengan oligarki itu akan dengan mudah menggengenjot kesadaran publik dengan pengaruh pengetahuan yang dimiliki. Apalagi didukung dengan data-data yang fiktif. Akhirnya lebih lanjut ialah masyarakat tidak mampu lagi berpikir kritis dan selektif. Yang terjadi kemudian ialah masyarakat menelan dengan mentah-mentah produksi pengetahuan kaum intelektual.
Upaya pelanggengan itu dapat dilihat dari frame retorika yang menguak di media massa. Pada titik ini keresahan kita terhadap intelektual bangsa ini semakin tinggi. Padahal, semua elemen masyarakat mengharapkan posisi intelektual dalam suatu demokrasi untuk penjernihan kebijakan-kebijakan strategis sekaligus memberikan semacam pendidikan politik yang baik, justru tejebak dalam logika oligarkis.
Karena itu, masyarakat sendiri semakin dibodohi dengan retorika-retorika kaum intelektual yang cenderung mengorasikan pengetahuan dalam rangka merasionalisasikan suatu kekuasaan tertantu.
Intelektual Organik
Berhadapan dengan kenyataan yang cukup mencemaskan ini, akhirnya kita berharap akan hadirnya intelektual-intelektual organik di negeri ini. Konsep intelektual organik ini sendiri sebenarnya dicetuskan oleh Antonio Gramsci.
Gramsci memulai analisisnya tentang peran intelektual dalam suatu hegemoni kekuasaan. Ia menilai bahwa peran intelektual sangat penting sebagai bagian dari suprastruktur. Mereka merupakan suatu kelompok sosial yang otonom dan independen. Dalam dunia suprastruktur, kaum intelektual menampilkan fungsi organisasional dan konektif di dalam wilayah masyarakat sipil.
Gramsci mengharapkan intelektual organik bekerja dalam suatu sistem dominan. Sistem dominasi yang dilakukan ialah membangun sebuah ideologi perlawanan atas dominasi represif negara yang terjelma dalam diri elit politik.
Intelektual organik mesti membangun hubungan dengan masyarakat sipil dan memberikan kesadaran tentang fungsinya bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial politik.
Karena itu Gramsci menekankan tindakan intelektual organik sebagai manusia politik. Ia menawarkan pandangan yang lebih revolusioner. Bagi dia penting sebuah ideologi untuk mengubah masyarakat dan membentuk paradigma umum.
Gramsci mengemukakan pandangan bahwa ideologi tidak hanya eksis melainkan juga memiliki pengaruh sangat signifikan bagi perubahan historis. Ideologi dapat dilihat sebagai kekuatan material maupun politik.
Pada tahap ini ideologi berperan sebagai pembebasan dari keterkungkungan. Hal ini hanya mungkin ketika intelektual organik mampu memposisikan diri sebagai pembebas (Sugiono, 2006:29).
Gramsci menyadari bahwa dalam mekanisme hegemonik, peran intelektual begitu penting dan sentral karena mereka dapat disebut sebagai kelas yang memimpin dengan gaya persuasi yang tinggi. Intelektual oraganik ini kemudian membawa masyarakat sipil keluar dari ketertindasan.
Oleh karena itu, intelektual organik mesti mengembangkan jalan keluar yang produktif secara sosial-politik. Mereka harus mampu menggairahkan pembicaraan-pembicaraan penting yang mendalam mengenai persoalan-persoalan dengan merangsang pengembangan pandangan dan perhatian yang asli. Ia berperang sebagai pembawa kebenaran (truth-teller).
Michel Foucault juga menegaskan suatu peran penting intelektual dan derap kehidupan politik bangsa. Kehadiran mereka mesti mengarah pada suatu kebenaran hidup. Mereka diusahakan untuk mengungkapkan sesuatu secara realistis.
Foucault menegaskan: “Tugas intelektual khusus ialah mencoba mengisolasikan (dalam kuasa tekanan tapi juga dalam kontingensi dari formasi-formasi historis) sistem-sistem berpikir yang kini sudah menjadi biasa bagi kita yang tampak jelas bagi kita dan yang sudah menjadi bagian dari persepsi, sikap dan tingkah laku kita” (Bdk. Kebung, 1997;11-12)
Oleh karena itu, ada tiga fungsi intelektual dalam kekuasaan. Pertama, seorang intelektual organik seharusnya hidup dalam lingkup sosial tertentu dengan segala ciri dan kualifikasinya.
Kedua, seorang intelektual memiliki kebebasan dalam akal dan batinya. Kebebasan itu harus memberdayakan yang lain.
Ketiga, intelektual harus menyatakan kebenaran dalam tingkah laku dan hidup.
Intelektual organik mesti mampu independen dan otonom untuk menyatakan kebenaran. Sisi lain, mereka harus mampu mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat sipil sebagai bentuk penyadaran (konsientisasi ala Paulo Freire).