Oleh: Pius Rengka*
Perihal Golput kembali jadi ramai dibahas tatkala usai tulisan Prof. Frans Magnis Suseno disiarkan di harian Kompas pekan lalu.
Tulisan itu menjadi sangat heboh lantaran lewat tulisan itu Prof. Magnis menuding bahwa orang-orang yang memilih untuk tidak memilih (Golput) pada Pilpres kali ini (17 April 2019) tidak lain dari orang-orang bodoh, sakit jiwa dan parasit. Tudingan itu, tentu saja, membangkitkan gelombang protes, terutama dari kalangan aktivis dan cendekiawan.

Protes mereka berdasar dan cukup mendasar. Menurut kaum protes ini, sikap memilih untuk tidak memilih, bukan karena mereka bodoh atau benalu atau sakit jiwa sebagaimana dituding Magnis, tetapi sikap memilih untuk tidak memilih itu justru dilakukan setelah dilakukan evaluasi sangat kritis atas realitas pasangan Capres yang tersedia oleh sistem politik Pilpres kali ini.
Sikap memilih untuk tidak memilih itu sebagai wujud dari protes politik mereka akan sistem politik Indonesia hari ini yang tidak memberi peluang sangat luas kepada rakyat Indonesia untuk menimbang sejumlah alternatif pilihan.
Sistem politik Indonesia (terutama kasus Pilpres) seolah-olah memaksa rakyat untuk hanya memilih satu dari dua pilihan. Padahal, jika sistem politik Indonesia memberi peluang bagi terbukanya calon lebih dari dua pasangan, maka rakyat akan leluasa menentukan aneka pertimbangan dan memperhitungkan persaingan demokratik yang lebih luas.
Sesungguhnya, sejak awal perihal syarat calon presiden disoalkan banyak kalangan di luar parlemen. Sedangkan di kalangan dalam parlemen sendiri, Partai Demokrat telah memotori dan mengakomodasi pikiran kalangan luar parlemen.
Demokrat pun telah meramalkan hal buruk akan terjadi kemudian hari jika bersikukuh dengan syarat yang disetujui.
Partai Demokrat kala itu berpendapat, tidak ada syarat lain dari pencalonan presiden kecuali setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon, baik calon presiden hasil kompromi gabungan partai politik maupun masing-masing partai mengajukan calonnya sendiri.
Partai Demokrat mendukung pikiran bahwa perihal calon presiden dan wakil presiden itu adalah salah satu fungsi partai politik yang merepresentasi kepentingan obyektif politik rakyat.
Partai Demokrat berpikir, demokrasi di Indonesia dikerjakan dalam setting sosial politik yang multidimensional, fragmented. Atau sistem politik Indonesia patut memantulkan realitas kandungan sosialnya atau kandungan materialnya. Arend Lijphart (1977) menyebutnya sebagai democracy in plural societies.
Partai pendukung pikiran Partai Demokrat kala itu, kalah tarung dalam voting. Sayangnya pikiran mayoritas partai di parlemen malah dibenarkan Mahkamah Konstitusi, ketika MK menolak gugatan Partai Demokrat untuk membatalkan keputusan parlemen.
Akibatnya, jumlah calon presiden sangat terbatas karena dibatasi syarat yang disepakati mayoritas partai politik di parlemen. Seandainya tuntutan Partai Demokrat dan para pendukungnya yang lain itu diterima, maka hari ini kemungkinan besar calon presiden dan wakil presiden tidak hanya ada dua pasangan calon, tetapi lebih.
Diskusi Kompas TV
Selang beberapa hari kemudian, pada acara Rossy di Kompas TV, diundang sejumlah narasumber antara lain, Wimar Witoelar dan Haris Azar. Sengaja cukup dua nama ini disebut dalam tulisan ini, karena dua tokoh ini cukup mewakili dua arus pemikiran berbeda paska tulisan Romo Magnis.
Haris Azar, dikenal luas sebagai aktivis pejuang gigih hak-hak asasi manusia. Ia juga menuntut agar negara (cq. Pemerintah) segera melacak dan menemukan para pelaku kejahatan penghilangan orang terutama dalam kasus Munir.
Haris terus bersuara agar para pelaku kejahatan kemanusiaan itu diseret ke pengadilan HAM dan dijebloskan ke dalam jeruji penjara.
Tuntutan Haris Azar itu sudah berlangsung sangat lama sejak pemerintahan SBY 10 tahun hingga pemerintahan Jokowi. Tetapi hingga hari ini, kita semua sama tahu, tuntutan Haris dan kawan-kawannya itu terkesan tidak digubris.
Haris Azar juga sangat kencang menuding dan menuntut mantan Danjen Kopasus Jenderal Prabowo yang dipecat dari satuannya dan diduga kuat terlibat sangat jauh dalam kasus penghilangan orang dan kasus Trisakti.

Prabowo selalu disebutnya sebagai bagian sangat penting dalam kasus penghilangan orang terutama para aktivis pada masa silam. Prabowo harus dimintai pertanggungjawabannya.
Haris Azar pun berulang kali meminta Jokowi, untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia yang diduga ikut terlibat beberapa oknum militer, termasuk di antaranya mantan militer di kalangan dalam kabinet Jokowi.
Tetapi hingga hari ini, permintaan, tuntutan dan seruan berulang kali Haris Azar dan kawan-kawan itu, tampaknya tak digubris hingga proses pemilu penentuan politik mesti dikerjakan hari ini.
Dalam diskusi panel yang dipandu Rossy Silalahi di Kompas TV pekan lalu, Haris Azar berpendapat, sikap politik seseorang pemilih untuk tidak memilih justru membela kepentingan opini publik atas ketidaksetujuannya terhadap dua calon presiden yang tersedia.
Pilihan untuk tidak memilih dua calon sebagai satu bentuk koreksi atas opini politik parlemen yang tidak sensitif dengan realitas masyarakat plural.
Karena itu Golput sama sekali tidak buruk. Malah, Golput itu adalah satu jenis gerakan politik rakyat untuk mengingatkan elite politik atas kesemberonoan dan kesewenangan politik selama ini. Dia mengoreksi sikap parlemen yang tidak sensistif pada konflik politik dan bahkan tidak sensitif terhadap pemilik kedaulatan rakyat itu sendiri.
Sedangkan Wimar Witoelar, adalah seorang intelektual prodemokrasi. Ia selalu menawarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk membuka ruang diskursus seluas-luasnya agar memberi makna substantif pada demokrasi.
Baginya, demokrasi dari hari ke hari harus lebih bermakna agar rakyat Indonesia lekas keluar dari penderitaannya. Dia selalu kritik rezim despotik Orde Baru. Dia menawarkan rezim demokratik yang berbasis pada pluralisme di Indonesia ini.
Pada masa Pemerintahan Gus Dur, Wimar Witoelar terbilang orang lingkaran dalam yang berdiri satu front dengan pendirian Kiayi Agung yang sangat humanis itu. Bahkan dalam berbagai artikelnya, Wimar Witoelar selalu membela pentingnya perdamaian. Ia salah satu intelektual yang kritis dan terkemuka.
Wimar Witoelar berpendapat, sebaiknya rakyat memilih satu dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tersedia, meski mungkin dua pasangan calon presiden ini dianggap buruk.
Menurut Witoelar, meski dua calon itu buruk, tetapi toh tentu masih ada di antaranya yang peringkat buruknya jauh lebih kurang dibanding yang lain. Maka pilihlah calon presiden yang tingkat keburukannya kurang itu.
Sikap memilih calon presiden dari dua calon yang tersedia merupakan kehendak sistem politik. Kita jalani dengan sikap yang biasa saja, kata Wimar sambil menambahkan, tetapi tidak boleh menghilangkan kesempatan untuk ikut mengendalikan negara dengan cara terlibat dalam pemilihan dari pilihan yang tersedia oleh sistem politik yang ada.
Karena itu, memilih satu di antaranya adalah keniscayaan politik. Memilih satu dari dua calon presiden adalah tanggung jawab politik rakyat karena rakyat selalu menyimpan seketul harapan agar setelah memilih ada sedikit perubahan berarti.
Mengapa Golput?
Tampaknya, dua argumen dari dua kubu berbeda sama kuat dan mendasar. Tetapi pertanyaan yang menarik tentulah ini. Mengapa rakyat memilih si A misalnya, dan bukan memilih si B, atau tidak memilih keduanya (A dan B)?
Tindakan memilih dalam politik, tentu saja terkait pula dengan motif tiap orang melakukan pemilihan. Karena motif itu menggerakkan sikap pribadi atau sikap politiknya.
Misalnya, Badu memilih si A dan bukan si B karena Badu mengidentifikasikan dirinya dengan si A, sedangkan si B sangat jauh dari identifikasi diri Badu pribadi. Tetapi sangat besar kemungkinan Badu tidak memilih A atau B karena tak ada identifikasi dirinya dengan kedua calon tersebut.
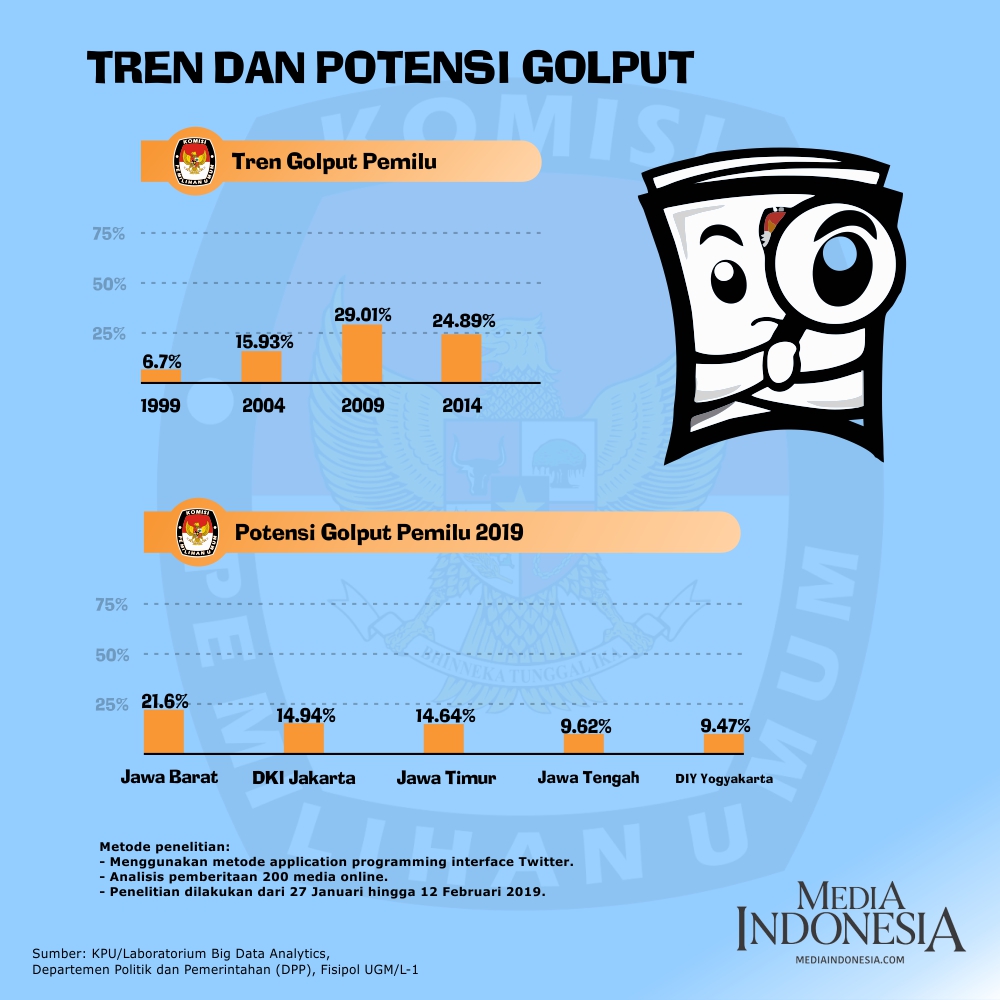
Anthony Downs, misalnya, berpendapat sikap memilih calon ditentukan oleh nilai yang diharapkan pemilih. Pemilih memilih orang atau partai politik karena disadarinya bahwa orang atau partai politik yang dipilihnya sanggup merepresentasikan kepentingan pemilih atau sanggup memecajkan masalah para pemilih.
Memilih untuk tidak memilih A atau B sebagaimana contoh si Badu di atas lalu dituding sebagai Golput. Seseorang memilih untuk tidak memilih (Golput) mengandung dua kemungkinan mendasar.
Pertama, opsi negatif, ketika seseorang merasa tidak mempunyai alasan cukup untuk turut memilih (vide: Ignas Kleden, Partai Politik dan Politik Partai dalam Pergulatan Partai Politik di Indonesia; 2004).
Kedua, opsi positif, ketika seseorang merasa mempunyai alasan cukup untuk tidak turut memilih (Ibid).
Menurut Ignas Kleden (Ibid), opsi manapun yang menjadi dasar pertimbangan, pilihan untuk tidak memilih tidaklah menguntungkan dilihat dari perlunya perubahan politik.
Dengan tidak turut memilih dalam pemilu, seseorang sudah mengabaikan kesempatan (melalui pemberian suaranya) untuk menciptakan perubahan politik, khususnya menciptakan sirkulasi elite, melalui rekruitmen elite politik baru dalam pemilu.
Tentu saja, demikian Ignas Kleden, masih ada keraguan apakah suara yang diberikan dalam pemilu sanggup menciptakan perubahan politik, mengingat calon yang ada barangkali tidak cukup memenuhi harapan.
Peluang untuk perubahan dan pembaharuan politik bisa besar atau kecil, tetapi kesempatan untuk melakukannya adalah sesuatu yang layak untuk dicoba dimanfaatkan.
Sebab dalam akibatnya (meskipun bukan dalam niatnya), tidak memilih berarti memilih untuk tidak mengadakan perubahan apa pun dalam politik Indonesia.
Dengan pandangan terakhir ini, terlihat sangat jelas pentingnya partisipasi politik dalam pemilu (cq pilih presiden) yang merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi politik dalam demokrasi. Karena demokrasi juga menuntut besar dan luasnya partisipasi serta alasan paling minimal dari partisipasi politik itu.
Catatan akhir untuk tulisan ini, saya menyarankan untuk tetap memberi suara pada Pemilu nanti dengan harapan berikut ini.
Pertama, untuk pemilihan para wakil rakyat (DPR RI) perlu ikut diperhatikan hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga survei, mengingat tidak semua partai politik akan memenuhi syarat parliament threshold.
Demi tuntutan itu, saya kira tidak semua calon DPR RI memiliki kualifikasi handal sebagaimana dituntut oleh demokrasi yang kuat yaitu calon yang berintelektual tinggi dan berintegritas yang terandalkan.
Cara melihatnya, yaitu dengan mencari dan menemukan track recordnya. Kita tentu tidak sedang mencari orang-orang bodoh dan bermoral buruk duduk di DPR RI.
Kedua, memilih partai tengah atau kiri tengah atau kanan tengah mengingat opsi kita agar Indonesia masih menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Partai-partai tengah, atau kiri tengah atau kanan tengah, berorientasi pada berlakunya Pancasila sebagai Dasar Negara.
Sehingga partai-partai yang sekiranya berniat dan berminat menggantikan dasar negara sebaiknya dihindari tanpa harus disertai kebencian. Kita hanya menghindari peluang perubahan dasar negara ini.
Ketiga, untuk DPRD (kabupaten, kota dan propinsi), mencari dan memilih calon yang berukuran sama dengan calon DPR RI, yaitu berintelektual tinggi dan berintegritas yang handal. Tentu saja, jika saya menyebut intelektual tinggi tidak paralel dengan calon bergelar tinggi.
Keempat, untuk calon presiden dan wakil presiden, sebaiknya mempertimbangkan dengan sungguh apa yang dikemukan Prof. Anthony Downs di atas yaitu bahwa memilih calon presiden yang sekiranya sanggup memecahkan masalah yang dihadapi para pemilih. Sekian.
*Penulis adalah jurnalis senior, PU VoxNtt.com


