Oleh: Ican Pryatno*
Perbincangan mengenai golput kian mengemuka akhir-akhir ini. Aneka diskusi dan perdebatan tentangnya kerapkali berseweliran dalam ruang publik.
Faktum menunjukan, dalam perdebatan tersebut ada pihak yang memandang golput sebagai berkah, namun ada juga yang menilai golput sebagai malapetaka dalam demokrasi dengan beberapa pendasaran yang mumpuni.
Namun terlepas dari perdebatan tersebut, tulisan ini sesungguhnya tidak berpretensi untuk ‘menghakimi’ ataupun memberikan pembenaran atas gerakan golput.
Tulisan ini sesunggunya hanyalah sekadar sebuah refleksi atas keberadaan golput.
Golput dalam Bentangan Perbincangan
Secara historis, perbincangan mengenai golput erat kaitannya dengan situasi menjelang pemilihan umum pada tahun 1971. Pasalnya, ketika itu muncul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda (mahasiswa)yang salah satunya dimotori Arif Budiman dengan tujuan untuk memboikot gebyar kontestasi pemilihan kala itu.
Gerakan politik tersebut sesungguhnya merupakan sebuah bentuk protes dan kekesalan oleh karena penyelenggaraan konstetasi elektoral kala itu sangat tidak demokratis. Saat itu, sasaran perlawanan mereka ialah Soeharto beserta partainya yang sangat sentralistik.
Konon, pemilihan umum yang diselenggarakan saat itu sangat tidak demokratis. Pembatasan jumlah partai dan keberadaan partai Golkar dinilai sebagai taktik untuk melanggekan kekuasaan Soeharto.
Sehinggga jangan heran pelbagai tanggapan, kritikan, kekesalan, dan aksi protes yang didaulatkan saat itu dilatari oleh sebuah proses demokratisasi semu. Sesungguhnya aneka akrobat yang diwujudkan dalam pemilu saat itu tidak lain hanya bertujuan untuk melegitimasi Soeharto.
Lebih lanjut, menyitir Sri Yanuarti, setidaknya dalam kaitan dengan perkara golput yang terjadi semasa orde baru, ada tiga kebijakan pemerintah yang diyakini melatari pembiakan golput.
Pertama, kebijakan massa mengambang yaitu dengan membatasi kepengurusan partai politik di tingkat partai di tingkat kabupaten/kota.
Kedua, adanya kebijakan yang membatasi warga negara dalam mengekspresikan pendapat dan berorganisasi. Salah satu instrument yang digunakan oleh pemerintah kala itu ialah melalui kebijakan politik perizinan.
Konsekuensi logis dari hal ini, setiap kegiatan politik masyarakat apalagi yang berbau kritikan diperhambatan bahkan dihalangi. Hal ini dapat dinyatakan dalam aksi pencekalan kegiatan kesenian dari WS Rendra dan kawan-kawan.
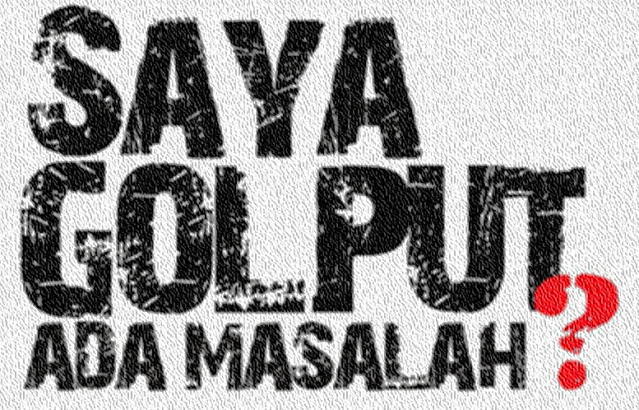
Ketiga, adanya kebijakan korporatisme negara dalam kemasyarakatan, kelompok kepentingan serta profesi. Untuk mengendalikan aktivitas mereka, pemerintah mewajibkan program-program dari organisasi tersebut untuk tidak bertentangan dengan program-program pemerintah (Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 6, No. 1, 2009).
Selain itu, menurut Prof. Miriam Budiardjo, salah satu alasan yang mendasari aksi mereka saat itu ialah karena kurang terjaminnya kebebasan (civil liberties) yang semestinya terakomodasi di dalam sebuah arena demokrasi. Adapun yang terjadi saat itu, rakyat sepenuhnya diarahkan dan diintimidasi hanya demi melegitimasi keberlangsungan rezim (Budiardjo, 2007: 479).
Sesudah kejatuhan rezim orde baru, gerakan golput terus saja berkelindan. Kenyataan ini diperkuat dengan sejumlah data yang dikeluarkan lembaga KPU bahwa sejak pemilu 2004 hingga 2014 jumlah golput cukup varatif dan cenderung meningkat.
Pada pemilu 2004 jumlah golput sebanyak 23,3 persen, pada pemilu 2009 jumlah golput sebanyak 27,45 persen, dan pada pemilu 2014 jumlah yang golput sebanyak 30,42 persen (Tempo, 3 April 2019).
Faktum menunjukan, gerakan golput yang terjadi paska reformasi demikian cukup beralasan. Pada pemilu 2004, misalnya, gerakan golput yang terjadi diyakini sebagai sebuah bentuk protes dan perlawanan sekaligus ekspresi kekesalan terhadap pemerintahan dan lembaga yang ada saat itu.
Gerakan golput yang terjadi dalam momentum kontestasi elektoral saat itu sesungguhnya adalah sikap bersama untuk meresistensi persoalan korupsi yang kian merangkak dan juga adanya perkara disfungsi lembaga DPR.
Selain itu, gerakan golput yang terjadi, juga merupakan sikap bersama guna ‘meredam’ intervensi masif pemerintah atas lembaga pengadilan. Adanya ketidakjelasan dalam penyelesaian sejumlah kasus kala itu disignalir karena adanya intervensi pemerintah kala itu. Maka sesunggunya gerakan golput yang terjadi saat itu berintensi guna meresistensi pembiakan korupsi dan untuk menegakan kembali kesejatian lembaga peradilan.
Merefleksikan Golput
Selain beberapa hal di atas, salah satu alasan pergerakan golput akhir-akhir ini ialah untuk meredam penetrasi kepentingan dari para elite dalam politik, yang dibahasakan Jeffry Winters sebagai Oligarki.
Sesungguhnya alasan demikian cukup mendasar, pasalnya dalam beberapa kali momentum kontestasi elektoral, keterlibatan beberapa figure sentral semakin mencolok.
Kehadiran mereka diyakini bertujuan untuk mengafirmasi kemenangan dari sang kandidat. Adapun yang dapat mereka lakukan ialah melalui afirmasi finansial, turut terlibat mengkapitalisasi sekaligus mempolitisasi media ataupun agama. Semuanya itu dimaksudkan demi memintal sebuah kemenangan dan tentu demi mempertahankan kekayaan.
Selain dari pada itu, menyitir Winters pergerakan para oligarki di dalam politik juga nyata dalam sejumlah usaha membeli partai-partai politik atau membeli jalur untuk memperoleh posisi-posisi berpengaruh dalam politik kepartaian.
Hal ini dilakukan dengan membayar sejumlah uang kepada anggota-anggota partai pada tingkat lokal dan regional untuk mendukung yang bersangkutan menjadi pemegang kendali partai dan dalam banyak kasus menggunakan kekuatan uang mereka untuk mendirikan partai.
Gagasan ini yang dinyatakan ini menurut Winters bertujuan untuk menjadikan diri mereka sebagai ketua partai sehingga dapat dilentingkan ke kontestasi kepresidenan (Winters, dalam Priyono, 2014: 219).
Guna mengokohkan kepentingan dan keberlangsungan rezimnya, para oligarki cukup sering terlibat dalam kontrol media. Melalui usaha demikian, kalangan oligarki berusaha membangun logika publik dengan menyatakan demokrasi sesungguhnya bebas dari interese para elite, tetapi nyatanya mereka ingin membangun sensasi dan pencitraan atas diri beserta mereka yang berada dalam frame kepentingannya.
Karena itu, disinyalir hal yang sama turut dilakukan dalam kontestasi mendatang tatkala adanya pencitraan atas calon yang dibuat oleh melalui media-media yang sudah tunduk di bawah logika kepentingan oligarki.
Selain dari pada itu, hal lain yang dibuat oleh para oligarki untuk mengokohkan kepentingannya ialah melalui sejumlah kebijakan yang dapat mengakomodasi pergerakannya. Misalnya melalui penentuan presidential threshold 20 % yang justru membuka ruang lobbying yang besar dan memantapkan kepentingan di tingkat elit politik.
Jika menggeledah kembali pergerakan golput sejak 1971 hingga medio mutakhir ini, dapat dimaklumkan bahwa golput sudah menjadi perkara yang sudah mengurat akar dalam demokrasi.

Karena itu, tanpa memberikan vonis ataupun pembenaran atas ‘perkara’ golput, hemat penulis, sesungguhnya yang mesti dikemukan ialah bagaimana negara mesti merefleksikan keberadaan golput yang sudah lama bertengger dalam demokrasi.
Pertama, pemerintah semestinya memaknai dan mereflesikan keberadaan golput sebagai sebuah sikap yang menunjukan ekspresi kekecewaan atas sejumlah persoalan yang sudah lama menjalar dalam lintas demokrasi bangsa.
Dalam konteks mutakhir, perkara golput mestinya dijadikan titik total refleksi penguasa agar mengedepankan kesejatinya sebagai abdi rakyat, yang berjuang demi kepentingan rakyat, dan bukannya menjadi pengabdi dari para oligarki.
Kedua, gerakan golput yang terjadi mestinya menjadi bahan introspeksi diri para elite yang sudah lama berwajah oligarki. Adanya perkara golput semestinya menjadi bahan evaluasi diri dari para oligarki agar mulai menata kesejatiannya sebagai agen yang mendukung kemasahalatan bersama.
Gerakan golput yang sudah lama membentang mestinya dilihat sebagai titik tolak dari para oligarki agar mulai menobatkan diri dan sepenuhnya menjadikan diri untuk selalu berkiblat pada kepentingan rakyat dan sekaligus menjadi agen pengadaban demokrasi
*Penulis adalah Anggota Centro-John Paul II Ritapiret, Maumere


