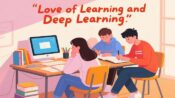Oleh: Sirilus Aristo Mbombo
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas
Katolik Widya Mandira Kupang
Demokrasi seperti matahari dalam politik, adalah sumber cahaya bagi kehidupan bernegara.
Namun, di Indonesia cahaya itu kadang tertutup kabut, menyisakan keremangan yang menggugah tanya: sudahkah rakyat sungguh menjadi tuan dalam rumahnya sendiri? Ataukah demokrasi tinggal nama yang kehilangan makna?
Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Maka secara etimologis, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.
Sebuah gagasan luhur yang menjanjikan keterlibatan setiap warga dalam pengambilan keputusan politik, dan dalam idealnya, menjadi wahana keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Namun sebagaimana bunga yang indah pun rentan layu oleh cuaca yang salah, demokrasi dapat rusak bila tidak dirawat dengan jiwa yang jujur dan nalar yang merdeka.
Di jantung demokrasi terdapat Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut, karena keberadaannya sebagai manusia.
Deklarasi Universal HAM (1948) menegaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak.
Maka tidak ada demokrasi sejati tanpa perlindungan terhadap HAM. Di Indonesia, konstitusi telah menjamin HAM, namun kenyataan di lapangan masih menyisakan banyak luka dan ketimpangan.
Salah satu permasalahan mendasar dalam penerapan demokrasi Indonesia adalah politik uang.
Dalam sistem pemilu yang seharusnya menjadi perayaan rasionalitas dan partisipasi warga, justru marak praktik transaksional yang menodai proses demokratis.
Jean-Jacques Rousseau pernah menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah kekuatan yang tak boleh dibeli.
Namun, dalam praktiknya, suara rakyat kadang ditukar dengan selembar uang, menciptakan demokrasi yang cacat sejak dalam rahimnya.
Ketika pemimpin lahir bukan dari kualitas, melainkan dari kekuatan modal, maka yang terjadi bukan pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tetapi oleh elite, untuk elite, dengan rakyat sebagai alat legitimasi semata.
Masalah lain yang menyertai demokrasi Indonesia adalah terbatasnya kebebasan sipil.
Dalam pandangan filsuf liberal seperti John Stuart Mill, kebebasan individu adalah syarat mutlak bagi kemajuan masyarakat.
Mill menyatakan bahwa “satu-satunya alasan yang sah bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan individu adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain.”
Namun di Indonesia, ekspresi kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman. Aktivis ditangkap, demonstrasi dibungkam, dan media dibungkam secara halus melalui tekanan ekonomi atau politik.
Demokrasi tidak dapat hidup dalam iklim ketakutan; ia hanya tumbuh dalam udara bebas yang mengizinkan setiap lidah mengungkapkan isi pikirannya tanpa teror.
Permasalahan lainnya adalah kebijakan publik yang sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
Dalam filsafat politik Hannah Arendt, politik seharusnya menjadi ruang untuk tindakan kolektif dan kebersamaan, bukan sekadar administrasi kekuasaan.
Namun kenyataannya, kebijakan sering lahir dari meja elite, tanpa konsultasi yang berarti kepada masyarakat yang terdampak.
Ketika suara rakyat tidak menjadi dasar keputusan, maka demokrasi berubah menjadi oligarki tersembunyi di mana segelintir memutuskan untuk yang banyak, bukan berdasarkan keadilan, tetapi atas dasar kepentingan kelompok.
Namun demikian, harapan tidak boleh padam. Demokrasi adalah proses, bukan produk jadi. Maka selalu ada ruang untuk pembenahan.
Prospek perbaikan demokrasi Indonesia dapat digerakkan dengan landasan filsafat politik yang mengakar pada etika, kebebasan, dan keadilan.
Immanuel Kant, dalam filsafat moralnya, mengajarkan tentang imperatif kategoris: bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat.
Prinsip ini seharusnya menjiwai para penguasa dalam menyusun kebijakan rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan subjek yang harus dihargai dalam otonomi moral dan martabatnya.
Perbaikan demokrasi Indonesia hanya dapat terwujud jika kebebasan rakyat dijamin secara nyata oleh negara.
Kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah fondasi partisipasi sipil.
Negara harus menjadi pelindung, bukan penghalang. Aparat keamanan bukanlah alat represi, tetapi garda pelindung kebebasan warga negara.
Ketika kebebasan ini dihormati, maka rakyat akan merasa memiliki tanggung jawab untuk merawat kehidupan bersama, bukan sekadar menuntut hak tanpa mengemban kewajiban.
Begitu pula, kebebasan berkeyakinan merupakan unsur yang esensial dalam demokrasi.
Indonesia, dengan pluralitas agama dan kepercayaan, harus menjamin bahwa tidak ada warga yang dikucilkan karena keyakinannya.
Demokrasi yang sehat tidak memaksa homogenitas, tetapi merayakan perbedaan sebagai kekayaan bersama.
Filsuf seperti Charles Taylor menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya dan spiritual sebagai bagian dari martabat manusia. Maka negara wajib menjadi ruang aman bagi semua, bukan hanya bagi mayoritas.
Kebebasan pers juga menjadi tiang demokrasi yang harus dijaga. Pers adalah mata dan telinga rakyat, penjaga nalar publik dari manipulasi.
Tanpa pers yang bebas, demokrasi terjerumus dalam kebutaan dan ketulian. Pemerintah yang bijak bukan yang membungkam kritik, tetapi yang bersedia dikritik demi kebaikan bersama.
Maka perlu diciptakan iklim hukum yang melindungi jurnalis dan mendorong lahirnya media yang independen dan bermutu.
Kesetaraan gender adalah dimensi lain dari demokrasi yang kerap diabaikan. Demokrasi tidak akan utuh bila separuh dari warga yakni perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap ruang publik, politik, dan ekonomi.
Simone de Beauvoir mengkritik bagaimana perempuan sering dikonstruksikan sebagai “yang lain” dalam sejarah patriarkal.
Maka demokrasi harus berani menghapus diskriminasi dan membuka jalan bagi keterlibatan aktif perempuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa.
Perempuan bukan hanya penerima kebijakan, tetapi pencipta arah kebijakan.
Akses masyarakat terhadap informasi publik juga menjadi syarat utama demokrasi yang sehat.
Dalam filsafat politik Jurgen Habermas, ruang publik yang rasional dan inklusif hanya bisa terjadi jika informasi bersifat transparan dan dapat diakses oleh warga.
Ketertutupan birokrasi dan manipulasi data hanyalah cermin dari ketakutan kekuasaan terhadap kontrol rakyat.
Maka perlu reformasi menyeluruh dalam sistem informasi negara agar rakyat tidak menjadi buta dalam menentukan nasibnya sendiri.
Kinerja lembaga legislatif dan pelaksanaan pemilu juga patut menjadi perhatian serius. Lembaga legislatif adalah representasi rakyat.
Namun ketika mereka lebih sibuk dengan kompromi politik daripada menyuarakan kepentingan konstituen, maka terjadi pengkhianatan terhadap mandat demokrasi.
Para legislator harus sadar bahwa jabatan mereka bukan privilese, melainkan amanah. Mereka adalah pelayan rakyat, bukan raja kecil.
Begitu pula pemilu, sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bebas dari manipulasi.
Pemilu yang bermartabat hanya mungkin terjadi jika disertai pendidikan politik yang memampukan rakyat memilih secara rasional, bukan emosional atau transaksional.
Terakhir, pengakuan terhadap hak-hak minoritas adalah ujian utama demokrasi.
Filsuf John Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai fairness: struktur sosial harus diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan.
Demokrasi bukanlah pemerintahan oleh mayoritas semata, melainkan perlindungan atas semua, termasuk yang lemah dan kecil.
Maka negara harus aktif melindungi kelompok minoritas, bukan membiarkan mereka terpinggirkan dalam sunyi.
Penutup dari seluruh uraian ini dapat disarikan dalam satu pandangan bijak: demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan medan tempur moral yang terus berlangsung antara kekuasaan dan kebajikan.
Seperti yang dikatakan Plato, “satu-satunya alasan untuk memilih pemimpin adalah karena ia mencintai kebenaran lebih dari kekuasaan.”
Maka demokrasi yang sejati hanya mungkin tumbuh bila rakyat dan pemimpin sama-sama mencintai kebenaran dan keadilan lebih dari kekuasaan dan keuntungan pribadi.
Sebagaimana refleksi mendalam dari Cornel West yang mengatakan bahwa “demokrasi adalah bentuk cinta publik terhadap rakyat jelata,” dan pandangan Martha Nussbaum bahwa demokrasi hanya akan bertahan jika warga dididik untuk berpikir kritis, berempati, dan memiliki kasih terhadap sesama, maka Indonesia membutuhkan demokrasi yang bukan hanya prosedural tetapi substantif, demokrasi yang bersumber dari hati nurani, disirami oleh pendidikan, dijaga oleh hukum, dan dijalani dengan keberanian moral untuk mencintai sesama warga sebagai sesama manusia.
Dengan demikian, perbaikan demokrasi Indonesia bukan sekadar persoalan teknis atau kebijakan administratif.
Ia adalah panggilan jiwa, pertaruhan etika, dan proyek moral yang harus dijalani bersama.
Dalam sunyi sejarah, semoga demokrasi Indonesia tumbuh bukan hanya sebagai sistem tetapi sebagai semangat, semangat untuk hidup bersama dalam kebebasan, keadilan, dan kasih yang mengangkat seluruh insan menuju martabat yang layak bagi manusia.