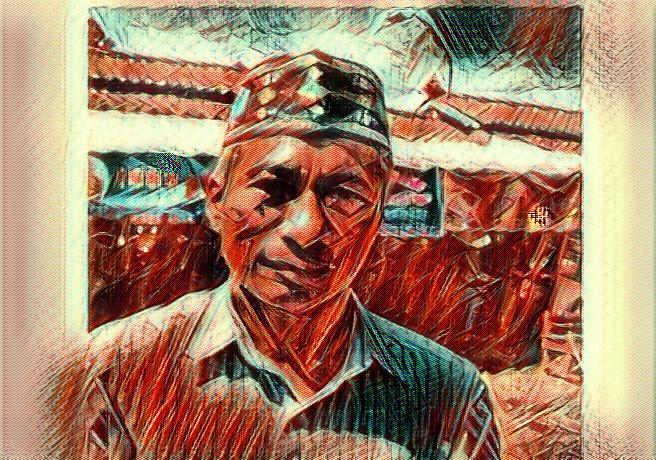Oleh: Ben Senang Galus
Penulis buku: Demokrasi Bumi dan Air, tinggal di Yogyakarta
Kemiskinan yang melekat pada masyarakat NTT, bahkan membuat ribuan orang rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan keselamatan hidup (lihat James C. Scott, 1981), menyebabkan menguatnya arus urbanisasi ke kota, ribuan orang menjadi tenaga kerja di luar negeri terutama ke Malaysia.
Masalah TKI, bukan persoalan tunggal yang ada pada keluarga TKI, melainkan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) sudah keluar dari misi sejatinya yakni tidak memberi perlindungan dan jaminan kepastian hidup terhadap warganya. Elit politik lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri.
Pemerintah daerah termasuk gereja dalam penziarahannya belum mampu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi oleh orang NTT, sehingga tidak heran orang kristiani yang miskin pun mudah dijumpai di NTT.
Kemiskinan di NTT dapat didekati melalui berbagai pendekatan.
Pertama adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini menilai bahwa rendahnya askses masyarakat terhadap kebijakan publik lebih banyak terjadi karena adanya “diskriminasi” pelayanan birokrasi. Pemda lebih berpihak kepada pemodal.
Kemunculan kelas kaya di NTT, lebih banyak dibentuk oleh hubungan yang terjalin erat antar kapitalis lokal dengan penguasa. Pendekatan struktural juga menilai bahwa penyebab stigma tadi adalah birokrasi yang lebih banyak bekerja untuk memperoleh keuntungan sendiri dengan membudayakan sikap hidup priyayi.
Kedua adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural menilai bahwa faktor penyebab kemiskinan di NTT adalah budaya masyarakat NTT yang cendrung malas, menjunjung tinggi sikap hidup boros dan foya-foya.
Sikap malas dan boros ini nampak dalam berbagai bentuk seperti adanya masyarakat yang lebih suka bermain judi, berpesta dibandingkan dengan kerja di kebun, dan adanya budaya belis dalam perkawinan, dan gereja juga tidak pernah melakukan inisiasi.
Ketiga, adalah pendekatan program dan kebijakan Pemda. Diakui bahwa sejak berdirinya Provinsi NTT 1958 sampai saat ini program pemda belum menyentuh masyarakat basis.
Kecendrungan program yang mucul adalah bersifat ke dalam dan elitis. Sehingga program itu banyak menilai berhasil ke dalam tapi gagal ke luar. Sebut saja di antaranya adalah program pembangunan fisik (infrastruktur) lebih diutamakan dari pada pembangnan sosial dan ekonomi.
Pemda lebih banyak menuntut kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembanguan demi alasan ”keluarga mandiri”, namun yang terjadi justru tidak memperhatikan kualitas hidup rakyat. Lalu kita bertanya di mana tanggungjawab pemda?
Semua program-program tersebut, di samping salah sasaran, juga tidak berhasil karena banyak uangnya yang disunat oleh aparat birokrasi, keterlibatan rakyat yang terbatas dalam memonitor dan target rakyat sasarannya tidak jelas.
Keempat, pendekatan tata kelola pemda (Manajemen Pemda). Ada rakyat menilai bahwa rendahnya kualitas hidup rakyat NTT lebih banyak disebabkan oleh tata kelola pemda yang buruk.
Buruknya tata kelola pemda NTT, dapat dilihat dari partisipasi rakyat yang rendah dalam pembangunan, respons pemda yang kurang terhadap kemiskinan, akuntabilitas program kemiskinan yang tidak berjalan, transparansi anggaran pemda yang tidak ada, sampai dengan imunitas atau kebalnya birokrasi pemda yang terlibat dalam ”penyalagunaan” anggaran pemda.
Kelima, kemiskinan di NTT juga dapat didekati dari teologi kemiskinan. Pendekatan ini menilai bahwa penyebab utama kemsikinan di NTT adalah gereja yang terlalu bersikap tertutup terhadap realitas kemiskinan.
Tidak adanya teologi kemiskinan yang diajarkan di Seminari Tinggi yang berbasis umat, menyebabkan banyak pelaku sosial di kalangan gereja yang bertindak tidak pro terhadap orang miskin di NTT dan bahkan mereka cendrung melegalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merepresi orang NTT yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Keenam, fenomena kemiskinan di NTT dapat juga didekati melalui sosiologi masyarakat. Pendekatan sosiologis menilai bahwa pola interaksi antar masyarakat di NTT, cendrung bersifat komunal.
Interaksi yang bersifat komunal ini cendrung menyuburkan semangat ”kemiskinan” sebagai milik bersama masyarakat. Karenanya, kemunculan orang kaya dalam masyarakat, dipandang sebagai ancaman bagi komunitas masyarakat NTT itu sendiri.
Tentu saja, banyak sekali pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan realitas kehidupan rakyat NTT. Tetapi kata kunci yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah pekerja migran (TKI).
Pekerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional ( Edi Suharto, 2007).
Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.
Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Globalisasi ternyata juga mendorong perpindahan tenaga kerja antar negara. Dewasa ini, penduduk dunia bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi.
Di wilayah Asia saja pada tahun 2017, tenaga kerja asing (sesama Asia) yang mengisi sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut mencapai jutaan.
Menurut Elwin Tobing (2003), arus migrasi tenaga kerja ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan melonggarnya hambatan-hambatan resmi migrasi di negara-negara yang tergabung dalam World Trade Organisation (WTO). Melonjaknya arus migrasi ini pada hakekatnya merupakan resultante dari perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dan berkembang.
Pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju telah mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi di negara maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu.
Secara umum, permintaan akan tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya. Sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih “terpaksa” didatangkan dari negara berkembang. Pekerja dari negara-negara maju sendiri seringkali tidak tertarik dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka bergaji rendah.
Menurut hasil penelitian Edward Marshall White, dengan judul: The Problems of Migrant Worker and the Death Labor of Indonesian Origin East Nusa Tenggara Part One (2017), mengatakan “The majority of migrant workers from East Nusa Tenggara are economic difficulties, narrow employment and low wages, encouraging people to try their luck to developed countries despite lack of expertise, preparation, adequate documents. Most migrant workers from East Nusa Tenggara are generally driven by wages that are relatively higher than the wages received in the area of origin. However, some of the migrant workers are motivated by other reasons, due to parents’ encouragement”.
(Terjemahan bebas penulis: Sebagian besar pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur ialah kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah rendah, mendorong orang untuk mengadu nasib ke negara maju meskipun tanpa bekal keahlian, persiapan, dokumen yang memadai. Sebagian besar pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di daerah asal. Namun, sebagian dari pekerja migran ada yang termotivasi oleh alasan lain, karena dorongan orangtua”. (catatan: White, hanya memberikan kepada saya beberapa lembar hasil penelitiannya. Tulisan ini saya kutip dari penelitiannya atas izin White)
Faktor pendorong dan penarik di atas sebenarnya merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan.
Persoalan menjadi lain manakala tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal dan/atau tanpa keahlian serta persiapan yang diperlukan.
Dalam konteks ini, munculah dua macam migrasi, yaitu yang legal (resmi) dan yang ilegal (gelap). Status gelap inilah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan sosial-psikologis.
Masalah lain menurut White, dalam arus migrasi dari Nusa Tenggara Timur ini, terdapat fenomena lain yang disebut “ migration feminism,” yakni, bahwa “migration is increasingly dominated by girls and women. The collapse of the local economic system caused many girls and women to be exposed to global workplaces to make a living”.
(Terjemahan bebas penulis: migrasi semakin didominasi oleh anak gadis dan perempuan. Ambruknya sistem ekonomi lokal menyebabkan banyak anak-anak gadis dan perempuan yang diekspos ke tempat-tempat kerja global guna mencari penghidupan).
Menurut White, “This situation will intensify in East Nusa Tenggara, which has experienced an economic crisis, especially in East Flores, parts of Timor Island, as Sumba as well as areas that experience domestic conflict and disunity in families. In the context of NTT, this migration feminism occurs in the form of sending large-scale migrant workers to Hong Kong, Saudi Arabia, Malaysia and Singapore“.
(Terjemahan bebas penulis: situasi ini akan semakin menjadi-jadi di Nusa Tenggara Timur yang mengalami krisis ekonomi terutama di Flores Timur, sebagian pulau Timor, sebagai Sumba serta daerah-daerah yang mengalami konflik dalam rumah tangga dan perpecahan dalam keluarga. Dalam konteks NTT, feminisme migrasi ini terjadi dalam bentuk pengiriman TKW besar-besaran antara lain ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura). .
Ada bab yang paling menarik dari hasil penelitian White, di Bab di bawah judul: Box Off Migrant Workers East Nusa Tenggara (Peti Mati Pekerja Migran Nusa Tenggara Timur), mengatakan begini:
“Most Melanesian races, including East Nusa Tenggara, Alor, Solor, Pantar and Flores have strong body structures. Although the body of this race is classified as small and short but they can walk far with high speeds can reach 80km per day. They can go up and down the mountain by not wearing footwear even though the weather is hot. Their organs include strong and agile. They are close to nature. They concentrate on what is produced by nature. The Lama Holot tribe and the surrounding islands consume a lot of fish”.(
(Terjemahan bebas penulis: Sebagian besar ras Melanesia termasuk, Nusa Tenggara Timur, Alor, Solor, Pantar dan dan Flores mempunyai struktur tubuh yang kuat. Walaupun badan ras ini tergolong kecil dan pendek namun mereka bisa berjalan jauh dengan kecepatan tinggi bisa mencapai 80km per hari. Mereka bisa naik turun gunung dengan tidak memakai alas kaki walau pun cuaca panas. Organ-organ tubuh mereka termasuk kuat dan lincah. Mereka dekat dengan alam. Mereka berkonsum apa yang dihasilkan oleh alam. Suku Lama Holot dan pulau sekitarnya mengkonsum ikan sangat banyak).
Lebih lanjut White mengatakan : All the results of studies in the world say that the Melanesian race’s limbs must be very good. Their organs such as the eyes, teeth, ears, heart, lungs, kidneys, liver are best among other races in the world. The death of migrant workers from East Nusa Tenggara is not caused by a disease, but it is related to the trade in body tissue“. (Terjemahan bebas penulis: Semua hasil studi di dunia mengatakan bahwa anggota tubuh ras Melanesia pasti baik sekali. Organ-organ tubuh mereka seperti mata, gigi, telinga, jantung, paru-paru, ginjal, liver paling bagus di antara ras lain di dunia. Kematian pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur bukan karena disebabkan oleh penyakit, melainkan terkait dengan perdagangan jaringan anggota tubuh).
Menurut White : “The human body trade network not only involves the sending companies of migrant workers but also involves the recipient companies of migrant workers. Receiving country of migrant work as an agent. We are trapped in the framework of economic improvement. It’s actually a small thing. The bigger thing is organ trade. We see in East Nusa Tenggara that there are corpses that are sent to be sure that the first two things should not be opened, second. the condition must not be examined. And I found all of that in my research from 2004 to 2017. All the shipping costs of corpses, including the costs of hosting, were the responsibility of the company.
(Terjemahan bebas penulis: Jaringan perdagangan anggota tubuh manusia ini tidak saja hanya melibatkan perusahaan pengirim tenaga kerja migran akan tetapi juga melibatkan perusahaan penerima pekerja migran. Negara penerima pekerjaan migran sebagai agen. Kita tercjebak dalam kerangka perbaikan ekonomi. Sebenar itu hal kecil. Hal yang lebih besar adalah perdagangan organ tubuh. Kita lihat di Nusa Tenggara Timur kalau ada korban mayat yang dikiri pasti dua hal pertama peti mati tidak boleh dibuka, kedua. mayat tidak boleh diperiksa kondisinya. Dan Saya menemukan semua itu dalam peneltian saya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Semua biaya pengiriman jenasah termasuk biaya pengunurab menjadi tanggungjawa perusahaan).
Kebanyakan para pekerja migran ini tidak paham hak dan kewajibannya. Kenyataan yang mereka hadapi sangat berbeda dengan gambaran yang mereka peroleh dari PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Mereka memiliki dua “musuh” yakni majikan dan perusahaan pengerah tenaga kerja.
Penanganan pekerja migran internal selama ini lebih banyak menyentuh aspek hilir ketimbang hulu. Padahal, menyentuh persoalan di hilir saja seperti halnya kegiatan “menyapu sampah di halaman rumah”.
Sedangkan, membersihkan penyebab yang mengotori halaman tersebut tidak tersentuh. Dengan demikian, penanganan persoalan pekerja migran perlu dilakukan secara terpadu. Ekoturisme, pengembangan agroindustri, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, antara lain, dapat memperbaiki kemakmuran desa yang pada gilirannya membantu membatasi laju migrasi ke luar negeri.
Pemberian pelatihan bagi peningkatan produktivitas ekonomi kecil, bantuan permodalan, dan pemberdayaan masyarakat miskin kiranya masih tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas pekerja migran ini.
Selama ini, kedutaan besar Indonesia di negara-negara lain belum memiliki atase sosial. Oleh karena itu, penempatan atase sosial, terutama di negara-negara yang banyak menerima TKI, perlu dipertimbangkan. Atase sosial ini harus memiliki keahlian yang lengkap mengenai konseling, advokasi, pendampingan sosial, dan teknik-teknik resolusi konflik.
Di dalam negeri, pembekalan terhadap TKI tidak hanya menyangkut “cara-cara bekerja dengan baik” di negara tujuan. Namun, sebaiknya menyangkut pula coping strategies dalam menghadapi persoalan yang mungkin timbul di negara tujuan.
Pelatihan mengenai strategi penanganan masalah ini bisa menyangkut pengetahuan mengenai karakteristik politik dan sosial-budaya negara tujuan, serta cara-cara menghadapi burn-out (kebosanan kerja), stress, kesepian, maupun pengetahuan mengenai fungsi dan tugas kedutaan besar.
Harapannya, semoga Gubernur NTT terpilih memperbanyak pencitaan lapangan kerja, memberi pelatihan bagi kaum ibu dan anak muda dan jaringan kerjasama pasar produk pertanian.