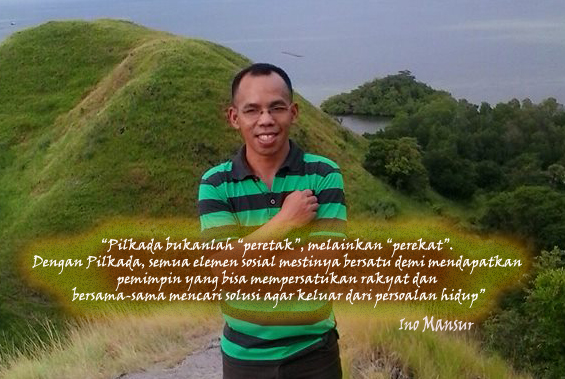Oleh: Inosentius Mansur *
Pilkada seringkali diidentikan dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Betapa tidak, dalam Pilkada setiap kandidat berusaha merebut simpati rakyat agar “diberikan” kekuasaan.
Hal inilah yang menyebabkan adanya kompetisi tidak sehat antara calon pemimpin. Akibatnya terjadilah “gesekan” antar elite dan polarisasi rakyat. Maka, Pilkada pun “rawan” melahirkan kondisi-kondisi distortif.
Hal tersebut menyebabkan keretakan sosial. Demi mendapatkan kekuasaan, kekeluargaan dikorbankan, persaudaraan dipinggirkan dan cinta kasih diabaikan.
Pilkada yang diharapkan memperkuat semangat persaudaraan, justru mendekonstruksinya demi pemenuhan hasrat pragmatik. Etika berdemokrasi yang sehat disingikirkan karena “para kontestan” Pilkada cenderung menggunakan cara berdemokrasi yang keji.
Tesis Nichollo Machiavelli dalam The Prince (1532) ada benarnya atau sekurang-kurang bisa menjelaskan hal ini. Hanya saja, jika maksud Machiavelli adalah untuk mempertahankan kekuasaan, cara-cara tak etis, keji dan dan tak bermoral dapat digunakan oleh penguasa; maka dalam Pilkada, untuk mendapatkan kekuasaan, cara tak etis dan nirdemokratis pun acapkali “dilegalkan”.
Persaingan yang seharusnya menjadi dinamika dalam Pilkada justru melahirkan persoalan sosial yang melebar.
Deklarasi Damai Vs Hasrat Berkuasa
Salah satu “tradisi” positif menjelang Pilkada adalah deklarasi damai. Esensinya adalah agar keharmonisan tidak retak. Pilkada harus menjadi momentum perang ide, perang logika, argumentasi dan bukannya perang fisik, perang teror (Arendt,1979) yang melahirkan perpecahan.
Pilkada mesti mengedapankan persaingan yang sehat dan mengutamakan cara-cara beradab. Martabat Pilkada justru semakin nampak, saat setiap orang yang berkepentingan tidak mendegradasinya menjadi hal-hal artifisial semata.
Namun, ini bukanlah hal gampang. Mengapa? Karena Pilkada seringkali melahirkan keresahan publik. Rakyat terfragmentasi dalam politik kubu-kubuan. Segmentasi seperti itu menyebabkan lahirnya dikotomi ekstrem.
Elite politik yang diharapkan menjadi promotor keharmonisan, seringkali menjadi “dalang” terciptanya Pilkada “anarkis”. Maka terjadilah persaingan tidak rasional.
Hasrat untuk berkuasa, sebagaimana kata Nietzsche (1883) tidak diterjemahkan berdasarkan nalar demokrasi, melainkan berdasarkan nalar pragmatis. Orientasinya adalah kekuasaan semata. Demi mendapatkan kekuasaan, demokrasi “dikriminalisasi”.
Omnes Vos Fraters Estis
Ungkapan ini diambil dari Injil Matius 23:8 yang artinya “kamu semua adalah saudara”. Kendatipun konteks pernyataan Yesus dalam teks tersebut adalah kecaman terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi saya “mengambilnya” untuk dikaitkan dengan situasi Pilkada kita.
Pilkada bukanlah “peretak”, melainkan “perekat”. Dengan Pilkada, semua elemen sosial mestinya bersatu demi mendapatkan pemimpin yang bisa mempersatukan rakyat dan bersama-sama mencari solusi agar keluar dari persoalan hidup.
Pilkada memiliki dimensi persatuan karena semua orang yang berbeda suku, agama, ras ataupun asal bersatu padu untuk memilih pemimpin. Pejabat, elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun rakyat biasa memiliki hak yang sama. Tujuan mereka sama yaitu mencari pemimpin artikulatif.
Keterlibatam mereka dalam politik bukan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi bersifat meta-pragmatik. Benarlah Emha Ainun Nadjid, bahwa politik merupakan seni mendapatkan kekuasaan.
Baginya, seni dalam konteks politik mengacu pada etika, logika, dan estetika. Etika mengacu pada keluhuran moralitas, logika mengacu pada kebenaran yang absolut, dan estetika mengacu pada keelokan dan kepantasan (Bdk. Kompas,10/10/16).
Karena itu, Pilkada tidak boleh direduksi kedalam kepentingan subyektif. Pilkada mesti menjadi pijakan refleksi untuk menjaga persatuan. Untuk itu, semua elemen dan pemangku kepentingan mesti menyadari bahwa Pilkada merupakan momentum mencari pemimpin serentak pemersatu.
Keharmonisan, cinta kasih, persaudaraan harus menjadi karakter Pilkada dan melampuai hasrat pragmatis tertentu. Pilkada mesti memperkuat sendi-sendi demokrasi dan mempererat relasi sosial.
Di sinilah sinergisitas berbagai elemen diperlukan. Kaum intelektual, tokoh agama, tokoh politik, tokoh publik mesti menghindari tindakan serta ucapan yang berpotensi mencederai persatuan.
Mereka mesti bahu membahu untuk merawat kebhinekaan dalam konteks Pilkada dengan tetap menjaga keharmonisan. Mereka tidak boleh menjadi batu sandungan dalam demokrasi elektoral Pilkada lewat tindakan tak pantas serta ucapan apublik.
Selain itu, hasrat pragmatik tidak boleh membordir substansi Pilkada sehingga hancur berkeping-keping. Kiranya kata-kata Yesus: Omnes Vos Fratres Estis, menjadi pijakan bagi kita untuk bersama-sama mendukung Pilkada yang mendamaikan. Hasrat untuk berkuasa mesti dijabarkan secara etis berdasarkan nalar demokrasi.
Penulis adalah pemerhati sosial-politik dari Ritapiret