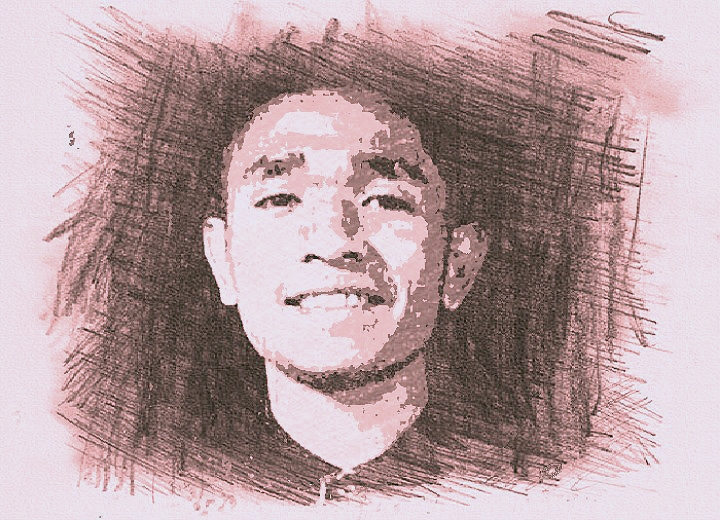Oleh: Rian Odel
Anggota KMK Ledalero
Gotong-royong antara pemerintah dan para pemodal (korporatokrasi) nyaris merobohkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang otoritas demokrasi.
Suara rakyat yang menjerit menuntut legalitas Hak-Hak Asasi dikebiri melalui konsep-konsep politis yang manipulatif. Demi idealisme untuk menjadi orang kaya, diduga pemerintah secara diam-diam berselingkuh dengan golongan kapitalis untuk merampas sistem kepemilikan masyarakat kecil yang masih berpegang kuat pada hukum adat.
Secara represif hukum-hukum adat diselewengkan melalui instrumen-instrumen kekuasaan yang diproduksi oleh pemerintah dan didukung oleh para kapitalis kelas wahid.
Akibanya, terjadi benturan besar antara masyarakat hukum adat dan pemerintah yang seenaknya menghadirkan proyek-proyek raksasa tanpa diskursus proporsional dan ada indikasi pencaplokan tanah serta manipulasi kompensasi.
Latar Belakang Kasus
Rivalitas ide–bahkan mengarah ke fisik–antara masyarakat hukum adat versus pemerintah atau kekuasaan yang diduga berjubah kapitalisme sering tejadi.
Pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan dianggap melecehkan warisan-warisan adat yang inheren dengan masyarakat melalui dalil pembangunan demi urgensitas bonum commune yang hadir misalnya melalui bisnis pertambangan maupun pariwisata.
Dalil misi pembangunan yang diproduksi pemerintah menemukan titik buntuh ketika berbenturan dengan hak aprimafacie (hak yang ada pranegara dan tidak bergantung padanya).
Namun, sebagai penguasa, seringkali pemerintah tetap menanggapi konflik semacam ini melalui intrumen-instrumen kekuasaan yang legal misalnya Undang-Undang pasal 33 Konstitusi 1945 atau bahkan memakai tangan militer untuk memuluskan cara kerjanya.
Sebaliknya, masyarakat adat yang minim modal kekuasaan terlihat kalah sebelum bertanding tatkala berhadapan dengan hegemoni represif kekuasaan para pemodal; maka jalan yang lumrah dicapai yaitu demonstrasi “brutal” atau membuat petisi tertulis (Alex Jebadu, 2018) jika dialog formal mubazir.
Ada dua alasan kontradiktif yang perlu dicari benang merah demi proses rekonsiliasi. Masyarakat adat merasa tidak dihormati bahkan dirugikan oleh pemerintah karena tuntutan hukum adat diabaikan; sebaliknya, pemerintah yang dimandatkan untuk menjawab kesejahteraan masyarakat selalu membentengi diri dengan teori pembangunan (theory of development); mengeksploitasi alam demi misi tersebut dianggap halal.
Kasus mutakhir terjadi benturan antara Pemerintah daerah Lembata versus masyarakat adat Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT yang getol mempertahankan tanah adat.
Tanah ini sudah sebagian diperkosa oleh pemerintah demi pariwisata, juga kasus kontroversial pembangunan tempat pariwisata di Pulau Siput, Lembata.
Langkah pemda Lembata ini mati-matian ditolak oleh masyarakat atas nama adat dan budaya karena tempat itu diyakini sebagai kuburan masal para leluhur sehinnga dianggap sakral.
Konsep metafisis semacam ini sangat kuat diyakini oleh masyarakat lokal khususnya di Flores sebagai sebuah kebenaran total sebab eksistensi alam dilihat sebagai personifikasi dari kehadiran Tuhan maha cinta dan dilindungi oleh roh-roh tak kelihatan (Ibid).
Artinya, sebuah konsep pembangunan yang menyentuh langsung dengan nilai-nilai hukum adat oleh pemerintah mesti secara transparan didahului dengan sebuah diskusi bersama agar aspirasi-aspirasi masyarakat bisa disampaikan sebagai suara pengontrol demi mencegah adanya kolonialisasi kekuasaan.
Namun, libido pemerintah untuk mengeksploitasi alam hampir tidak mampu dipatahkan oleh argumentasi tradisional masyarakat adat.
Fenomena ini sangat jelas membuka mata publik bahwa di hadapan kekuasaan yang hegemonik, militansi masyarakat kecil beradat selalu dirong-rong bahkan dibungkam secara terpaksa oleh instumen-instrumen kekuasaan yang menyetir hukum.
Kejadian kontradiktif tersebut jelas membuktikan bahwa selain motivasi murni pembangunan, pasti ada motivasi bisnis untuk mengeruk profit pribadi.
Tokoh yang mendukung langgengnya hak a prima facie yaitu John Locke. Dia menegaskan hak-hak alamiah–salah satunya tentang hak kepemilikan–yang hadir pranegara sedangkan konsep yang bertentangan bisa ditemukan pada teori utilitarianisme yang mementingkan aspek pragmatik.
Utilitarianisme didukung oleh Jeremy Bethan dan John Stuart Mill. Keduanya mengafirmasi bahwa Hak-Hak Asasi hadir ketika sebuah negara resmi dibentuk.
Artinya, hak-hak tersebut disusun oleh para pengatur negara. Namun, antara Jeremy Bethan dan Jhon S. Mill terdapat kontradiksi ide tentang utilitarianisme karena menurut Bethan, sebuah pembangunan harus menyentuh kepuasan individual–dia kurang serius berbicara tentang konsep keadilan sedangkan Jhon S. Mill lebih terbuka bahwa sebuah konsep pembangunan tidak mesti mengabaikan keadilan. Keduanya menilai Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia adalah sebuah kesalahan besar (Yosef Kladu, Manuskrip, 2019).
Jika eksistensi Hak-Hak Asasi manusia merujuk secara total pada konsep Utilitarianisme, menurut saya peluang penyelewengan hukum gampang terjadi dan merugikan masyarakat sipil karena hukum Hak-Hak Asasi manusia dibentuk sesuai keinginan pemerintah.
Oleh karena itu, dalam sebuah negara demokrasi, hukum adat yang lahir pranegara mesti diakui substansinya sebagai salah satu hukum legal yang mengayomi perjalanan hak hidup masyarakat kecil.
Hukum yang diatur oleh para petinggi negara tidak mesti mengabaikan nilai-nilai positif yang ada dalam hukum adat masyarakat tertentu tetapi harus ada upaya untuk melanggengkan hukum-hukum pranegara sejauh nilai-nilainya menopang kesejahteraan masyarakat kecil, misalnya penyesuaian dan pencarian titik temu antara hukum adat dan hukum positif.
Politik Pengakuan
Masyarakat lokal yang merasa tidak berdaya dalam perjuangan menghadapi masalah globalisasi pembangunan cenderung menjadikan kekerasan fisik sebagai jalan membela diri (Gusti Madung, 2009: 6).
Awasan tersebut menjadi rambu-rambu merah bahwa bahaya ketidakadilan bisa memicu revolusi berdarah, maka jalan tengah yang perlu dicapai yaitu kesadaran untuk mengakui “yang lain” versi filsafat wajah E. Levinas menjadi titik pijak primer (Felix Baghi, 2012).
Pengakuan tersebut akan menghasilkan sebuah komunikasi rasional (J. Habermas) untuk membangun sebuah perdamain bersama (pax) dalam suasana kesetaraan dan pluralitas (Gusti Madung, opcit., hlm. 7).
Pengakuan pertama mesti datang dari atas yang ditopang oleh ide keadilan dan kesadaran terhadap aspek tanggung jawab serta didorong oleh misi karitatif terhadap konteks dan konsep fundamental yang dimiliki oleh masyarakat lokal beradat.
Namun, perlu disadari bahwa sebuah pengakuan mengandaikan adanya pengetahuan dasar tentang kebenaran-kebenaran filsafat timur yang dimiliki oleh masyarakat lokal sehingga tidak menimpulkan kecurigaan.
Mereka mesti diakui keberadaannya sebagai sebuah kelompok masyarakat beradat yang memelihara nilai-nilai kebenaran, sebab melalui pengakuan, nilai kemanusiaan dijunjung tinggi dan rekonsiliasi pasti terjamin.
Ide E. Levinas dan J. Habermas tersebut mesti terakumulasi dalam sebuah forum formal untuk menghasilkan egalitarianisme hukum. Jawabannya harus tersistimatisasi dalam bentuk Undang-Undang formal yang tetap mengakomodasi tuntutan masyarakat adat dalam mengelolah wilayahnya demi kepentingan hayati dan pelestarian budaya yang sebenarnya adalah tanggung jawab negara.
Hak politik masyarakat adat mesti bersifat partisipatif. Maksudnya supaya para penguasa tidak seleluasa mengeksploitasi alam demi dalil pembangunan yang berwajah ganda dan melalui sebuah legal standing Undang-Undang, masyarakat bisa menjadi watchdog bagi gerakan-gerakan pemerintah yang berpotensi membohongi Undang-Undang.
Di sini, masyarakat harus membangun kekuatan akar rumput (The Power Of Civil Society) sebagai basis dasar menghadapi gemuruh raksasa dari atas sebab sejarah membuktikan bahwa kekuatan rakyat sipil dapat mengkudeta ekpansi kejahatan politik.
Tentang hal ini, masyarakat lokal mesti selalu diadvokasi oleh lembaga-lembaga sosial–para LSM ataupun organisasi sosial lainnya yang merasa bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat kecil, sumber daya lingkungan hidup dan kearifan lokal perlu mengawasi kinerja pemerintah, memberi pelayanan publik dan melakukan advokasi kontinu terhadap pelanggaran HAM; memperluas demokrasi dan desentralisasi ( Lisa Jordan dan van Tuijl, (eds.), 2009).
Hal ini akan mempermudah menemukan jalan tengah demi rekonsiliasi antara kekuatan “gajah dan semut.”