Oleh: Ambros Leonangung Edu
Dosen STKIP Santu Paulus Ruteng
Setelah dinobatkan sebagai provinsi dengan prevalensi stunting (gagal pertumbuhan otak dan fisik) tertinggi, kini NTT dililit masalah sampah yang menjadi-jadi.
Wajah ekologi NTT dapat dilihat dari dua ikonnya, yakni Labuan Bajo (destinasi internasional) dan Kupang (kota provinsi) dengan predikat 2 kota paling kotor. Di Kupang, seperti diungkapkan Gubernur NTT, Bapak Viktor Laiskodat, sampah berserakkan hampir di setiap jalan utama.
BACA JUGA: Memburu Sampah Birokrasi NTT
Sementara itu di Labuan Bajo, lanjut gubernur, merupakan “kota yang aneh”. Aneh karena tempat sampah berada di mana-mana melampaui persyaratan 50 meter tetapi sampahnya berserakan bahkan sudah mengotori laut.
Kota yang melahirkan pesona wisatawan internasional dan tahun lalu mendapatkan “adipura” (penghargaan kota bersih, sehat dan hijau) itu ternyata tidak diikuti semangat menata diri.
Data WWF Indonesia di Labuan Bajo menyebutkan kota tersebut memproduksi sampah setiap hari mencapai 112 meter kubik.
Labuan Bajo sebenarnya hanya sebuah cerita tentang minimnya manajemen kebersihan pada wilayah-wilayah dengan karakteristik fisik padat seperti pemukiman dan pasar.
Janganlah jauh-jauh, tetangganya Kabupaten Manggarai pada sejumlah pasar seperti di kota Ruteng “dihiasi” aneka sampah. Selera untuk membeli sayur yang segar harus berpapasan dengan aroma busuk di areal pasar.
Pertanyaannya, apa langkah konkret pemerintah untuk mengurangi sampah? Baru-baru ini, sikap berani bapak gubernur untuk menginstruksikan kepada para bupati/walikota agar menyelesaikan masalah sampah dalam waktu 6 bulan, patut diapresiasi.
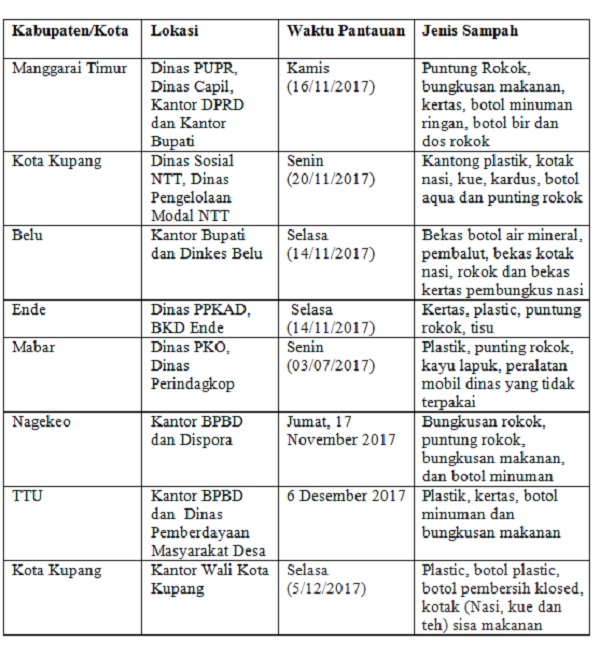
Gubernur berencana akan mengambil alih kepemimpinan kabupaten/kota jika selama 6 bulan bupati/walikota tertentu tidak dapat mengatasi masalah kebersihan itu.
Publik tentu berharap hal itu akan menjadi semacam pressure pemprov kepada bupati/walikota sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk membangun sinergisitas.
Koordinasi dan instruksi saja tidaklah memadai sampai semua pihak bahu-membahu, berkolaborasi dan berpartisipasi untuk mengurangi produksi dan volume sampah.
Langkah pemprov yang aktif berdiskusi dengan beragam level masyarakat akhir-akhir ini sebagai transformasi baru dalam gaya kepemimpinan yang mengutamakan kepemimpinan relasional ketimbang kepemimpinan posisional yang sudah out of date, adalah suatu pendekatan untuk membangun sinergisitas.
NTT yang dikenal dengan gudang para pemikir dan pekerja harus diikuti model kepemimpinan bottom-up, yang rela berbagi kekuasaan dan kekuatan ke pinggiran untuk mendapatkan respons profesional sehingga keputusan yang diambil bersifat akuntabel dan implikatif.
Pendekatan instruktif-birokratis yang top-down berdasarkan imajinasi sepihak kepala daerah tidak cukup efektif mengatasi sampah, seperti papan-papan larangan dan saksi membuang sampah yang dikeluarkan para pimpinan daerah.
Sampah adalah persoalan yang sangat rumit, kalau bukan dikatakan lingkaran setan, karena berkaitan dengan rupa-rupa sebab yang saling terkait: perilaku, budaya masyarakat, kualitas hidup yang rendah, atau IPTEK yang berorientasi pada gaya hidup konsumtif.
Oleh karena itu, solusinya tidak boleh sporadis dan spasial, tetapi harus menyeluruh, membangkitkan kesadaran dan semangat berpartisipasi, tidak hanya dan untuk hari ini tetapi juga hari esok. Tindakan yang dilakukan bukan lagi tindakan biasa, tetapi meminjam kata-kata Anang Sudarna, Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Jawa Barat, masalah sampah harus melibatkan “kekuasaan politik tingkat tinggi”.
Inilah yang semestinya disambut jika pemprov NTT dengan political will sudah menginisiasi gerakan pengurangan sampah. Sekiranya para pimpinan daerah menggerakkan mesin birokrasi dan kekuatan masyarakat untuk mengaktifkan kembali spirit cinta lingkungan. Pemberantasan sampah memerlukan sebuah gerakan besar hingga ke tingkat akar rumput.
Pertama, keluarga-keluarga perlu dijadikan sebagai bagian dari program-program pemerintah daerah.
Larangan pemerintah untuk membuang sampah harus dimulai dari fondasi dan sel terkecil masyarakat dan bangsa bernama “keluarga”.
Kalau keluarga sehat dan bersih, masyarakat dan bangsa pun ikut sehat dan bersih. Konstruksi dan restorasi masyarakat dan bangsa harus berdiri di atas fondasi keluarga-keluarga yang sehat.
Perubahan gaya hidup keluarga-keluarga masa kini sebagai ekses sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi konsumtif, membuat rumah tangga suka membeli dan menumpuk barang, yang berakibat pada menumpuknya sampah-sampah rumah tangga.
Belanja ibu-ibu rumah tangga ke pasar atau swalayan tanpa tas atau kantong di tangan karena berharap para penjual akan mempersiapkan plastik, merupakan logika para ibu rumah tangga yang keliru. Tidaklah heran jika banyak rumah tangga memiliki banyak sampah plastik.

Kedua, peran sekolah terhadap kebersihan lingkungan perlu ditata ulang. Subjek dan objek kurikulum dan pembelajaran adalah fenomena alam, fenomena sosial dan fenomena budaya yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Platform IPS SD adalah Geografi yang menggiring anak didik untuk berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya, atau platform MIPA SD adalah Biologi yang selalu berbicara tentang lingkungan hidup. Tema-tema pelajaran sejak SD kelas 1 hingga kelas VI sarat dengan latar belakang alam, sosial dan budaya.
Akan tetapi, sejauh ini, pelajaran-pelajaran di sekolah masih berupa pokok-pokok teoretis untuk dihafal dan direproduksi saat ujian berlangsung, sedangkan interaksi anak didik dengan alam yang menjadi tujuan utama pembelajaran bersifat artifisial dan instrumental belaka.
Belum lagi kita melihat kultur sekolah: sekolah-sekolah tidak terurus rapi, banyak lahan dibiarkan kosong tanpa tanaman bunga dan pohon pelindung, tanpa tempat sampah, tanpa pagar pengaman sehingga hewan-hewan leluasa masuk ke kompleks sekolah.
Untuk itu, sekolah-sekolah sebaiknya melakukan oto-kritik terhadap pendidikan ekologi secara luas untuk dioperasionalisasikan ke dalam pendidikan intra-kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
Ketiga, paradigma kita tentang sampah perlu diubah. Sampah yang berserakkan di mana-mana bukan untuk dihindari melainkan diurus, karena sampah bernilai ekonomis.
KSU Sampah Komodo di Labuan Bajo dan Bank Sampah Flores di Maumere adalah contoh-contoh kelompok yang concern terhadap bekas-bekas material sisa itu agar dapat dijadikan tas, alat permainan anak, dsb, untuk dipakai atau dijual.
Kelompok-kelompok pencinta alam harus digerakkan yang melibatkan setiap usia. Maka peran lembaga adat, pendidikan, pemerintah, dan agama harus dimaksimalkan.
Keempat, pola penanganan sampah pihak pemerintah selama ini diduga lebih banyak bekerja untuk “menangani” sampah sehingga lebih banyak mengurus hal-hal teknis-operasional seperti mengumpul, mengangkut, dan membuang/membakar, padahal yang lebih efektif untuk jangka panjang adalah “mengurangi” sampah, bukan menangani sampah.

Mengurangi sampah mau tidak mau harus bersentuhan dengan cara pandang dan perilaku melalui pendidikan dan sosialisasi untuk hidup hemat dan menjaga kebersihan yang melibatkan berbagai stakeholders dari pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, hingga RT/RW dan keluarga-keluarga.
Sampah di NTT adalah bagian dari masalah nasional. Saat ini salah satu perang terbesar adalah perang terhadap sampah. Sampah sumber penyakit, perusak ekologi tanah, pemicu ketidakseimbangan ekosistem, polusi dan pemanasan global serta mengganggu hubungan internasional.
Guernsey, salah satu kepulauan di Inggris, diceritakan diterpa sampah-sampah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbesar kedua dunia di mana menurut BPS sebesar 64 juta ton/tahun dan 3,2 juta ton di antaranya di buang ke laut.
Mari cinta Indonesia, cinta NTT, dengan bebas dari sampah!



