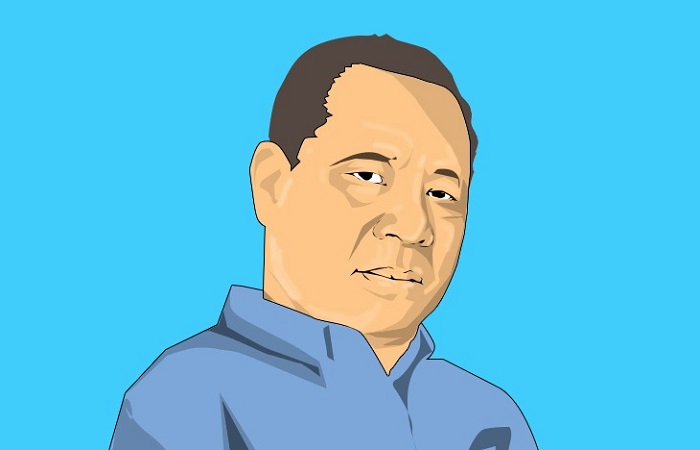Oleh: Anselmus Sahan
Dosen Universitas Timor, Kefamenanu, NTT
Hampir sebulan lalu, tepatnya Jumat, tanggal 24 April 2020, pejabat Satgas Covid-19 Propinsi Nusa Tenggara (NTT) dengan semangat mengumumkan bahwa saudara kita EA dinyatakan sudah sembuh dari sakit Corona. Atas dasar itu, wilayah kita dikategorikan “hijau”. Semua oang menyambutnya dengan senang sekali dan berbagai media memviralkan “rahmat” itu. Karena berita itu, banyak masyarakat beramai-ramai mulai melakukan aktivitasnya dan memenuhi jalan raya, tanpa peduli lagi terhadap protokol kesehatan.
Sayangnya, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat dan harus terhenti dengan datangnya informasi baru. Hari Kamis, 30 April 2020, tersiar secara luas berita bahwa ada 9 orang baru terpapar Corona. Sampai Selasa, 18 Mei 2020, tercatat sudah ada 71 warga NTT yang positif terpapar Covid-19 di NTT.
Berita ini sontak menghadirkan sebuah sinyalemen baru di tengah masyarakat bahwa wilayah ini akan memerah lagi. Tentu saja, berita ini menurunkan darah banyak orang ke kaki dan ketakutan akan virus ini mulai menganakkan tanya, “Kapan badai ini akan berlalu”.
Saya masih ingat, tanggal 28 April 2020 malam, seorang teman FB saya mengomentari postingan saya bahwa kita jangan terlalu cepat bangga dengan berita kesembuhan pasien perdana COvid-19, yaitu EA. Sebab, menurut dia, masih banyak orang yang tergolong orang tanpa gejala (OTG). Harapannya, hasil pemerksaan leb terhadap OTG dan kategori lainnya, akan segera diungkapkan.
Saling Menuduh
Di tengah meningkatnya jumlah orang terpapar corona di NTT, ada begitu banyak tudingan, baik di media massa online maupun cetak. Setidaknya ada empat tudingan yang seperti mengalami ekskalasi tinggi dan akselerasi sangat cepat, dari hari ke hari.
Pertama, sumber virus. Jika sejak awal, media dan massa mengetahui bahwa virus jahat berasal dari China, dan menyebar ke seluruh dunia, melalui orang-orang yang melakukan kontak dengan orang di sana, kini, di daerah kita, sumber virus dibawa oleh sekelompok orang yang mengikuti kegiatan keagamaan di Sulawesi dan Jawa.
Kedua, sembunyi diri. Orang-orang yang datang dari Sulawesi dan Jawa, setiba di tempat tinggalnya, telah melakukan interaksi dengan anggota keluarga lain. Secara tidak sadar, ikatan sosial itu ternoda oleh hadirnya virus Corona di dalam tubuh mereka.
Entah diketahui atau tidak, mereka sepertinya menyembunyikan diri dari upaya pemeriksaan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghindarkan diri sikap kooperatif terhadap petugas kesehatan.
Ketiga, berontak dengan stigma virus. Ketika mencuat informasi bahwa beberapa orang yang datang dari kedua pulau tadi terpapar virus corona, di situ baru sebagian berusaha untuk mengecek kesehatannya.
Sementara di tengah masyarakat telah terjadi stigma, sebuah cap social yang dialamatkan kepada mereka sebagai sumber virus. Diterima atau tidak, stigma ini terus menggelinding dari hari ke hari dan seperti sebuah embrio, yang pada akhirnya melahirkan sinisme baru terhadap mereka.
Terakhir, saling tutup wilayah. Akibat dari kurangnya koordinasi, perbatasan antarwilayah Manggarai Barat dengan Manggarai saling berjuang untuk mengisolasi masyarakatnya dari serangan virus. Isolasi ini melahirkan pemblokiran di batas wilayah antara kedua kabupaten tersebut. Patut disyukuri, masalah itu telah diselesaikan secara baik. Jika mengambang, tentu saja, Manggarai, yang tidak punya rumah sakit rujukan COvid-19 akan mengalami kesulitan dalam menangani pasiennya.
“Bisul” Corona
Dari berbagai pemberitaan terlihat jelas bahwa jumlah OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan) terus meningkat.
Jumlah ini adalah sebuah borok atau bisul yang dimulai sejak dua minggu lalu mulai memecah dan entah sampai kapan akan terpecah terus. Ini sebuah situasi di mana, hasil lab yang memeriksa ketiga kategori orang di atas belum semuanya diungkap oleh Pusat.
Jika peningkatan jumlah OTG dan ODP saja, misalnya, harus disandingankan dengan sebuah bisul, atau ‘bisul Corona’, maka ia tentu saja akan pecah dan melahirkan orang baru yang terpapar Corona lagi.
Jika orang baru terpapar itu telah melakukan kontak dengan begitu banyak orang, maka bisul-bisul baru bakal berjamur lagi di mana-mana.
Selanjutnya, jika orang tersebut memiliki perilaku yang sama yaitu tidak membatasi pergaulannya selama ini, maka bukan tidak mungkin hal itu akan menyulitkan para petugas untuk melacak penyebarannya. Ini menunjukkan bahwa perkembangbiakkan bisul baru akan selalu memiliki potensi.
Bisul Corona baru bisa juga bersumber dari anggota keluarga yang sudah terpapar virus Corona, namun tidak mau memeriksakan dirinya ke Posko Covid-19 atau ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
Dari berbagai pemberitaan, terlihat bahwa klaster, seperti klaster Banyuwangi, Magetan, Sukabumi, dan Goa, ini amat sulit dilacak karena masyarakat “terlalu yakin” pada kesehatan dirinya. Mereka terlalu percaya pada dirinya bahwa mereka bebas dari gejala-gejala Corona.
Yang tidak boleh dilupakan dan dianggap remeh juga ialah bahwa jika gelombang puluhan ribu orang Indonesia di luar negeri balik ke tanah air, bukan tidak mungkin, ‘bisul’ baru menyertai mereka. Itu berarti bahwa ancaman baru harus selalu siap dihadapi.
Di sisi lain, penimbunan jumlah bisul baru kemungkinan besar akan bersumber dari sekelompok masyarakat, yang sudah terkategori OTG atau ODP, yang baru datang dari zona merah.
Terkait kelompok ini, kita bisa saksikan atau baca di berbagai media bahwa ada di antara mereka yang enggan dikarantina dan bahkan, ada yang menginginkan untuk mengkarantina sendiri di rumah. Hal ini tentu saja akan selalu menyulitkan para petugas kesehatan untuk memantau keadaan kesehatannya.
Belum lagi tempat tinggalnya berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan, maka bertambahlah beban yang petugas kesehatan harus pikul.
Bukan tidak mungkin, kondisi tempat tinggal yang jauh dan jalan rusak ke karantina mandiri, menyebabkan petugas kesehatan sendiri terpapar virus Corona. Kondisi ini membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu meringankan beban petugas kesehatan.
“Stigma Sosial”
Jika “bisul” Corona terkait dengan OTG atau ODP, maka “stigma” Corona terkait dengan sekelompok orang yang datang dari wilayah zona merah atau setiba di daerahnya terpapar Corona.
Kita akui, mereka telah diperiksa dari satu tempat ke tempat lainnya sebelum tiba di wilayahnya masing-masing di NTT. Buktinya, mereka diberi selembar kertas yang berisi tentang protokoler kesehatan yang telah mereka lalui dan keadaan dirinya. Namun, kertas itu tidak pernah menyatakan bahwa mereka bebas dari gejala.
Sebagaimana kita ketahui, masa inkubasi virus ini akan muncul antar 5-14 hari, bahkan ada yang lebih dari masa tersebut. Di sisi lain, pemeriksaan kondisi kesehatan mereka harus dikirim ke Jakarta dan itu butuh waktu lama untuk memperoleh hasilnya. Dalam kasus baru Covid-19 di NTT, yaitu 9 orang sebelumnya, terlihat jelas bahwa sampel mereka telah dikirim ke Jakarta sekitar sebulan lalu dan baru Kamis sore (30 April 2020), hasil pemeriksaan lab diperoleh.
Kemajuan teknologi seperti handphone dan televisi telah membuat masyarakat sangat peka dengan pemberitaan virus ini dan bahkan sudah membangun sebuah “stigma” bahwa orang dari luar kampungnya adalah pembawa virus.
Stigma itu terdorong oleh pemberitaan yang mereka peroleh dan mengandung “bisul” yang bisa pecah di mana saja dan mengancam jiwa dan raga siapa saja. Di satu sisi, para pendatang baru itu adalah anggota keluarga kita, tapi di sisi lain, mereka di-‘stigma’ sebagai sumber Corona.
Apa sebenarnya yang salah? Ada dua hal. Pertama, disiplin. Dalam hal ini, kita semua harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan pemerintah. Jika dilarang pulang kampung atau mudik, ya, ikuti itu, demi kebaikan dan kesehatan kita bersama di hari-hari selanjutnya. Sepertinya, masyarakat telah dihantui oleh “setan” Corona, yang menggeneralisasi bahwa semua pendatang telah terpapar Corona.
Kedua, taat. Jika terpaksa pulang, Anda harus taat untuk dikarantina selama 14 hari. Entah mandiri atau umum, wajib bagi mereka untuk mengikutinya. Tidak perlu lari dari rumah karantina atau memarahi petugas. Ini bertujuan untuk memudahkan petugas kesehatan memantau kondisi kesehatan mereka. Apalagi selama di karantina, Pemerintah menyiapkan segala kebutuhan mereka.
Ketiga, berani terbuka. Orang-orang yang telah terpapar Corona dari beberapa klaster di atas jelas telah berinteraksi dengan keluarganya sendiri dan relasinya. Kelompok ini diharapkan untuk berani membuka diri dan secara sukarela melakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak perlu menutup diri dan berharap bahwa penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya.
Dan keempat, Patuhi Protokol Kesehatan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak orang yang mengabaikan protokol ini. Keadaan ini memang tidak mengenakkan siapa saja. Ini juga telah merusak tatanan kehidupan bersama dan penghormatan kita pada Allah, Sang Pecipta.
Selain itu, ia telah membuat banyak orang di-PHK dari tempat kerjanya atau memaksa kita untuk menunda semua yang ‘enak’, seperti jalan-jalan ke mall atau belanja ke luar negeri.
Harus Kerja Sama
Stigma tak bisa dihindari. Jumlah pasien terpapar Corona kian meningkat. Menghadapi kenyataan pahit ini, kita harus tunduk, taat, dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, yaitu antara lain cuci tangan, gunakan masker, dan jauhi keramaian. Jika ini kita langgar, kita sendiri sama seperti ‘bisul’ bagi orang lain dan siap di’stigma’ sebagai biangkerok Corona di tengah keluarga dan masyarakat kita.
Kita juga harus mampu membangun kerja sama yang baik untuk menghadapi virus ini. Antara orang yang datang dari daerah merah dengan keluarga, dengan petugas kesehatan dan dengan masyarakat lainnya sehingga virus ini tidak menjalar ke mana saja, mengikuti perjalanan badan manusia yang terpapar.
Masalah berat sudah ada di depan mata kita. Virus Corona sudah ada di tengah kita. Saudara-saudari kita yang terpapar sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita kita mendoakan agar mereka lekas sembuh. Kita sendiri, yang masih sehat, harus dengan sadar mengikuti protocol kesehatan pemerintah.