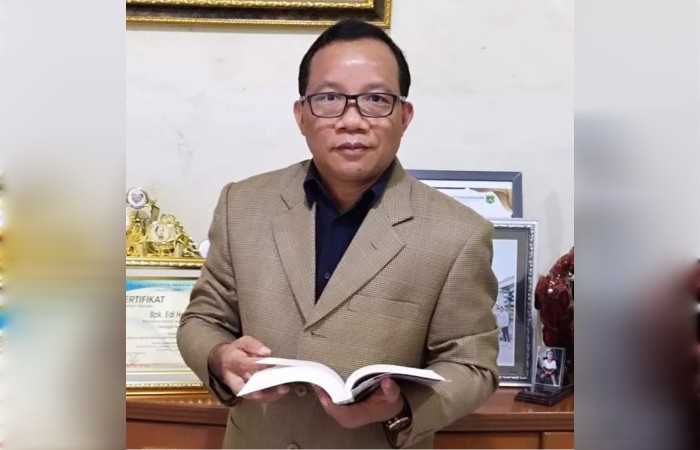Oleh: Pater Darmin Mbula, OFM
Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK)
Jejaring hidup bahagia berkelanjutan merupakan konsep yang menggabungkan keseimbangan antara kesehatan, lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna.
Dalam ilmu IPA, pendekatan ini selaras dengan pemahaman ilmiah tentang ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan alam agar manusia dapat hidup sehat dan berkelanjutan.
Peran dokter sangat krusial dalam jejaring ini, karena mereka tidak hanya menangani penyakit, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat melalui edukasi, pencegahan, dan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, aspek kemanusiaan menjadi landasan moral dan etis, mengingatkan bahwa setiap tindakan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun profesi medis, harus berorientasi pada nilai empati, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Kolaborasi antara ilmu pengetahuan, profesi kesehatan, dan nilai-nilai kemanusiaan inilah yang membentuk jejaring hidup bahagia yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan.
Profesi kedokteran sejak lama dipandang sebagai profesi mulia yang berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan, dan pembentukannya telah disiapkan sejak jenjang sekolah dasar dan menengah melalui pengembangan minat serta pemilihan jurusan IPA, yang kemudian dilanjutkan ke pendidikan tinggi dan spesialisasi di bidang kedokteran.
Proses panjang ini mencerminkan dedikasi untuk mencetak tenaga medis yang tidak hanya unggul secara ilmiah, tetapi juga beretika dan humanis dalam menjalankan tugasnya.
Namun, citra luhur profesi ini kini tercoreng akibat ulah segelintir oknum dokter yang terlibat dalam tindakan kejahatan kemanusiaan, seperti kekerasan seksual terhadap pasien, yang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap sumpah profesi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Kejadian-kejadian ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi medis, tetapi juga menjadi alarm penting bagi dunia pendidikan dan lembaga profesional untuk memperkuat pembinaan karakter dan etika sejak dini, agar profesi dokter benar-benar kembali menjadi teladan dalam menjunjung tinggi martabat dan keselamatan manusia.
Keluarga
Ketika seorang dokter melakukan kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan, publik sering kali bereaksi dengan mengejutkan dan langsung mempertanyakan latar belakang pribadi pelaku—seperti keluarganya, pendidikannya, dan agamanya.
Hal ini terjadi karena profesi dokter selama ini dipandang sebagai simbol integritas moral, kepandaian, dan kemanusiaan.
Harapan masyarakat terhadap dokter sangat tinggi; bukan hanya sebagai penyembuh secara fisik, tetapi juga sebagai figur yang dipercaya menjaga kerahasiaan, keamanan, dan martabat manusia.
Ketika ada dokter yang justru melanggar nilai-nilai tersebut secara ekstrem, publik mengalami semacam “kekecewaan kolektif” dan berusaha mencari penjelasan: apakah keluarga yang membesarkannya gagal menanamkan nilai etika? Apakah sistem pendidikan tidak berhasil membentuk karakter? Apakah agama yang dianutnya tidak cukup membimbing moralnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul sebagai refleksi atas kegagalan struktural yang lebih luas—bukan hanya soal individu, tapi juga sistem sosial dan budaya yang membentuknya.
Masyarakat merasa perlu mencari akar penyebab dari perilaku menyimpang itu, karena sulit diterima jika seorang yang dididik selama bertahun-tahun dengan ilmu dan nilai-nilai luhur bisa melakukan perbuatan yang sedemikian jahat.
Dalam konteks ini, publik tidak hanya melihat peristiwa tersebut sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kegagalan moral yang dalam.
Oleh karena itu, pertanyaan tentang keluarga, pendidikan, dan agama menjadi semacam upaya memahami bagaimana sosok yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan.
Core Values
Dalam denyut kehidupan yang terus mengalir, nilai-nilai luhur ibarat akar yang menjejak dalam tanah jiwa—menguatkan batang manusia agar tak goyah di tengah terpaan zaman.
Di sinilah keluarga memainkan peran paling mula, tempat anak pertama kali belajar tentang cinta tanpa syarat, hormat pada sesama, dan tanggung jawab yang tak kasat mata.
Orang tua, dalam tutur lembut dan sikap yang dicontohkan, menanamkan benih integritas, kejujuran, dan empati.
Nilai-nilai itu tumbuh perlahan, menyatu dengan darah dan napas anak-anaknya, hingga suatu hari mereka berjalan sendiri di dunia, membawa bekal yang tak tampak, tapi menentukan arah.
Lalu pendidikan menyambut mereka, bukan sekadar dengan pelajaran angka dan fakta, melainkan dengan harapan bahwa sekolah menjadi taman karakter, bukan sekadar pabrik nilai akademik.
Di ruang kelas, guru bukan hanya penyampai ilmu, tapi penjaga nilai—yang lewat kejujurannya, disiplin, dan kepeduliannya, memperkuat akar yang telah ditanam keluarga.
Di sinilah integrasi nilai menemukan ruang kedua, tempat anak belajar berpikir kritis sekaligus merasa dengan hati.
Pendidikan sejati bukan hanya menyiapkan anak menjadi cerdas, tapi menjadikannya manusia yang utuh—yang tahu bahwa kecerdasan tanpa nilai bisa menjadi bumerang bagi kemanusiaan.
Agama, sebagai pelita batin, hadir melengkapi. Ia tak sekadar ritual atau hafalan dogma, melainkan sumber kearifan moral yang menuntun manusia dalam kesendirian dan keramaian. Agama meneguhkan bahwa hidup bukan hanya soal diri sendiri, tapi tentang kebermaknaan untuk sesama.
Dalam profesi kemanusiaan seperti dokter, nilai-nilai dari keluarga, pendidikan, dan agama bertemu, membentuk pribadi yang dipercaya tak hanya karena gelar, tetapi karena jiwanya bersih dan tindakannya tulus.
Maka jika nilai-nilai ini benar-benar hidup dan menyatu dalam tiap tahap pembentukan manusia, kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang diminta, melainkan anugerah yang hadir dengan sendirinya.
Pendekatan Multidisiplin
Meskipun seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, mendapat pendidikan tinggi, dan tumbuh dalam lingkungan yang religius, kenyataannya masih ada kemungkinan ia melakukan kejahatan kemanusiaan seperti kekerasan seksual.
Dalam ilmu neuroscience, otak manusia sangat kompleks dan pembentukan perilaku tidak semata-mata bergantung pada lingkungan luar, tetapi juga pada struktur dan fungsi otak itu sendiri.
Misalnya, gangguan pada prefrontal cortex—bagian otak yang mengatur kontrol diri, pengambilan keputusan moral, dan empati—dapat menyebabkan seseorang bertindak impulsif atau kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang lain, meskipun secara kognitif ia tahu perbuatannya salah.
Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang tumbuh dalam lingkungan positif, kerentanan biologis dalam sistem saraf bisa tetap memengaruhi kecenderungan perilaku menyimpang.
Ilmu kognitif modern juga menyoroti pentingnya proses mental seperti persepsi, ingatan, dan penalaran moral. Seseorang bisa saja memiliki pemahaman agama dan pendidikan tinggi, tetapi jika proses interpretasi atau penyusunan nilai dalam pikirannya mengalami bias atau distorsi kognitif, ia bisa meyakini pembenaran yang keliru atas tindakan buruknya.
Misalnya, ia mungkin menganggap kekuasaannya sebagai dokter memberi “hak” tertentu atas tubuh orang lain—sebuah bentuk kognisi yang menyimpang dari nilai etika dan kemanusiaan.
Distorsi semacam ini bisa tumbuh dari pengalaman pribadi yang tak diketahui publik, trauma masa lalu yang tersembunyi, atau bahkan paparan konten digital yang memperkuat normalisasi kekerasan, terutama di era digital dan AI.
Dalam bidang ilmu perilaku, para ahli mencatat bahwa perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh nilai yang dianut, tetapi juga oleh konteks sosial dan situasional.
Misalnya, kekuasaan yang besar tanpa pengawasan, budaya instansi yang permisif terhadap penyimpangan, serta lemahnya sistem pelaporan korban bisa menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan untuk menyalahgunakan posisi, bahkan oleh orang-orang yang sebelumnya tampak berintegritas.
Ini disebut sebagai efek situasional, di mana tekanan, kesempatan, dan budaya sekitar lebih kuat pengaruhnya daripada nilai pribadi.
Dalam konteks ini, sistem harus disiapkan tidak hanya untuk membentuk individu baik, tetapi juga mencegah kondisi sosial yang membuka celah kejahatan.
Di abad kecerdasan buatan (AI), dimensi baru muncul dalam studi perilaku manusia. AI kini bisa mengenali pola perilaku menyimpang, memperkirakan risiko, dan memberi peringatan dini berdasarkan data—namun semua itu tak akan berguna jika tidak diintegrasikan dengan kebijakan dan pendekatan yang mengedepankan etika.
Justru tantangan di era ini adalah bagaimana manusia tetap memiliki otonomi moral di tengah derasnya informasi dan kemungkinan manipulasi digital.
Seseorang bisa terlihat taat dan cerdas secara luar, tetapi menyembunyikan sisi gelap perilakunya melalui kemampuannya memanipulasi sistem, bahkan AI sekalipun.
Maka, penguatan nilai harus dilakukan tidak hanya di tingkat individu, tetapi juga melalui pengawasan berbasis teknologi yang etis dan sistem pendidikan yang membekali kesadaran diri mendalam.
Kesimpulannya, meskipun seseorang tumbuh dalam keluarga yang baik, mendapat pendidikan tinggi, dan hidup religius, tidak ada jaminan absolut ia akan terbebas dari kecenderungan menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan.
Ilmu otak, ilmu kognitif, dan perilaku menunjukkan bahwa banyak faktor tersembunyi—baik biologis, psikologis, maupun sosial—yang saling bersinergi membentuk perilaku seseorang.
Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak bisa hanya fokus pada pendidikan dan nilai, tetapi juga harus melibatkan pendekatan multidisiplin, deteksi dini, penguatan sistem sosial yang sehat, serta pemanfaatan teknologi secara bijak untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan di era yang semakin kompleks ini.