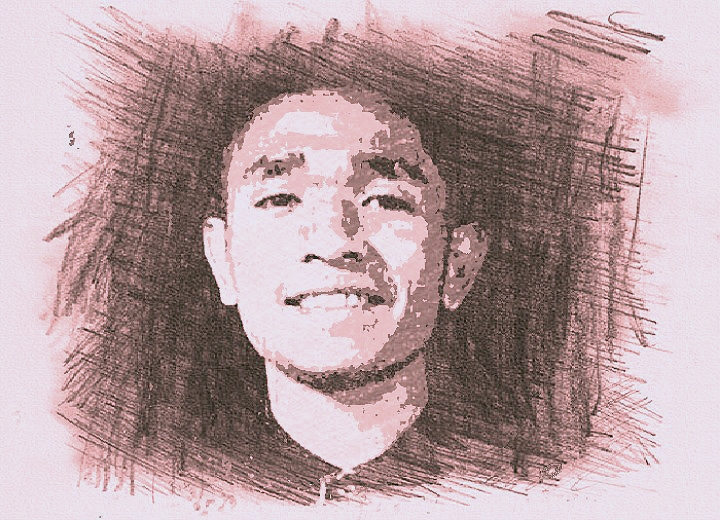Oleh: Rian Odel
Anggota KMK STFK Ledalero, Maumere
Bahasa K(e)dang di Lembata tergolong bahasa austronesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kedang, diakses pada 1 Januari 2019) dan dipakai oleh masyarakat Kedang, Lembata, Flores NTT (Bdk. Yohanes Orong, ms., 2014: 36).
Robert H. Barnes dalam bukunya, Kedang: A Study of the Collective Thought of an Eastern Indonesian People, menyebut bahasa Kedang lebih tepat dianggap sebagai satu bahasa sendiri, dan bukan merupakan dialek dari salah satu bahasa di sekitarnya.
Prof. Karl van Trier juga pernah melakukan penelitian atas prakarsa para misionaris memperkenalkan penulisan huruf q untuk melafalkan bunyi glottal stop (tanda hamzah ‘) dalam bahasa Kedang.
Selain itu, lafal k sering dipakai, misalnya ‘Edang, diganti menjadi Kedang atau nama-nama tempat seperti ‘Ali’ur menjadi Kalikur, ada yang menghilangkan lafal tersebut, sebagaimana terjadi pada penyebutan nama Bale’uring, menjadi Balauring, Aliur’oba menjadi Aliuroba.
Bahkan ada yang menggantikanya dengan ng seperti Dolulolo’ menjadi “Dolulolong” (Lamaholot), Wowon menjadi “Wowong”, Weilolon menjadi “Weilolong”, Leubatan menjadi “Leubatang”, Leuwayan menjadi “Leuwayang”.
Glottal stop itu sangat banyak, maka van Trier memperkenalkan huruf q untuk melafalkannya. Misalnya kalimat: Aduh anakku disebut Ero’ ko’ ana’, tetapi penulisannya menjadi Eroq koq anaq (https://molansio.wordpress.com/category/bahasa-kedang/,diakses pada 1 Januari 2019).
Ursula Samely telah menerbitkan sebuah kamus bahasa Kedang. Judulnya: A Dictionary of the Kedang Language:Kedang-Indonesian-English (2013).
Pesan Moral
Tutu’ nanang edang artinya “berbicara bahasa kedang.” Tutu’ artinya “berbicara”, Nanang artinya “menganyam”. Jadi bisa diterjemakan berbicara artinya menganyam bahasa/pesan yang diungkapkan oleh orang lain.
Hal ini mengindikasikan bahwa ketika seorang berbicara harus ada pihak lain yang mendengarkan dengan cara menganyam isi pembicaraan itu dalam ingatannya atau mengikat (menganyam) dalam hatinya, seperti yang ditemukan dalam pepatah: Amo tutu’ puli, ana’ pau panang “bapa berbicara-mewariskan; anak menelusuri kembali.”
Makna terdalam dari ungkapan Tutu’ Nanang mengafirmasi bahwa menghargai pembicaraan orang lain adalah hal yang mulia.
Ketika seorang berbicara, pihak pendengar diwajibkan untuk menyimak isi pembicaraan itu karena terselip pesan-pesan penting.
Menurut Edward Sapir B. Lee sebagaimana yang dikutip Yohanes Orong, bahasa yang dipakai selalu memengaruhi kebudayaan manusia (Ibid., hlm. 45).
Jika ditelusuri, sebenarnya ungkapan ini sangat bermakna bagi kehidupan sosial-budaya sekaligus menjadi sebuah kritikkan atas relasi komunikatif yang selalu kita alami atau praktikan.
Mental mendengarkan pembicaraan orang lain tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan yang dipelihara khususnya oleh generasi muda. Oleh karena itu, tutu’ nanang mengajak kita untuk memerhatikan etika ketika berbicara maupun mendengarkan pembicaraan orang lain. Misalnya dalam lingkungan sekolah, ibu guru tutu’, anak murid nanang (menganyam pesan dalam hati dan ingatan), di rumah, orangtua tutu’ anak-anak nanang sehingga terjalin suatu keharmonisan baik dalam berbicara maupun proses untuk merealisasikan isi pembicaraan itu.
Istilah – istilah bermakna
Biasanya istilah – istilah bermakna selalu dilihat apa adanya atau tampak seperti tidak bermakna tetapi setelah ditelusuri terbukti ada nilai atau pesan-pesan.
- Buren bahu’ dan bahu’ buren.
Buren bahu’, buren artinya “benci”, Bahu’ artinya “mabuk”. Buren bahu’ artinya “sangat benci” atau membenci seperti orang mabuk.
Contohnya, Nuo buren bahu’ rasa ne: “dia sangat membenci (orang lain) yang berujung pada marah /beke’. Jadi, jika seseorang membenci sesamanya akan disebut buren bahu’ dan berujung pada beke’ atau marah. Tetapi nilai yang hendak dilihat ialah orang kedang secara implisit melarang kita untuk marah.
Hal ini dapat dilihat dalam sebutan buke’ beke’ “orang yang marah adalah orang bodoh.” Buke’ artinya bodoh ; beke’ artinya marah; orang yang sudah marah, rasionalitasnya lumpuh.
Kesimpulannya, walaupun kita membenci sesama tetapi dilarang menghasilkan kemarahan karena akan berujung pada adu fisik atau awe we’ yang juga berarti merebut badan sendiri atau menghancurkan badan sendiri.
Memukul orang lain berarti juga bahwa kita sedang memukul diri sendiri karena orang lain adalah juga gambaran akan diri kita sendiri.
Bahu’ buren
Artinya “mabuk berlebihan”. Bahu’ artinya “mabuk”, buren artinya “membenci”. Bahu’ buren mengartikan orang yang mabuk berlebihan atau tidak sadarkan diri sehingga seenaknya mengganggu orang lain, memukul orang dan menghancurkan barang orang atau membenci orang (buren). Jadi bahu’ buren mengartikan orang yang mabuk berlebihan karena terlalu banyak mengonsumsi tuak atau arak sehingga ada sebutan tua’ tahi’.
Tua’ berarti “tuak” tahi’ berarti “laut”. Tua’ tahi’ merupakan sebuah gambaran analogis jumlah minuman keras. Jika dalam suatu pesta terdapat banyak minuman keras akan disebut tua’ tahi’ “tuak yang sangat banyak seperti laut”.
Orang mabuk pasti selalu identik dengan kebencian atau kemarahan dan mungkin akan sampai kepada adu fisik. Jika demikian, lebih baik jangan mabuk atau kara bahu’.
- Tiwa we’
Tiwa artinya “membuang”, we’ artinya “badan”. Tiwa we’ diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi aborsi. Nilai moral yang perlu kita petik ialah praktik aborsi pada dasarnya negatif.
Mempraktikan aborsi berarti sama dengan membunuh diri sendiri/membuang tubuh sendiri. Ibu yang melakukan aborsi sebenarnya ia sedang membunuh dirinya sendiri.
- Bongan we’
Bongan we’ berarti “berkumpul atau musyawarah untuk mufakat”. Hal ini mengandaikan ada masalah yang hendak diselesaikan bersama dalam suatu pertemuan.
Bongan artinya “leher” dan we’ artinya “badan”. Bongan atau leher adalah penghubung antara kepala (nalar/pikiran/otak) dengan dada (hati/perasaan).
Artinya dalam suatu pertemuan, pikiran dan hati atau perasaan harus digunakan secara seimbang untuk menyelesaikan suatu masalah; bukan hanya menggunakan otak melainkan juga perasaan kita.
- Atedi’en daten
Atedi’en diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti manusia atau orang ( ate artinya “orang” di’en artinya “baik”) sehingga atedi’en artinya “orang baik sama seperti dalam bahasa lamaholot yaitu ata diken (Budi Kleden, 2008).
Misalnya, suo atedi’en ape ya? Terjemahan bebasnya ialah “Mereka orang (baik) apa atau berasal darimana?”, jawabannya, suo atedi’en edang ya “mereka orang kedang”, atau untuk pengingkaran bisa dijawab hanya dengan satu huruf yaitu i yang berarti “tidak tahu.”
Daten berarti “jahat, rusak, busuk”, sehingga atedi’en daten merupakan sebuah ungkapan untuk menyebut orang yang bertingkah laku jahat.
Nilai terdalam yang perlu didalami dalam konsep atedi’en daten ialah esensi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik (di’en). Selain kebaikan, terdapat pula sisi negatifnya (daten) sehingga disebut atedi’en daten ( pencuri, pembunuh, perampok juga memiliki kebaikan dalam diri).
Konsep ini secara implisit hendak menjelaskan tentang sisi baik dan buruk yang selalu ada dalam diri manusia. Sejahat-jahatnya seorang manusia, pasti juga memiliki kebaikan dalam diri.
Masalah yang sering kita temukan ialah kecenderungan kita untuk melihat keburukan atau kejahatan orang lain tanpa melihat kebaikannya. Misalnya dalam dunia politik, para lawan politik selalu menyerang “Musuhnya” dari sisi jahat tanpa melihat atau mendukung kebaikan yang pernah dibuat.
Kecenderungan kita ialah melihat keburukan orang padahal dalam dirinya ada kebaikan sehingga disebut Atedi’en daten bukan atedaten.
Pesan untuk kita ialah harus lebih dahulu melihat kebaikan sesama sebelum menilai keburukannya sebab kata baik (di’en) lebih dekat dengan kata ate daripada kata daten.
Secara ontologis, ilmu metafisika mengafirmasi bahwa keberadaan manusia adalah sebagai makhluk yang baik, keburukan adalah kekurangan dari kebaikan itu; hanya Tuhan yang baik secara sempurna. Jadi dalam bahasa Kedang, orang jahat disebut atedi’en daten “orang baik dan jahat.”
- A tutu’ tin tehe’
Istilah ini selalu dipakai oleh orang tua atau pemimpin suku dalam memulai suatu pertemuan.
A berarti “makan”, tutu’ berarti “berbicara”, tin “minum”, tehe’ “menasihati”.
A tin berarti makan minum (walaupun sebenarnya hanya berarti makan). Misalnya, te a tin te! (ajakan untuk makan dan minum). Kata te berati “kita” seperti dalam bahasa indonesia , mari kita makan! Frasa kita makan secara impilisit ada dalam kalimat te a tin te.
A “makan”, tin “minum”, te pada awal kalimat berarti “kita”; pada akhir kalimat berarti penegasan. Jadi terjemahan lurusnya, kita makan karena makanan ini milik kita. Sebutan milik kita sama dengan kata te pada akhir kalimat te a tin te!
Contoh lain, sio ne’e lala’ no’o we? “siapa punya nasi ini e?” Jawabannya te te’e ne yang berarti milik kita. Te “kita”, te’e “milik kita”, ne sama seperti logat le dalam kebiasaan orang Lewoleba. Nasi itu kami punya le (selalu ada penegasan di belakang kalimat). Te’e/ ke’e “ milik kita/kami”, se’e “milik mereka”, me’e “milik kamu jamak”. ko’o “milik saya”, ne’e “milik dia”, mo’o “milikmu.”
Tutu’ berarti berbicara dalam arti umum tetapi jika ditambahkan kata tehe’ berarti nasihat. Tutu’ tehe’ “berbicara untuk menasihati”, sehingga a tutu’ tin tehe’ memiliki dua makna yaitu selain kegiatan makan minum (bersama) dijadikan juga momen untuk saling menasihati.
Nilai positif yang perlu didalami ialah pesan moral bagi kehidupan sosial khusunya ketika terjadi keretakan baik dalam keluarga, suku, maupun masyarakat umum, momen makan bersama adalah kesempatan berharga untuk saling menasihati sekaligus merekonsiliasi keretakan.
Selain mengisi perut yang sedang kehabisan makanan, hati dan pikiranpun diisi dengan nasihat –nasihat baik yang mencerahkan relasi sosial.
Perempuan dalam Bahasa Kedang
Perempuan dalam bahasa kedang disebut are’ rian. Kata are’ mungkin berasal dari nama seorang perempuan dalam legenda purba kedang yang bernama are’ (putri dari Naran Nuhan).
Ia menjelma menjadi makanan bagi kehidupan manusia (Bdk. Cerita Tonu Wujo versi Lamaholot), sedangkan Rian berarti “pemimpin, raja, atau besar”.
Mengapa perempuan selalu disebut rian? Jawabannya mungkin karena perempuan adalah sumber kehidupan baik makanan dalam versi legenda maupun yang melahirkan kehidupan, sehingga kemudian seorang istri disebut we’ rian “badan besar.”
Hal ini menggambarkan bahwa tubuh perempuan adalah sumber bagi kelahiran manusia baru. Oleh karena itu, dalam bahasa kedang, perempuan disebut “yang besar”.
Kata rian dalam budaya kedang sebenarnya dipakai untuk menyebut orang-orang terhormat seperti raja atau pemimpin negara, maka sebenarnya perempuan juga memiliki status yang sama sebagai orang terpandang bahkan “lebih” daripada “laki-laki”.
Tindakan pemerkosaan terhadap perempuan merupakan praktik terharam dalam budaya kedang karena perempuan adalah sumber makanan bagi kehidupan dan yang bisa melahirkan manusia baru.
‘Surga ada di telapak kaki ibu’ sebenarnya sesuai dengan penyebutan perempuan dalam budaya kedang yang melihat perempuan sebagai “orang besar”, terpandang bahkan sebagai surga kehidupan yaitu rahim ibu.
Are’ rian berbeda dengan are’ weri’ (gadis/ perempuan muda). Namun, baik gadis maupun yang sudah bersuami terangkum dalam sebutan are’ rian.
Seorang bayi perempuan tetap disebut are’ rian karena ungkapan ini mengandung makna perempuan secara umum hanya para gadis yang bisa disebut are’ weri’. Penyebutan are’ weri’ hanya mau membedakan perempuan yang sudah bersuami dengan yang masih mencari pasangan.
Satu Bahasa Beda Logat
Orang kedang diakui memiliki satu bahasa sendiri namun di antara mereka terdapat perbedaan logat maupun penekanan. Misalnya, kata kita dalam bahasa kedang bagian pedalaman ialah te atau ke tetapi sebagian orang pesisir akan menyebut ete atau eke.
Kata ‘tidak’ versi pedalaman ton, pesisir tong, kata baru, werun, pesisir menjadi werung. Bahkan beberapa perbedaan; jambu mete ada yang menyebutnya lumasawa, tetapi juga bisa taluma, beringin disebut gudi’ / beu dan masih banyak lagi.
Menurut para narasumber, sebenarnya sejak dahulu kala semua orang kedang menggunakan bahasa yang sama tetapi sejak masuknya Islam, dialek mulai terkontaminasi dengan kebiasaan dari luar,misalnya dari Lamahala, Makasar, Buton dan bahkan Melayu (sekitar abad ke 18).
Catatan Penulis: sumber ilmiah tentang bahasa kedang sangat terbatas sehingga tulisan ini merupakan sebuah analisis untuk mendalami bahasa Kedang.